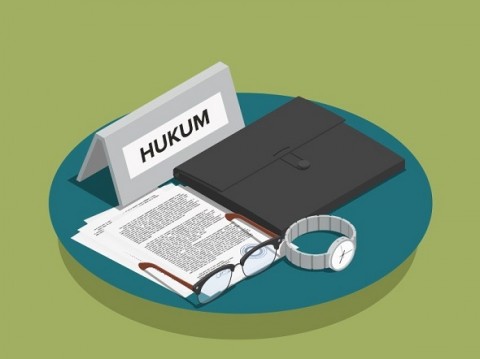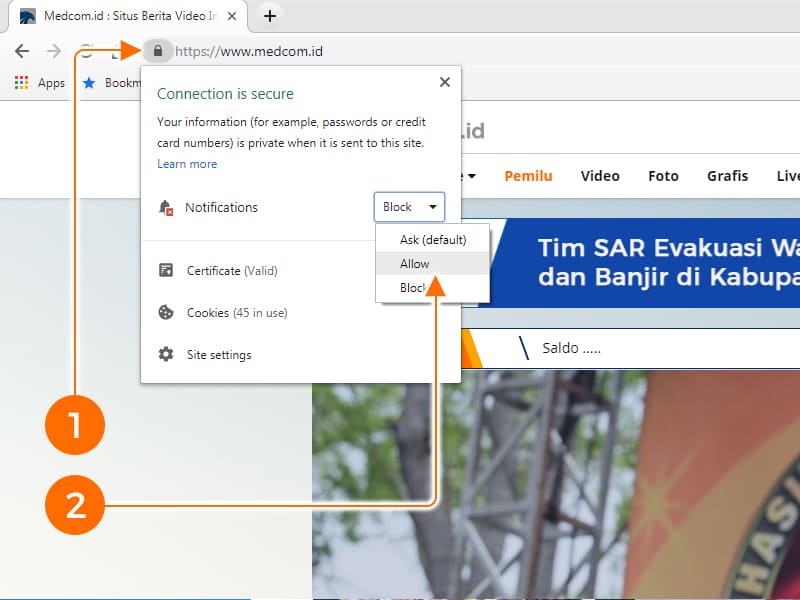DALAM sistem presidensial, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden.
Logika sistem presidensial berdampak pada personifikasi presiden dan wakil presiden di dalam naskah akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Naskah yang merupakan pengantar dan rasionalisasi bagi hadirnya Pasal 218 disebutkan bahwa kepala negara dan wakilnya dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri.
Dalam konteks ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ingin mengatakan bahwa siapa pun yang menghina presiden dan wakilnya, maka secara otomatis menjadi penghinaan bagi negara karena presiden dan wakilnya adalah personifikasi dari negara.
Selain persoalan personifikasi negara, dapat disaksikan bahwa terdapat beberapa argumentasi yang dihadapkan kepada kita semua terkait legitimasi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, meliputi:
1. Kepentingan/benda hukum (rechtsbelangan/rechtsgood) atau nilai dasar (basic values) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat/derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-niai HAM/kemanusiaan, karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal) oleh karena itu secara teoritik dipandang sebagai “rechtsdelict”, intrinsically wrong”, “mala per se” dan oleh karena itu pula dilarang di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ibadan dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan, bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum pemerintah; presiden/wakil presiden; termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan.
6. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahkan dengan prinsip “equality before the law” apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaa, pembunuhan, penganiayaan dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “equality before the law”.
Pada titik ini rupanya kritik semakin terbuka untuk dilayangkan kepada narasi yang dikembangkan oleh BPHN untuk memasukkan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap presiden. Pertama, dalam konteks personifikasi presiden, maka sebenarnya hasrat penguasaan simbolik seperti menjadi penting untuk kedaulatan, meskipun harus membuat rakyatnya menjadi korban delik.
Selain itu, personifikasi presiden sebagai “simbol negara dan terlarang untuk dihina” menjadi sumir. Di satu sisi presiden sebagai lembaga negara (dengan logika presidensial), tapi di sisi lain menjadi manusia yang memiliki hati nurani merasa terhina.
Jika kita jujur, maka masing-masing kita pasti secara tidak langsung menyadari bahwa presiden adalah predikat sosial. Sama seperti kapitalisme. Sebagai contoh, Chairul Tanjung ketika berada di CT Corp, maka predikat sosial dia adalah kapitalisme. Tapi ketika sesampainya di rumah maka bekerja predikat sosial yang lain seperti ayah bagi Putri Tanjung.
Begitu pun presiden, jika di Istana Negara dan kunjungan kenegaraannya, maka melekat predikat sosial bernama presiden. Dan jika di rumah atau warung kopi maka terlepas predikat sosialnya itu.
Kedua, sebagai nilai dasar, penghinaan berkaitan dengan subjektivitas seseorang, “merasa atau tidak merasa” dan “tersinggung atau tidak tersinggung” sebenarnya adalah interpretasi diri dan terlepas dari pemaknaan secara kolektif. Maka para penegak hukum sulit untuk mencari dan merengkuh apa saja persoalan yang dapat menimbulkan ketersinggungan.
Oleh sebab itu, maka penghinaan tidak memiliki persoalan yang begitu substansial. Maka melakukan kriminalisasi pada penghinaan adalah sebuah bentuk overkriminalisasi.
Hal ini terjadi disebabkan ada indikator untuk melakukan kriminal. Di antaranya adalah mensyaratkan terjadinya kerusakan yang benar-benar serius meskipun tidak bersifat jahat dan mengatur pencegahan atas kerusakan yang ingin dihindari dan harus melakukan pencegahan tersebut seproporsional mungkin dengan resiko kerusakan yang dapat dicegah.
Kerusakan apa yang bisa dihadirkan lewat penghinaan terhadap presiden? Tidak sama sekali, subjektivitas atas sebuah peristiwa sulit diandaikan dapat mengakibatkan bencana dan sebuah kerusakan.
Selain itu untuk menjatuhkan fatwa kriminal kepada seseorang, negara harus membatasi pada tiga jenis pembatasan. Douglas Husak mengatakan pembatas itu adalah kepentingan negara yang substansial. Upaya yang secara langsung mendukung terlaksananya kepentingan negara, pembatasan minimun yang diperlukan.
Ketiga pembatasan ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi, sebelum memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, negara harus bisa memastikan bahwa usulah kriminalisasi itu relevan dengan kepentingan negara yang substansial yang telah dimilikinya.
Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tindakan kriminalisasi memberikan pengaruh langsung untuk tercapainya kepentingan negara yang substansial tersebut. Selain itu, jika pilihannya adalah melakukan kriminalisasi, negara masih harus bisa membuktikan bahwa pemberian hukuman kepada perbuatan tersebut tidak melebihi apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung tercapainya dua pembatasan sebelumnya.
Maka sekali lagi kita renungi, apakah kriminal atas penghinaan yang jelas begitu sangat sumir merupakan agenda kepentingan negara di tengah wabah virus covid-19 yang belum selesai? Padahal, ketimpangan dari persoalan kemiskinan dan yang lainnya masih mengakar. Oleh sebab itu, maka pasal penghinaan terhadap institusi negara adalah bentuk overkriminalisasi atau kegandrungan negara untuk mengkriminalkan warga negaranya.
Ketiga, persoalan penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara mengakibatkan terseretnya presiden dan orang dalam lembaga negara untuk masuk ke ruang persidangan sebagai legal standing atau subjek hukum yang merasa dirinya terhina. Tentu ini menjadi problematis dan pelik sekali, alih-alih terkena kepada masyarakat sipil justru sebenarnya pasal ini dapat menjadi agenda kriminalisasi untuk setiap lawan politiknya.
Selain itu, para perumus dalam naskah akademik sudah memberikan sebuah disclaimer bahwa apa yang disebut “menghina” pasti sesuai juga dengan sosiokultural yang ada di berbagai negara, namun bagi penulis bukan terkait dengan negara, tapi dengan individu subjektif.
Keempat, menurut Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat CPM Cleiren, martabat raja tidak membenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu (aanklager). Pasal 134 KUHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (selaku konkordansi dari Article 111 Wvs Nederland) merupakan pasal perlakukan pidana khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap raja (atau ratu) belanda. “Pribadi raja begitu terkait erat dengan kepentingan negara, sehingga martabat raja memerukan perlindungan khusus”.
Namun, menurut Reksodiputro, tidak ditemukan rujukan apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia yang mengganti kata “raja” dengan “presiden dan wakil presiden”.
Pada titik ini, sebagai poin adalah Indonesia yang kembali lagi menggunakan logika penjajah. Ada semacam paradoks dalam perumusan RKUHP ini. Di sisi lain ingin melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan, namun di sisi lain menggunakan logika penjajah dalam beberapa pasal.
Di era demokrasi dan modern yang begitu terbuka seperti saat ini, presiden dan wakil presiden tidak sama dengan raja. Jika dulu raja diibaratkan sebagai wakil Tuhan ataupun sebagai manusia tertinggi yang dianggap paling rasional (meskipun subjektif atas dirinya sendiri), sekarang rakyat secara kolektif yang memiliki peran sebagai wakil Tuhan.
Kelima, naskah akademik BPHN mencoba untuk membedakan status antara warga negara dengan presiden ataupun instansi negara tertinggi lainnya. Ini adalah salah kaprah konstitusional filosfis. Indonesia sejak awal sudah memilih bentuk negara republik (bukan monarki), yang berarti seluruh warga negara tidak dapat dibedakan satu pun statusnya.
Dalam sejarah, waktu orang atau bangsa modern bermaksud mendirikan negara, tidak pernah dikatakan bahwa mereka pertama kali hendak membangun demokrasi. Yang pertama diungkapkan adalah bahwa mereka hendak membangun sebuah republik. Mulai dari Republik Athena, Republik Romawi Kuno hingga pendiran Republik Perancis awal abad ke-18 yang merupakan penanda pertama berdirinya sebuah negara modern di muka bumi.
Dikatakan bahwa yang hendak dibangun adalah republik. Artinya, republik menjadi prasyarat yang lebih dahulu dan paling fundamental dari pendirian komunitas bersama bernama negara.
Pada poin ini sebenarnya lembaga negara dan presiden sekalipun tidak berarti lebih dalam kehidupan repubik. Mereka adalah manusia dan warga negara. Bahkan secara radikal Daniel S Lev menjelaskan bahwa fondasi yang melandasi republik adalah sebagai berikut:
1. Pemisahan antara pemerintahan dan masyarakat, dalam arti bahwa masyarakatlah yang utama dan pemerintah didirikan untuk melayani keperluan masyarakat.
2. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi terbatas dan ditetapkan hukum.
3. Lembaga pemilihan dan kepartaian politik untuk menyalurkan pendapat umum.
4. Pers yang berfungsi baik sebagai sumber penerangan dan pengawas lembaga negara.
Pada titik ini, sebenarnya Lev lebih memutarbalikkan logika kita bahwa pemerintah adalah pelayan dan budak yang dapat diperintah oleh kita selaku raja, bahkan jika dihina sekalipun tidak menjadi sebuah permasalahan.
Oleh sebab itu, maka tidak ada satu dalil pun yang dapat membenarkan pasal penghinaan terhadap presiden ataupun lembaga negara tertinggi untuk bisa masuk pada RKUHP. Apalagi harus membuat kita sebagai warga negara terkena imbasnya dan menjadi seorang kriminal akibat melakukan sebuah kritik.
Dan untuk tulisan ini, penulis tidak banyak menyinggung soal yang berkaitan dengan hak asasi manusia ataupun demokrasi, karena ditinjau dari sudut mana pun pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara adalah bentuk pemberangusan dan kejahatan negara melalui skema hukum.[]
*Muhammad Rizaldi Minahaqi, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Hima Persis

Ilustrasi. MI/Duta (Muhammad Rizaldi Minahaqi)

Tentang Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara
Muhammad Rizaldi Minahaqi • 03 Juli 2022 11:58