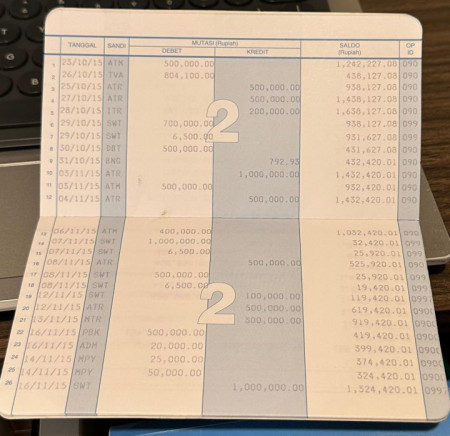Asep Salahudin, Dekan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya Dosen FISS Universitas Pasundan Bandung
SETIAP memasuki 10 November, memori kolektif kita senantiasa diingatkan ihwal peristiwa heroik kaum pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta di Gang Pegangsaan Timur 56.
Tahun 1945 di Surabaya dan juga di tempat lainnya raga dan roh dipertaruhkan Bung Tomo dan kawan-kawan demi tegaknya Indonesia yang hendak direbut kembali pasukan sekutu.
Pertempuran itu menjadi penanda pertama perang antara Indonesia yang telah resmi menjadi sebuah bangsa dan pasukan asing.
Pertempuran yang melambangkan awal sejarah revolusi nasional Indonesia.
Pertaruhan spirit nasionalisme melawan kolonialisme yang hendak mencengkeramkan kembali taring penjajahannya di tanah Nusantara.
Sebagaimana dicatat sejarah, pascakekalahan Jepang segenap rakyat berusaha melucuti persenjataan pasukan Jepang yang kemudian menimbulkan pertempuran di banyak wilayah.
Namun, bersama itu pula pada 15 September 1945 pasukan Inggris atas nama mazhab sekutu ikut ambil bagian datang ke Indonesia bergabung dengan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) dengan nawaetu awal yang tidak jauh berbeda; melucuti persenjataan tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negara asal dengan selamat.
Namun, di balik itu semua tersembunyi tekad busuk, hendak mengembalikan Indonesia ke pangkuan administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda NICA (Netherlands Indies Civil Administration).
Di pusaran inilah amarah rakyat menemukan katupnya.
Perlawanan sengit terhadap AFNEI dan NICA terjadi di mana-mana.
Surabaya berkobar, api perlawanan dalam sekejap merata ke berbagai tempat.
Dalam sebuah catatan disebutkan sekitar 6.000-16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200 ribu rakyat sipil mengungsi dari Surabaya.
Korban dari Inggris dan India kira-kira sejumlah 600-2.000 orang.
Surabaya yang diperkirakan dapat ditaklukkan dalam hitungan tiga hari kenyataannya jauh panggang dari api.
Bukan hanya tidak bisa ditundukkan, Bung Tomo dan pasukannya beserta para kiai dan santri seperti dirasuki lipatan nyawa.
Mereka seolah tak mengenal takut, menerjang ke depan, maju ke muka, melawan dengan segenap upaya untuk mempertahankan Indonesia yang baru saja dideklarasikan kemerdekaannya itu.
Itulah asbabun nuzul 10 November yang sekarang kita sebut Hari Pahlawan.
Hari yang menandakan tidak saja bagaimana keberanian dirayakan, ketakutan dilucuti, tapi lebih dari itu bagaimana segenap rakyat mereka melakukan semuanya dengan ikhlas atas nama panggilan agama sekaligus negara (nasionalisme).
Takbir kebangsaan
Kalau kita berkunjung ke Surabaya, tidak jauh dari Tugu Pahlawan, kurang lebih 300 meter terdapat Monumen Nasional Resolusi Jihad yang diresmikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada 23 Oktober 2011.
Tentu saja Resolusi Jihad dan Hari Pahlawan 10 November ibarat anak kembar, satu sama lain tak bisa dipisahkan.
Resolusi Jihad yang dibidani Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'arie, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireung sekaligus pendiri NU (Nahdlatul Ulama) isinya berupa seruan kepada seluruh kiai dan santri di tanah Jawa dan Madura untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air dari kaum penjajah bahkan disebutkan sebagai jihad fi sabilillah dan kematiannya dipandang syahid.
Resolusi yang ditandatangani Mbah Hasyim 23 Oktober 1945 dan kemudian kepada KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syamsuri diinstruksikan untuk menjadi koordinator para kiai dan santri.
Secara berulang-ulang resolusi ini yang disiarkan Bung Tomo sehingga gemanya sampai ke berbagai pelosok.
Bung Tomo yang dibawa KH Wahid Hasyim (putranya KH Hasyim Asyarie) menghadap Mbah Hasyim, atas izin para kiai melawan pasukan asing dengan teriakan Allahu Akbar sampai kemudian menewaskan Brigjen Mallaby.
Sejarah tidak mencatat Bung Tomo bagian dari kelompok santri, tetapi hikayat mengabarkan bagaimana Bung Tomo melakukan aliansi strategis dengan kelompok kiai dan santri.
Bung Tomo sadar bahwa perlawanan menghadapi kaum kolonial ketika disuntik spirit religiositas jauh akan lebih bergelora ketimbang perlawanan yang mengandalkan sentimen nasionalisme semata.
Di titik ini sesungguhnya baik Bung Tomo ataupun KH Hasyim Asy'ari telah menafsirkan pekik Allahu Akbar secara kontekstual: sebagai panggilan jihad fi sabilillah sekaligus jihad wathaniyah (kebangsaan). Keduanya seolah hendak meneguhkan sebuah iman bahwa nilai jihad fi sabilillah sebangun dengan mempertahankan wilayah negara.
Bahwa keagamaan dan kebangsaan tidak sepatutnya ditarik dalam garis bipolar-dikotomik, tapi semestinya berada dalam maqam satu haluan napas, satu tarikan jiwa.
Bahwa tubuh kebangsaan menghajatkan nilai-nilai religiositas sebagaimana keagamaan membutuhkan wadah negara.
Agar agama dan bangsa tidak bertabrakan, keduanya wajib disublimkan dalam sikap lapang, terbuka, inklusif, dan kosmopolit.
Karena itu, menjadi dapat dipahami kalau karakteristik keberagamaan NU (dan Muhammadiyah) sangat moderat, menerima Pancasila sebagai ideologi final, menyetujui NKRI.
NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sadar sesadar-sadarnya bagaimana cara beragama yang benar kaitannya dengan negara, bagaimana cara bernegara yang benar selaras dengan haluan nilai-nilai universal agama.
Tidak pernah dalam sejarahnya kedua ormas itu melakukan tindakan anarkistis karena keduanya paham bahwa Indonesia ini dilahirkan dari rahim para pejuang yang, notabene diakui atau tidak, tak sedikit mereka ialah datang dari kalangan santri.
Menolak Indonesia atau mengajukan ideologi di luar Pancasila tidak saja mencerminkan sikap durhaka terhadap orangtua, tapi juga melambangkan tindakan yang tidak tahu cara berterima kasih kepada leluhur kaum pejuang pahlawan bangsa yang telah mempertaruhkan nyawa dan raga mereka itu.
Melampaui kepahlawanan
Tentu saja, pahlawan itu harus diingat, kata Soekarno, "Bangsa besar adalah mereka yang menghargai para pahlawannya," tapi juga ialah bangsa yang sakit kalau setiap saat mengharapkan lahir pahlawan apalagi kalau gelar pahlawan itu diajukan kepada negara dengan cara-cara tidak elegan.
Maksudnya memperingati Hari Pahlawan itu menjadi penting kalau di dalamnya terinjeksikan kesadaran untuk tidak pernah berhenti menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan dalam diri kita baik sebagai personal ataupun sosial sebagai bagian dari bangsa.
Hari Pahlawan tidak sekadar bagaimana kita datang ke lapangan menyelenggarakan upacara dan mengheningkan cipta mengenang jasa-jasa mereka, tapi bagaimana etos kepahlawanan itu ditransformasikan dalam wujud cara berbangsa, bernegara, dan beragama yang benar.
Hari Pahlawan penting kita kenang justru ketika hari ini, atmosfer peradaban politik yang mengepung kita sedang menuju ke era jahiliah sejahiliah-jahiliahnya, politik yang mengharu biru kita hanya menghasilkan kerumunan politikus yang nafsu kekuasaannya lebih besar ketimbang akal sehatnya, tatkala agama yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa mengalami defisit penghayatan dan hanya menyisakan gemuruh sikap intoleran termasuk yang diperagakan para kepala daerah (wali kota) bermental primitif yang semestinya menjadi figur yang memayungi semua keyakinan, manakala ekonomi hanya dikendalikan segelintir konglomerat dan visi koperasi semakin terpelanting ke tempat entah.
Kepahlawanan itu bukan raga apalagi semata menabur bunga di atas pusara di permakaman Taman Kalibata, tapi ia adalah 'roh' yang harus menjadi pandu untuk mengembalikan khitah bernegara kita, memulangkan lagi rute berbangsa ke arah jalan lurus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Memberi hormat saat pengibaran Bendera Merah Putih raksasa di tugu Monas, Jakarta. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja) ()