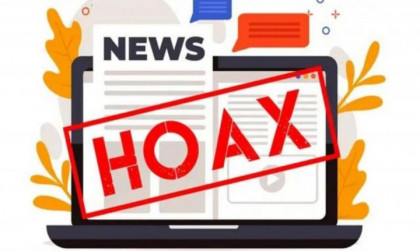Banjir bandang di Garut karena rusaknya alam. Tindak tegas pelaku perusakan lingkungan -Jkw pic.twitter.com/R9P05qUjJ6
— Joko Widodo (@jokowi) September 29, 2016
Pertanyaannya, mengapa masih ada perusak lingkungan sementara Indonesia sudah memiliki sederet regulasi terkait lingkungan hidup? Bagaimana pula aturan-aturan ini bisa ditabrak oleh si perusak lingkungan?
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, aturan terkait pelestarian lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam, bahkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sudah ada. Namun, penegakan hukumnya yang lemah.
"Kita ini tidak kekurangan regulasi. Aturan ada dan cukup ketat. Tapi undang-undang dan sebagainya itu kurang terimplementasi, hanya tersimpan rapi di laci meja," ujar Sutopo saat berbincang dengan medcom.id di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Baca: Mengenal Sungai Sebagai Sumber Peradaban dan Ancaman dari Sungai-sungai Rusak Sutopo menjelaskan, secara umum rusaknya DAS diakibatkan alih fungsi lahan yang sebabkan berkurangnya tutupan hutan dan pengabaian instrumen tata ruang, baik di bagian hulu, tengah dan hilir. Jumlah kerusakan meningkat signifikan ketika memasuki era reformasi, sejak tahun 1998 silam.
"Semua boleh, hutan ditebangi, perkebunan, konversi lahan pertanian termasuk otonomi daerah. Semua bicara atas nama PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan lain-lain. Pada bagian hulu banyak tambang masuk hutan," kata Sutopo.
Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan fakta abainya bangsa ini soal tutupan hutan di hulu DAS. Di Jawa Barat, hampir semua DAS kritis dengan angka tutupan hutan yang menurun. Selain alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, konsesi tambang menjadi penyebab terbesar hilangnya hutan (deforestasi) di Jawa Barat.
DAS Cimanuk yang memiliki luas lebih dari 350 ribu hektare pada 2013 hanya tersisa tutupan hutan sekitar 33 ribu hektare. Presentasi tutupan hutan terhadap luas kawasan DAS hanya 9,3 persen. Artinya, bila target pemerintah untuk presentasi tutupan hutan pada DAS saat ini adalah 30 persen, jelas DAS Cimanuk jauh dari target tersebut.
"Makanya jangan heran bila kemarin terjadi banjir bandang terhebat sepanjang sejarah Garut, karena tutupan hutannya tidak mencukupi," ucap Linda Rosalina, Divisi Kampanye dan Advokasi FWI kepada medcom.id, Jumat (30/9/2016).

Sampai tahun 2013 saja terdapat 889 izin tambang di DAS Jawa Barat. Daerah yang terbebani izin tambang terbanyak adalah Cianjur, Garut, Bogor dan Sukabumi. Linda menyatakan, banyaknya inkonsistensi mengenai tata ruang di wilayah hutan Indonesia juga menjadi persoalan dalam pengelolaan DAS dan perizinan yang terbit disekitarnya. "Contohnya di kawasan Pucak (Bogor), di tata ruang menyebut itu hutan lindung, sementara (Kementerian) Kehutanan bilang hutan produksi. Dualisme seperti ini banyak, ada ego sektoral juga dalam penyelesaiannya," ucapnya.
Menyoal banyaknya izin atau konsesi-konsesi yang sebabkan hilangnya tutupan hutan, terutama di sekitar DAS, Linda menuturkan bahwa izin yang tak terkendali menjadi salah satu penyebabnya. Sementara penyebab izin tak terkendali ini boleh jadi karena banyaknya instansi yang berwenang dalam pengelolaan DAS, seperti KLHK, Kementerian Dalam Negeri, pertanian, ESDM, dan PU.
Bahkan, menurut penelitian badan pangan sedunia alias Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1994, di Indonesia ditemukan lebih dari 13 lembaga atau instansi yang terlibat dalam urusan tanah dan penggunaan tanah pada suatu DAS. Akhirnya, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing lembaga menggunakan pendekatan, metode dan peritilahan sendiri-sendiri tergantung pada kepentingan sektoralnya. Akibatnya sering terjadi duplikasi kegiatan, juga informasi yang sulit untuk dimengerti dan terlihat sangat sektoral.
"Sekarang yang perlu dilakukan review perizinan, yang melanggar perlu ditindak, dan yang terpenting mengajak lagi masyarakat untuk berpartisipasi agar ada inisiatif mengawasi pembangunan di sungai-sungai dan melaporkan pelanggaran," kata Linda.

Hal ini juga diakui Kepala Divisi Kerusakan Lingkungan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Margaretha Quina. Menurut dia, penegakan hukum pelanggaran tata ruang hampir tidak ada, termasuk pengkajian ulang atas izin-izin usaha/kegiatan tertentu di daerah hulu. "Sebagian besar DAS terutama Jawa masalahnya memang itu. Yang di peta masuk kawasan lindung, kenyataannya sudah jadi perumahan, jadi lahan masyarakat maupun perusahaan," kata Quina dalam perbincangan dengan medcom.id, Kamis (29/9/2016).
Ia menambahkan, bila ada niat untuk menelusuri perusakan lingkungan akibat usaha atau kegiatan tertentu, cukup ditelusuri sumber izinnya. Bila berada di luar konservasi atau hutan - hulu DAS, perizinan ada di tangan Pemerintah Daerah.
Komisi AMDAL
Senada dengan Sutopo, persoalan rusaknya DAS, menurut Quina, bukan pada regulasi, melainkan pada pelaksanaan. Salah satunya dalam penerbitan izin lingkungan (IL) yang merupakan syarat sebelum diterbitkan izin mendirikan bangunan atau izin usaha/kegiatan tertentu.
Sebelum IL diterbitkan, permohonannya harus lolos verifikasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu. "Dalam proses ini juga banyak ditemukan masalah," katanya.
Verifikasi atau uji kelayakan ini dilakukan oleh Komisi AMDAL. Idealnya, pemerintah daerah mengundang unsur akademisi, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), LSM lingkungan juga masyarakat terdampak, sebagai komisi AMDAL.
"Banyak temuan sekarang undangannya dipilih, diundang orang-orang yang pro. Atau undangan dikasih pada H-1 atau hari-H, jadi masyarakat terdampak tidak aware bahwa itu sebenarnya ada dampak lingkungan," kata Quina.
AMDAL sendiri sifatnya rekomendasi. "Yang menentukan, stempel persetujuannya tetap pemerintah daerah. Sangat jarang pusat bisa intervensi proses AMDAL hingga IL dikeluarkan," ucapnya.
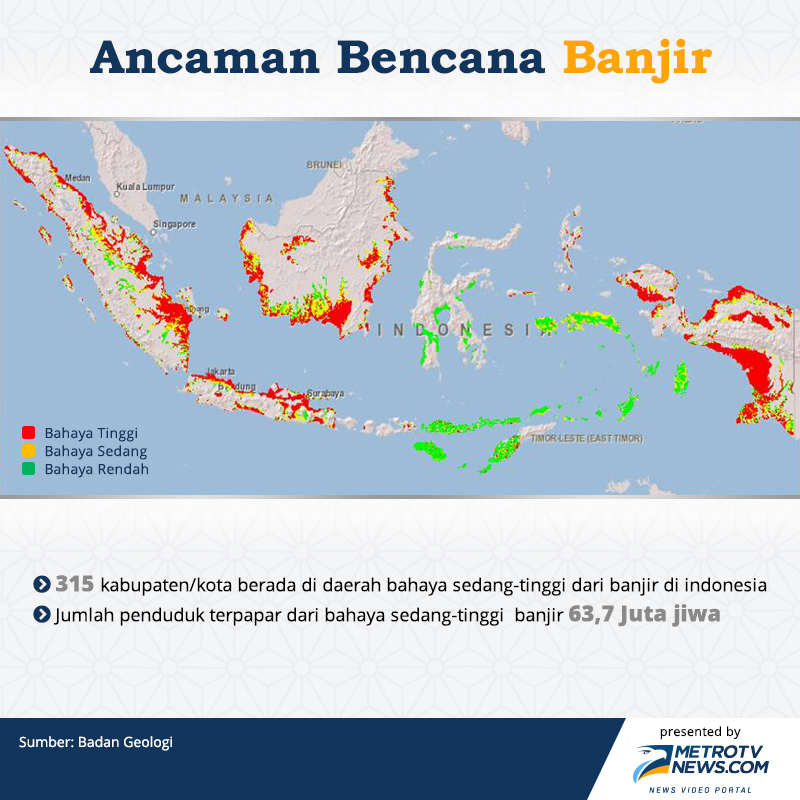
Saat ini yang banyak terjadi adalah keterlanjuran, AMDAL lolos dan IL sudah keluar untuk proyek-proyek tertentu yang ternyata di kawasan yang salah, tidak sesuai atau melanggar tata ruang. Sementara monitoring dan evaluasi dari pusat tidak memiliki mekanisme baku, padahal kewenangannya ada.
"Keterlanjuran ini baru bisa di-review bila pihak ketiga (masyarakat terdampak atau siapapun diluar pemohon dan pemberi izin) memintanya karena diindikasi melanggar. Intinya tunggu pengaduan," kata Quina.
Terkait penegakan hukum, untuk pidana, Polri dan Kejaksaan dinilai kurang memahami persoalan-persoalan hukum lingkungan. Penegakan hukum satu atap bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lembaga terkait juga belum berjalan. Menurut Quina, selain koordinasinya belum terbentuk, juga masih ada bumbu ego sektoral.
"Persoalan korupsi bisa masif penanganannya karena ada KPK, komisi independen dari berbagai unsur. Hal ini tidak terjadi di lingkungan," ucap Quina. Padahal, menurutnya, dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kementerian, Polri, Kejaksaan bisa bekerja satu atap menuntaskan persoalan pidana dalam lingkungan, seperti KPK, tapi tidak berjalan.
Saat ini yang berjalan hanya pada pelanggaran administrasi, seperti pencabutan izin, dll, yang dilakukan KLHK. Sementara Pemda, yang notabene lebih dekat dengan persoalan tata ruang, tidak melakukan itu. "Padahal regulasi sudah memberikan kewenangan Pemda untuk gugat. Tapi, bila dicek dalam sidang-sidangnya, staf atau dinas-dinas terkait Pemda malah jadi saksi untuk perusahaan. Ya, begitulah, ada paradigma yang beda antara pusat dan daerah," kata dia.
Kini, menurut Quina, yang diperlukan adalah niat untuk mengkaji ulang pelanggaran yang tergolong "keterlanjuran". Selain itu, perlu ada audit kepatuhan. Masalah di DAS, izin-izin pembangunan perumahan, usaha/kegiatan tertentu perlu diaudit semua, identifikasi pelanggaran dan ditindak baik administrasi maupun pidana.
Diperkirakan, bila audit ini dilakukan akan banyak potensi pelanggaran yang terkuak, bukan pada pemegang izin saja, bahkan penerbit izinnya. "Saya pikir ini suatu tantangan. Misalnya cimanuk, kalau ada alih fungsi lahan katanya, ya audit saja tunjukan ada pelanggaran atau tidak. Perhutani sertifikat-sertifikatnya bagaimana, kalau itu kawasan lindung dialih fungsi, kapan diberikan izinnya, apakah legal atau tidak," ujarnya.
Sementara evaluasi untuk skala rumah masyarakat yang non izin diperlukan pendekatan khusus, karena banyak rumah-rumah masyarakat di bantaran sungai yang usianya sudah lama, atau sebelum aturan-aturan lingkungan ini ada. "Opsinya ya relokasi. Tapi relokasinya harus memenuhi syarat-syarat kelayakan," kata Quina.
Begitu pula restoran, hotel, perumahan di kawasan DAS, bila hasil kajian ulangnya itu melanggar, harus dicabut izinnya. "Dan bila mereka ingin menuntut ganti rugi kepada pemberi izin, dalam hal ini Pemda, sebenernya bisa saja dikejar," ucap Quina.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News