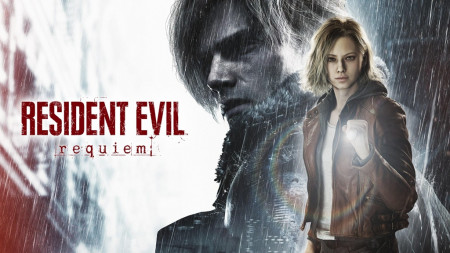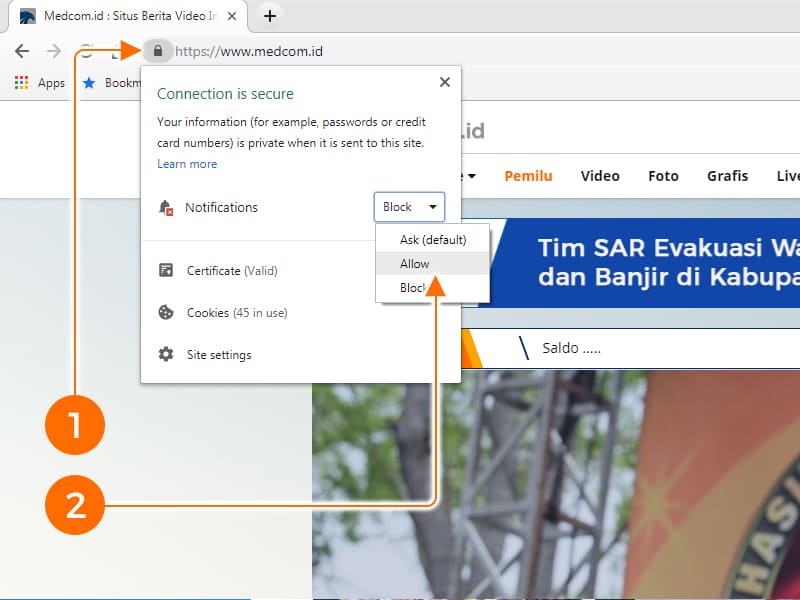Determinisme yang demikian kemudian diradikalkan oleh Laplace dengan menyatakan, ada wujud super-intelegensia yang dapat mengalkulasi segala variabel di alam semesta, sehingga ia dapat mengetahui alam semesta di sepanjang waktu.
Obsesi Laplace atas sains tersebut dianggap telah menjadi elan vital sains modern, yang menuntut suatu sikap rigiditas objektivitas ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Klaim objektivitas mengandaikan, pengetahuan yang objektif adalah pengetahuan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi yang akurat serta presisi.
Pengetahuan yang demikian diklaim murni dari campur tangan subjektivitas manusia. Keberjarakan antara si peneliti dengan objek yang ditelitinya adalah prasyarat mutlak dalam penelitian ilmiah yang memproduksi ilmu pengetahuan.
Problem Objektivitas
Terlepas dari kemajuan sains dan implikasi teknologisnya, keberjarakan ilmiah bukannya tanpa masalah. Konsepsi objektivitas membuat jarak yang tegas antara subjek penahu dan objek yang hendak diketahui. Keberjarakan yang demikian dituntut agar pengetahuan bisa murni dari unsur subjektif manusia, misalnya seperti komitmen dan tanggung jawab. Pengetahuan yang sahih adalah yang faktual dan bisa dibuktikan secara empiris.Obsesi demikian disebut dengan positivisme, yang sempat begitu dominan dalam alam pikir Barat modern. Persis akibat dari postivisme keras itulah sempat memunculkan ideologi tiran Marxisme-Komunisme dan totalitarianisme NAZI di abad ke-20.
Rezim komunis Uni Soviet pernah menjalankan program penelitian ilmiah yang terpusat, yaitu penelitian yang sudah digariskan untuk kepentingan partai atau ideologi komunis. Untuk kepentingan tersebut, maka hal-hal yang non-materialistik harus disingkirkan.
Sementara NAZI pernah menjalankan program eugenika (eugenics), yaitu program pemurnian ras bangsa Jerman menjadi ras unggul bangsa Arya. Baik Marxisme-Komunisme maupun NAZI, meskipun menjalankan agenda politik, namun keduanya mendasarkan diri pada sains.
Lokus krisis kemanusiaan abad ke-20 yang ditimbulkan oleh Marxisme-Komunisme dan NAZI adalah pada konsepsi objektivitas pengetahuan. Selain itu, atas nama objektivitas ilmiah, hal-hal terkait moralitas dan agama juga disingkirkan karena dianggap tidak ilmiah.
Kecenderungan seperti itu membuat dunia modern – menurut tilikan Michael Polanyi – mengalami krisis dan sakit. Untuk memulihkannya dari kondisi krisis dan sakit tersebut, diperlukan suatu konsepsi pengetahuan yang lebih “sehat”.
Struktur Pengetahuan
Konsepsi pengetahuan Polanyi menekankan pada partisipasi personal, alih-alih keberjarakan ilmiah mutlak yang positivistik. Ketika seseorang memperoleh pengetahuan, pada dirinya bekerja dua level kesadaran, yaitu kesadaran subsider dan kesadaran fokal.Kesadaran fokal berkaitan dengan kesadaran akan suatu objek yang menjadi perhatian kita. Tetapi, semua kesadaran fokal bergantung pada kesadaran subsider. Ketika kita terfokus pada objek yang menjadi pusat perhatian kita, pada saat yang sama kita juga berada secara subsider dalam berbagai petunjuk khusus yang berada di latar belakang.
Sebagai ilustrasi, misalnya saat kita hendak menancapkan paku ke tembok dengan menggunakan palu. Kesadaran fokal kita bekerja untuk mengayunkan palu setepat mungkin mengenai paku untuk menancap ke dinding.
Di sisi lain, kesadaran subsider bekerja ketika indera kita yang awas terhadap sensasi pada telapak tangan dan jari-jari yang menahan paku, dalam hal ini untuk menghindari palu menghantam telapak tangan. Keterpaduan antara kesadaran subsidier, pegangan kita atas paku, dan kesadaran fokal yang mengarahkan pukulan palu ke paku, menghasilkan tertancapnya paku ke dinding secara efektif.
Proses keterpaduan antara kesadaran fokal dan kesadaran subsider mendasari tindakan yang praktis hingga kerja teoretis yang canggih. Ketika seorang mahasiswa kedokteran sedang mendalami suatu penyakit, ia akan mempelajari daftar variasi gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit yang sedang dipelajarinya (kesadaran fokal).
Tetapi, hanya praktik klinis yang dapat mengajarkannya bagaimana mengintegrasikan petunjuk-petunjuk yang diamati pada pasien untuk membuat suatu diagnosis yang tepat (kesadaran subsider). Di sini terdapat peran keterampilan si mahasiswa kedokteran dalam mengintegrasikan pengetahuan dan pengamatannya untuk membuat diagnosis yang tidak keliru.
Peran Subjek
Konsepsi pengetahuan Polanyi mengandaikan partisipasi personal dalam memperoleh pengetahuan. Partisipasi personal ini mengandung dimensi tacit, yang tidak dapat diekspisitkan sepenuhnya.Dalam dimensi tacit terdapat tradisi dan otoritas yang turut berperan dalam transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Dimensi tacit ini juga bekerja dalam jenis pengetahuan lain di luar sains, misalnya ketika seorang pelukis membuat lukisan, seorang penyair menulis puisi, seorang pendeta menyampaikan khotbah, dan sebagainya.
Proses tacit knowing inheren dalam segala bentuk pengetahuan manusia, baik praktis maupun teoretis. Keterlibatan personal subjek dalam kerja ilmu pengetahuan mewujud dalam keterampilannya (connoisseurship) mengintegrasikan kesadaran fokal dan kesadaran subsider, misalnya ketika seorang astronom mengamati permukaan Planet Mars dengan alat stereoskop, instrumen yang digunakan untuk melihat sepasang foto yang berbeda dari objek yang sama (diambil dengan sudut yang berbeda).
Dimana masing-masing mata melihat gambar yang berbeda. Citra yang tampak merupakan citra tiga dimensi, sebagai hasil integrasi tacit dari kedua gambar dua dimensi yang berbeda.
Paradigma pengetahuan personal memulihkan cara pandang yang lebih “sehat” atas sains. Alih-alih berjarak atas nama objektivitas ilmiah, sesungguhnya kerja-kerja dalam sains melibatkan peran subjek dalam memproduksi ilmu pengetahuan.
Tidak hanya bekerja dalam ilmu-ilmu alam, pengetahuan personal juga bekerja dalam wujud ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti seni, teologi, etika, dan moralitas. Konsepsi pengetahuan personal yang digagas oleh Polanyi memungkinkan cara pandang yang lebih holistik atas ilmu pengetahuan.