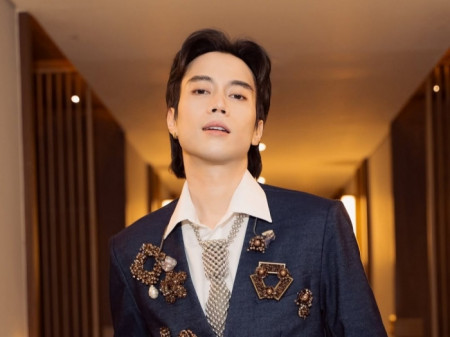Oleh Saharuddin Daming, Dosen Fakultas Hukum Ibnu Khaldun Bogor Mantan Komisioner Komnas HAM
Artikel ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Selasa 23 September 2014
PERUBAHAN dalam konteks peradaban dan keadaban sejatinya merupakan proses kemajuan konstruktif dengan pola comparative degrees. Esensi perubahan tidak lain ialah transformasi nilai dari kategori buruk, kurang, rendah, atau lemah menjadi baik, lebih, tinggi, atau kuat.
Begitulah ekspektasi dan obsesi anak-anak negeri ketika menabuh genderang reformasi 1998 pascatumbangnya Orde Baru sebagai rezim yang sangat lekat dengan karakter KKN, sentralistis, dan otoriter.
Sungguh sangat disesalkan karena rangkaian perubahan yang digerakkan rezim di kekinian ternyata tidak berbanding lurus dengan komitmen reformasi. Selain berjalan sangat alot dengan haluan yang cenderung menempuh jalur zig-zag, roda pergerakannya kerap ditunggangi kepentingan pragmatis oleh segelintir elite politik melalui strategi kolaborasi yang cenderung dipaksakan untuk sekadar memenuhi syahwat kekuasaan. Mereka sukses membangun kekuatan oligarki di hampir semua segmen penyelenggaraan negara.
Tidak mengherankan jika arah dan warna perubahan yang tersaji dalam segala bidang cenderung terdikte oleh pemegang kendali oligarki kekuasaan. Demokrasi dibajak sekadar untuk menjadi instrumen legitimasi dan justifikasi. Simpati publik dibombastis sedemikian rupa melalui politik pencitraan. Kekerdilan jiwa yang tak legawa menerima kekalahan dipoles sedemikian rupa melalui penyalahgunaan pranata hukum. Pencitraan dan cuci tangan
Tengoklah fenomena atraktif ketika pimpinan negara jatuh sepenuhnya di tangan rezim di masa kini. Mereka lantang meneriakkan slogan anti-KKN, antiotoriter, dan antisentralistis. Namun, bukankah waktu juga yang membuktikan betapa paradoksnya rentang yang menghubungkan antara input dan output sehingga hasilnya jauh panggang dari api. Satu per satu selebritas rezim akhirnya terjerat perangkap KPK. Ironisnya, karena ketika sejumlah elite papan atas mereka ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (TPK) oleh KPK, pucuk pimpinan partai sekaligus pimpinan negara ternyata hanya menyampaikan rasa prihatin tanpa menunjukkan sikap kecewa, marah, apalagi malu atas pengkhianatan yang dilakukan para pembantu dekatnya.
Parahnya lagi karena mereka yang menyandang predikat sebagai tersangka TPK diberi insentif dalam bentuk penyediaan tim advokat oleh partai untuk membela mereka. Realitas itu sekali lagi membuktikan peragaan sikap kemunafikan yang hebat. Karena ketika ada kader dan elite lainnya diputuskan menjadi tersangka oleh KPK, partai pengusungnya langsung cuci tangan dengan dalil bahwa TPK sejumlah kadernya bukan dan tidak ada korelasinya dengan partai.
Apakah ini merupakan buah dari politik santun yang senantiasa digembar-gemborkan rezim dimaksud, atau semua itu merupakan efek domino dari melembaganya sikap kemunafikan yang dibalut dengan kesalehan politik? Atau jangan-jangan itu merupakan konsekuensi dari elitisasi yang begitu membudaya pada rezim dimaksud sehingga demi menjaga soliditas, semua pejabat tinggi negara dianggap sebagai trompet kebaikan dan kebenaran dari titah sang pemimpin.
Kekisruhan MD3
Sikap kemunafikan berbalut kesalehan oleh sejumlah elite politik kita belakangan ini semakin memperoleh bentuk ketika DPR menetapkan revisi UU No 27 Tahun 2009, menjadi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tertanggal 8 Juli 2014. Dari delapan poin yang menjadi objek revisi, setidaknya ada dua hal yang sungguh-sungguh merefleksikan sikap tersebut.
Pertama ketentuan dalam Pasal 84 UU No 17 Tahun 2014 tentang mekanisme pemilihan dan penetapan ketua DPR, yang semula langsung dijabat kader partai pemenang pileg, kini diubah dengan mekanisme voting mengikuti rezim UU No 22 Tahun 2003. Anehnya, mekanisme seperti itu hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi tidak untuk DPRD provinsi/ kabupaten/kota. Meski itu dibungkus dengan berlaksa argumentasi yang membangun image kesalehan, publik dengan tingkat pemahaman politik yang relatif awam sekalipun tetap dapat menangkap iktikad tidak luhur di balik perubahan tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk ekspresi kemunafikan mereka yang berbalut kesalehan dengan mengatasnamakan demokrasi demi memenuhi ambisi dan syahwat untuk merebut kursi pimpinan parlemen.
Kedua, ketentuan dalam Pasal 224 ayat 5 UU No 17 Tahun 2014 tentang keharusan lembaga penyidik untuk memperoleh persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap setiap pemeriksaan atau penangkapan anggota DPR yang terkait dengan tindak pidana. Mekanisme imunitas anggota DPR seperti itu semakin menjauhkan komitmen legislator kita dari sikap kenegarawanan di bidang penegakan hukum dan keadilan. Selain bertentangan dengan prinsip equal justice under law equality before the law sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, klausul seperti itu menimbulkan perbenturan hukum.
Pasal 224 ayat 7 UU No 17 Tahun 2014 menegaskan, jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan persetujuan atas pemeriksaan oknum tersangkut tindak pidana, hal tersebut dinyatakan batal demi hukum. Itu berarti kewenangan KPK untuk memanggil apalagi menahan seorang legislator yang tersangkut TPK dapat dimentahkan sebuah keputusan nonyudisial. Semua itu sengaja dibangun legislator untuk memproteksi diri demi menghalang halangi proses penegakan hukum yang melibat kannya. Ini merupakan kelanjutan dari skenario koboi Senayan untuk menggembosi dan mengamputasi kewenangan KPK. Betapa tidak karena satu-satunya lembaga di Indonesia yang berani menindak tegas legislator yang terlibat TPK tidak lain ialah KPK. Karena itu, mereka sangat tidak rela jika kekuasaan yang begitu besar dalam jabatannya terusik oleh ketajaman pedang KPK.
Pergeseran demokrasi
Puncak penampakan wajah kemunafikan legislator kita berbalut kesalehan terkuak dari Koalisi Merah Putih yang berkomplot untuk menghapus pilkada langsung dan kembali memberlakukan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini jelas merupakan langkah mundur karena menjungkirbalikkan nilai demokrasi serta mengebiri kedaulatan rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya di tingkat lokal.
Sikap tersebut juga mereinkarnasi sistem otoriterisme Orde Baru. Dengan mekanisme seperti itu, tamatlah riwayat calon independen/nonpartisan untuk menjadi kepala daerah. Lebih mengherankan karena sebelum penyelenggaraan Pilpres 2014, koalisi tersebut menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, setelah pilpres, terjadi perubahan sikap secara drastis.
Sepintas argumentasi tersebut menampakkan wajah kesalehan yang saksama, tetapi ibarat kancing, masuk ke lubangnya bagaimanapun juga akan tetap terlihat posisinya. Manuver yang dilakukan Koalisi Merah Putih tersebut ditengarai sebagai imbas kekalahan mereka dalam pilpres. Revisi UU No 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk semakin memperkuat sistem demokrasi lokal kini mengalami pembiasan dan semakin terkontaminasi oleh dendam kesumat para elite parpol yang tak legawa menerima kekalahan.
Sebenarnya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa saja menghadirkan nilai keluhuran dan kesalehan demokrasi jika legislator kita berkualitas dan independen sejati. Masalahnya ialah sejak dulu hingga kini semua legislator kita merupakan representasi partai sehingga harus tunduk sepenuhnya kepada kehendak partai yang dikendalikan elitenya.
Karena itu, kita patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari partainya lantaran malu dan memprotes keras gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diprakarsai Koalisi Merah Putih. Sikap Ahok seperti itu merupakan wujud kesalehan hakiki seorang politikus yang berkepribadian tegas dan konsisten mempertahankan prinsip idealisme.