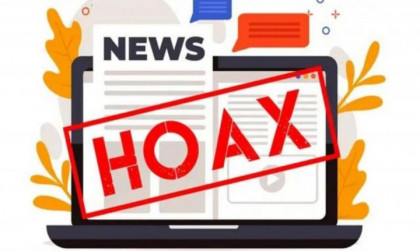Namun, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memanfaatkan peluang ekonomi maritim yang dimilikinya secara maksimal. Dalam mengembangkan industri maritim, semua pihak harus menyadari Indonesia adalah negara kepulauan. Konsep Indonesia Incorporated semestinya bisa diwujudkan demi mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
Keberhasilan Jepang dan Tiongkok menjadi dua negara dengan ekonomi terkuat di kawasan Asia justru karena mengimplementasikan konsep incorporated itu. Keduanya pun tak mengabaikan potensi industri kelautan dan maritimnya.
Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan, menyatakan bahwa Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim. Indonesia masih berstatus negara kepulauan (archipelago). Negara maritim, ia menjelaskan, adalah negara yang mampu menguasai dan mengelola laut dengan segala kekuatannya. Negara maritim tidak harus negara kepulauan.
Singapura bukan kepulauan. Amerika juga bukan kepulauan. Tiongkok pun bukan kepulauan. Tapi karena mereka menguasai laut dan mampu memanfaatkan laut dengan segala keunggulannya baik itu sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan lain sebagainya, maka mereka bisa dikategorikan sebagai negara maritim.
"Indonesia ini walaupun negara kepulauan, belum bisa disebut negara maritim. Karena belum mampu mengelola dan memanfaatkan laut secara maksimal untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah perbedaannya Indonesia dengan Singapura," ujar Yulian kepada medcom.id, Kamis (15/10/2015).
Kenapa Singapura disebut negara maritim? Karena, meski negara kecil Singapura mampu memanfaatkan wilayah laut dan posisi strategisnya untuk mengendalikan perdagangan dunia dengan membangun pelabuhan kelas utama. Ini bisa dilihat dari berbagai keunggulan pelabuhan Singapura, antara lain seperti kecanggihan teknologinya dan kualitas pelayanan mereka. Faktor ini yang membuat hampir seluruh kapal yang melintasi Selat Malaka memilih singgah di pelabuhan Singapura.
Ibaratnya, pelabuhan Singapura itu toko yang lengkap dan layanannya bagus, sehingga banyak orang tertarik untuk mampir ke situ.
"Bayangkan, karena kapal-kapal yang ingin ke Laut Pasifik itu melintasi Selat Malaka lalu mereka lihat pelabuhan Singapura ini keren, mampir deh mereka ke situ. Selain istirahat, mereka bisa isi logistik, perbaiki ini itu, dan lain-lain," kata Yulian.
Nah, begitu mampir, kapal mereka ini membayar, ada tarif kapal sandar alias parkir di pelabuhan. Berhenti di toko saja kita pasti kena biaya parkir kendaraan. Tapi ongkos parkir ini tidak seberapa dibandingkan uang yang dibelanjakan di toko itu. Maka bisa dipahami betapa besar keuntungan yang dinikmati Singapura sebagai persinggahan kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.

"Makanya, jangan heran dengan kenyataan tentang Singapura yang menjadi negara sangat kaya. Kekayaan Singapura itu dari sektor jasa, terutama jasa pelabuhan," kata Yulian.
Patut disesalkan Indonesia tidak membangun kekuatan maritimnya. Belum ada yang bisa dibanggakan oleh Indonesia di bidang maritim. Indonesia belum menjadi negara maritim.
"Sebenarnya, kalau mau menjadi negara besar dan maju, Indonesia tinggal fokus saja menjadi negara maritim," kata Yulian.
Negara agraris?
Sejarah mengatakan bahwa dulu kerajaan-kerajaan di Indonesia itu, antara lain seperti Majapahit dan Sriwijaya berjaya karena punya kekuatan armada niaga dan militer yang menguasai jalur perdagangan kawasan Asia.
Kalau sejarah itu benar, kata Yulian, berarti sejak dulu masyarakat di Nusantara ini sesungguhnya sudah punya visi dan melihat peluang maju di bidang maritim.
Namun, ia melanjutkan, setelah Belanda datang dan menjajah, paradigma dan cara berpikir bangsa di wilayah Nusantara ini banyak berubah. Selama kurang lebih tiga setengah abad agen-agen Belanda membangun kemitraan dengan para penguasa kerajaan di Nusantara di bidang pertanian agar rakyatnya menanam komoditas yang laku di pasar Eropa. Kemudian dari sistem kerja sama itu, perusahaan-perusahaan Belanda memonopoli produk-produk pertanian hasil bumi dari kerajaan di Nusantara, terutama rempah-rempah.
Maka, tak pelak lagi lambat laun kerajaan-kerajaan ini beralih dari negara maritim menjadi negara agraris. Belanda boleh dibilang sukses membuat paradigma bangsa di Nusantara ini berubah.
Sebenarnya, setelah merdeka dari penjajahan, era pemerintahan Soekarno selaku Presiden Pertama RI sempat berambisi membangkitkan lagi kekuatan maritim Nusantara. Waktu itu Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Karya era pemerintahan Presiden Soekarno berjasa memperluas wilayah laut Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.
Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.
Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
"Dulu sebelum ada Deklarasi Djuanda, wilayah laut kita yang diakui oleh dunia itu hanya sejauh tiga mil dari pulau-pulau Indonesia. Visi maritim Soekarno amat tegas dan bisa dilihat pada Deklarasi Djuanda, Soekarno tak mau wilayah laut Indonesia seperti mozaik. Bisa dibayangkan jika tanpa Deklarasi Djuanda, maka kawasan antara Jawa dan Kalimantan ini akan menjadi laut yang bebas untuk dimasuki oleh siapapun," kata Yulian.
Sayangnya, perjuangan Soekarno ini tidak dilanjutkan dan tidak dimanfaatkan oleh rezim pemerintahan Presiden RI ke-2, Soeharto. Setelah Djuanda membuat pagar keliling yang menjadikan Indonesia bertambah luas itu, wilayah ini tidak dikelola dengan baik. Soeharto tidak punya orientasi pada pengembangan kekuatan maritim. "Soeharto justru fokus pada pengembangan dan pembangunan di daratan, makanya Indonesia disebut lagi sebagai negara agraris," kata Yulian.
Padahal, ia melanjutkan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Karena terlalu fokus di darat, maka kawasan laut Indonesia jadi terabaikan.
Akhirnya laut Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya orientasi maririm untuk kepentingan dengan cara ilegal. Yulian menuturkan, misalnya, banyak orang menjadi kaya di era Soeharto karena punya usaha di sektor pertambangan dan eksploitasi hutan. Kayu-kayu hasil penebangan liar (ilegal logging) yang banyak dilakukan di hutan Kalimantan dialirkan ke sungai dan selanjutnya melintasi laut.
"Nah, karena waktu itu orientasi bangsa ini tidak mau terlalu pusing dengan urusan di laut, jadinya bebaslah mereka (pelaku ilegal logging) ini bawa kayu-kayu itu ke luar negeri," kata Yulian.
Contoh lain, ia menambahkan, jaman Orde Baru banyak kapal-kapal besar melakukan pencurian ikan (ilegal fishing) di wilayah perairan dan laut Indonesia.
Ambisi Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dipandang hanya sekedar jargon. Hampir setahun pemerintahan Jokowi (sapaan Joko Widodo) belum ada gebrakan yang berarti untuk mewujudkan jargon kampanyenya itu.
Upaya Jokowi membenahi masalah waktu bongkar muat kapal sandar di pelabuhan (dwelling time) maupun proyek pembangunan pelabuhan dianggap bukan upaya memperkuat kekuatan maririm Indonesia.
"Marah-marah soal dwelling time itu bukan urusan maritim, itu lebih mengurusi masalah terminal. Soal rencana pembangunan 24 pelabuhan pun itu proyeknya bakal digarap oleh China (Tiongkok)," kata Yulian.
Ia menjelaskan, Indonesia membangun hubungan kerja sama dengan Tiongkok, khususnya di sektor kemaritiman. Namun, Yulian memprotes penyerahan pembangunan 24 pelabuhan kepada Tiongkok terkait dengan konsep tol laut untuk dibangun oleh Tiongkok dengan alasan investasi.
Pelabuhan laut, ia melanjutkan, adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya, apalagi Indonesia yang tentu sangat tergantung pada sistem transportasi laut.
Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, di mana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan pengelolaannya pun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization).
Tiongkok, menurut Yulian, sedang gencar mewujudkan Jalur Sutra melalui laut untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi mereka ke seluruh dunia termasuk Indonesia. "Saya curiga gagasan poros maritim Indonesia ini sambungan dari proyek Jalur Sutra maritim Tiongkok, untuk memuluskan kepentingan perdagangan Tiongkok," kata Yulian.
Cara membangun kekuatan sebagai negara maritim harus realistis. Indonesia ini ibarat bangunan maritim pondasinya masih amburadul. Jadi, ambisi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya akan menjadi mimpi belaka jika tidak ada pembenahan pondasi kebijakan yang nyata. Apalagi berharap Indonesia bisa bangkit lagi sebagai negara maritim hanya dalam tempo lima tahun atau satu periode pemerintahan kabinet.
Menurut Yulian, untuk membangun kembali puing-puing kekuatan maritim, waktu yang dibutuhkan Indonesia minimal seratus tahun. Membangun infrastruktur seperti pelabuhan adalah mudah. Tapi yang sulit adalah membangun fungsi infrastruktur tersebut.
Negara memiliki undang-undang sebagai dasar peraturan dan kebijakan. Kenyataannya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang tidak banyak yang bersinggungan dengan orientasi Indonesia sebagai negara maritim.
"Sudah berapa banyak aturan di negara yang mengatur tentang aktivitas maritim? Itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, sinkron atau tidak antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Undang-Undang Kelautan itu sinkron tidak dengan undang-undang yang lain," kata Yulian.
Jika memang Presiden Jokowi ingin mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim, maka prioritas agenda pemerintah adalah menata ulang kebijakan maritim. Sehingga implementasi kebijakan itu pada kegiatan maritim di lapangan tidak saling tumpang tindih.
Tulang punggung
Ketua Umum Indonesia National Ship-Owners Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bukan digerakkan oleh ekonomi maritim. Padahal sektor maritim seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang besar.
Posisi Indonesia sangat strategis karena diapit oleh dua lautan luas yakni Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik serta berada di antara dua benua yakni Asia dan Eropa. Ini membuat Indonesia menghubungkan pasar perdagangan utama di wilayah barat dan timur serta menikmati Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia.
"Posisi strategis ini membuat alur laut kita memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Kalau itu semua dioptimalkan, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat," kata Mey, sapaan Carmelita, kepada medcom.id di Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Namun, keberpihakan pemerintah terhadap pelayaran nasional masih sangat kecil. Terlihat dari banyak aturan-aturan yang memberatkan dunia pelayaran nasional.
Menurut Mey, keberpihakan pemerintah terhadap pelayaran nasional semestinya ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Perlu ada kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pelayaran nasional. Sebab, posisi pemerintah sangan menentukan kemajuan pelayaran nasional.
Dengan ada kebijakan yang kuat dan setara, akan terjadi akselerasi pelayaran nasional. Sehingga ke depan sektor ini memiliki daya saing di dalam negeri maupun di luar negeri. "Ini pada akhirnya membuktikan kuatnya sektor pelayaran dapat merepresentasikan kuatnya kedaulatan negara," kata Mey.
INSA berharap ada insentif bagi dunia pelayaran. Kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah diharapkan mendorong industri ini bertumbuh.
Sesungguhnya, menurut Mey, para pengusaha di sektor pelayaran nasional tidak butuh perlakuan khusus. Cukup perlakuan yang setara dengan negara-negara sekitar. Misalnya, kalau harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal di negara-negara tetangga tidak mahal, di Indonesia juga sebaiknya begitu.
"Apa-apa yang di negara tetangga tidak dikenai pajak, di Indonesia pun seharusnya begitu. Pemerintah harus mengubah mindset, bukan hanya sekedar menyesaki pengusaha dengan berbagai pajak. Tetapi bagaimana agar industri bertumbuh dan menghasilkan multiplier effect yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Mey.
Ia menambahkan, salah satu penyebab Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam mengembangkan industri maritim adalah karena kebijakan yang tidak bersahabat bagi para pengusaha. Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia dianggapp kurang berpihak bagi sektor pelayaran nasional.
"Kebijakan fiskal dan moneter ini menyebabkan daya saing industri pelayaran nasional menjadi menurun. Sedangkan di negara tetangga, kebijakan fiskal dan moneternya mendukung sektor pelayaran," kata Mey.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News