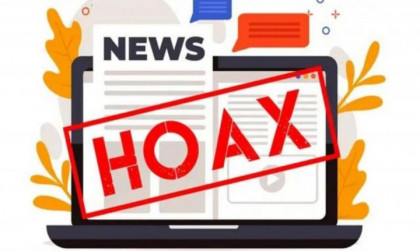medcom.id, Jakarta: Kemajuan industri selayaknya ditopang oleh penguasaan teknologi dan fundamental ekonomi yang kuat. Indonesia pernah menyiapkan kemajuan industri di era pemerintahan Presiden Soeharto. Ironisnya, saat baru memasuki tahap awal pembangunan menuju negara maju, Indonesia dihantam oleh krisis ekonomi. Alih-alih berubah menjadi negara maju, Indonesia malah terpuruk dalam krisis paling parah di antara negara berkembang lain di kawasan.
Di era Soeharto, teknologi komunikasi menjadi tonggak industri strategis dalam negeri. Alasannya, hubungan telekomunikasi dalam negeri masih menghadapi kendala. Penggunaan jaringan satelit untuk hubungan luar negeri menjadi kebutuhan utama sekaligus menjadi proyek teknologi pertama. Sehingga, setelah dua tahun menjabat Presiden RI, pada 1969 Soeharto meresmikan pengendali bumi satelit palapa Stasiun Bumi Jatiluhur. Pada pidatonya ia menekankan pentingnya sarana komunikasi bagi pembangunan bangsa di negara kepulauan.
Teknologi komunikasi modern pun dibangun, diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa, dibuat oleh Hughes Aircraff Company (sekarang Boeing Satellite Systems) bersama Perumtel Indonesia pada 1974.
Pada 8 Juli 1976, satelit yang dijuluki Palapa A1 itu akhirnya diluncurkan di Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat dan mengorbit di 83° Bujur Timur. Pada 16 Agustus 1976, satelit pertama Indonesia itu sudah dapat berfungsi. Keberhasilan ini menjadi perhatian dunia, Indonesia tercatat sebagai negara keempat yang memiliki satelit setelah Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Bahkan China dan India saja belum sempat memikirkan untuk memiliki satelit domestik.
Setelah Palapa A1, Indonesia terus meluncurkan satelit lainnya. Pada 11 Maret 1977 diluncurkan satelit Palapa A2 yang berfungsi sebagai cadangan yang siap digunakan apabila satelit Palapa A1 mengalami kerusakan atau gangguan. Satelit Palapa A1 dan A2 disebut sebagai satelit generasi pertama yang usia pakainya 7 tahun.
Pada 18 Juli 1983 diluncurkan lagi satelit Palapa B1 untuk menggantikan satelit Palapa A1 dan A2. Satelit ini diluncurkan dengan pesawat ulang-alik Challenger yang disusul dengan peluncuran satelit Palapa B2. Kawasan kerja satelit Palapa B2 meliputi negara-negara ASEAN dan Papua Nugini. Tanggal 20 Maret 1987 sateit Palapa B-2P diluncurkan. Selanjutnya berturut-turut diluncurkan satelit Palapa B-2R pada tanggal 20 Maret 1990, dan satelit Palapa B-4 pada tanggal 7 Maret 1992. Tanggal 16 Mei 1996 diluncurkan satelit Palapa C-1 untuk menggantikan posisi satelit sebelumnya.
Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan pertumbuhan ekonomi, industri strategis lainnya turut tampil ke permukaan, seperti IPTN (industri kedirgantaraan), PT PAL (industri perkapalan) dan PT Pindad (industri persenjataan). Kemampuan ini menjadi pertanda bahwa Indonesia secara perlahan-lahan dan dalam level tertentu akan segera keluar dari ketergantungan terhadap dunia barat dalam pengadaan sarana kedirgantaraan, transportasi laut dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kandas di era tinggal landas
Saat berpidato menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagai mandataris MPR dalam Sidang Umum MPR pada 1 Maret 1993, Presiden Soeharto optimistis bangsa Indonesia mampu tinggal landas menjadi negara yang sejajar dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju. Era tinggal landas adalah masa setelah Indonesia menyelesaikan program Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (PJP) Tahap I yang berlangsung sejak 1968 hingga 1993. PJP Tahap II direncanakan sejak 1993 – 2018.
“Dalam era tinggal landas ini kita harus mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju,” ujar Soeharto dalam pidato tersebut.
Berkat meningkatnya kemampuan teknologi serta kemampuan rancang bangun dan rekayasa nasional, katanya, industri kita sekarang sudah mampu menghasilkan barang-barang dengan teknologi canggih; seperti produk-produk rekayasa, elektronika, hasil-hasil kimia, pesawat terbang, kapal samudera, mesin pabrik, sampai pabrik yang utuh. "Yang sangat membesarkan hati adalah, makin banyak produk industri kita yang mampu bersaing dan menembus pasaran dunia,” ujarnya.
Kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang positif, menurut Soeharto, menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap melangkah maju ke tahap-tahap industrialisasi selanjutnya.
Pada pertengahan 1997 krisis moneter melanda Asia. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.
Perekonomian Indonesia, yang sebelumnya diklaim sehat, mendadak roboh. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri saat itu, Ginandjar Kartasasmita dalam bukunya berjudul Reinventing Indonesia, terperosoknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi biang krisis.
Dalam buku yang mengkaji krisis ekonomi tahun 1998 yang telah memicu reformasi politik dan perubahan sistem pemerintahan itu dijelaskan, masalah rupiah memicu lonjakan inflasi, terutama ada harga komoditas impor. Jatuh bebasnya kurs mengganggu hampir semua persendian ekonomi Indonesia.
Catatan PM Singapura
Pemerintah Singapura menjadi saksi betapa krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal 1997 berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik pada 1998. Antara lain ditandai dengan lumpuhnya kegiatan ekonomi karena jumlah perusahaan yang tutup terus bertambah dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.
Mendiang mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dalam buku memoarnya, From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000, menulis, menteri keuangan Indonesia saat itu ingin meminta bantuan IMF sebagai solusi krisis. Utusan Soeharto datang meminta dukungan Singapura agar posisi tawar Indonesia di mata IMF meningkat.
Saat itu Singapura setuju untuk membantu Indonesia sampai angka USD5 miliar, dengan catatan Indonesia sudah menggunakan pinjaman dari IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia senilai USD20 miliar dolar, juga menggunakan cadangan devisanya sendiri untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terpuruk lebih jauh.
Singapura juga berjanji akan membantu intervensi pasar uang jika Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan IMF. Paket bantuan IMF yang disiapkan untuk Indonesia mencapai USD40 miliar. Jepang juga sepakat untuk mendukung upaya meredam melorotnya nilai Rupiah dengan dana senilai USD5 miliar.
Indonesia akhirnya meneken kesepakatan dengan IMF pada 31 Oktober 1997, yang dikenal dengan Letter of Intent (LoI) jilid 1, diteken oleh Presiden Soeharto dengan Direktur IMF Michael Camdessus. Syarat dari IMF saat itu adalah, Indonesia menghentikan kegiatan infrastruktur dan melepas subsidi, khususnya pada industri strategis yang dianggap memakan banyak anggaran.
"Saat itu Indonesia diminta menunda 14 proyek infrastruktur termasuk yang dikendalikan oleh putri tertua Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan menutup 16 bank yang dianggap tidak sehat, salah satunya dimiliki oleh putra Soeharto," tulis Lee.
Namun, katanya lagi, ketika LoI dengan IMF ini dilanggar, dan Soeharto bersikeras melanjutkan proyek-proyek besar itu, pasar uang bereaksi negatif dengan aksi jual. Nilai tukar rupiah terus melorot.
Pada 6 Januari 1998, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN). Isinya beda dengan kesepakatan dengan IMF, dan tidak dibicarakan dengan lembaga multilateral itu. Dua hari kemudian rupiah anjlok dari Rp7.500 ke level Rp10.000 per dolar AS, melemah empat kali dibanding sebelum krisis.
APBN Indonesia dikritik oleh wakil direktur pengelola IMF Stanley Fischer dan wakil menteri keuangan AS Lawrence Summers, karena tidak memperhatikan kesepakatan dengan IMF.
Namun, untuk merangsang sentimen positif bagi pasar dan mencegah kerusuhan lebih parah di Januari 1998, yang bisa berdampak ke negara lainnya di kawasan, IMF setuju memberikan bantuan kembali. Pada 15 Januari 1998, mantan Presiden Soeharto meneken LoI kedua dengan IMF, yang isinya sejumlah paket reformasi ekonomi.
Lee bercerita, saat itu Lawrence Summers menyampaikan kepadanya, meminta praktik bisnis yang memberikan keistimewaan kepada keluarga dan teman dekat Soeharto harus diakhiri. Yang diperlukan adalah diskontinuitas cara Soeharto mengelola pemerintahannya saat ini. Semua pihak perlu mendapat kesempatan yang sama.
Intinya dalam memoar Lee banyak membahas bagaimana kepemimpinan Soeharto diganggu oleh masuknya anak-anak presiden ke bisnis yang sangat menjanjikan dan bersifat monopoli. Ini menjadi sorotan para manajer keuangan dunia, meskipun Soeharto bersikeras tak mau diintervensi siapapun terkait bagaimana dia mengelola ekonomi dan mengurus anak-anaknya.
Krisis ekonomi dan gunjang-ganjing politik kian memburuk meski LoI kedua diteken. Soeharto mengumumkan kriteria calon wakil presiden yang merujuk kepada figur Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie.
Lee menulis dalam bukunya, Habibie dikenal dengan proyek teknologi tinggi berbiaya mahal, seperti membangun industri pesawat terbang. Dia mengaku bahwa sejumlah pemimpin negara asing khawatir, pemilihan Habibie sebagai wakil presiden tak akan mampu memulihkan kepercayaan pasar.
Ketika Soeharto mengumumkan Habibie sebagai Wakil Presiden RI pada 14 Maret 1998, benar saja, rupiah melorot ke titik nadir, Rp17.000 per dolar AS, dan menyeret mata uang lain di kawasan ini, juga menghempaskan harga saham.
Gelombang Reformasi pun membesar hingga kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998. Inilah akhir cerita Pelita keenam yang kandas di tengah jalan.
Habibie, yang menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden RI Ketiga, ditekan untuk prioritaskan tuntutan reformasi dan selesaikan masalah krisis moneter. Syarat-syarat IMF pun turut diakomodir di masa pemerintahannya, di antaranya pembebasan tahanan politik dan membuka keran demokrasi seluas-luasnya, salah satunya Pemilu serta mengakhiri praktik-praktik monopoli era Orde Baru.
Penyelamatan APBN
Hal yang sama juga dirasa di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kegiatan industri tidak diutak-atik pasca turunnya syarat-syarat IMF di masa Soeharto dan Habibie. Pembangunan sosial politik berlandaskan demokrasi menjadi prioritas. Namun, wacana penjualan maupun privatisasi BUMN sudah muncul untuk mengamankan APBN.
Beban APBN membengkak ketika krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terutama terkait pelunasan utang luar negeri. Ini yang menjadi alasan pemerintah melakukan privatisasi BUMN pasca jatuhnya kekuasaan orde baru.
Setelah dihantam krisis moneter, perekonomian Indonesia tidak langsung pulih. Besarnya utang luar negeri yang diciptakan 30 tahun pemerintah orde baru sebesar USD120 miliar (1967-1997) menyebabkan beban bunga plus cicilan utang membengkak. Belum lagi inflasi yang tinggi, industri-industri bangkrut karena utang besar. Dalam situasi tersebut kesungguhan IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia dipertanyakan. Karena dalam menangani krisis ekonomi Indonesia, IMF menekan pemerintah untuk menjalankan program-program yang disarankan. Salah satunya, perluasan swastanisasi sektor-sektor strategis negara dengan menjual BUMN. Setiap LoI dengan IMF, selalu mensyaratkan jual aset ini dan jual aset itu.
Setelah Gus Dur jatuh pada 23 Juli 2001 melalui pencabutan mandat oleh MPR, kepemimpinannya digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Beberapa bulan setelah Megawati dilantik, munculah kebijakan-kebijakan baru yang dianggap sebagai langkah penyelamatan anggaran negara yang sebelumnya "jeblok".
Pada semester pertama pemerintahan Megawati, tujuh BUMN yang masih aktif dijual, yakni, PT Indosat, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Angkasa Pura II, dan PT Wisma Nusantara. Bahkan, perusahaan telekomunikasi negara, PT Telkom, diwacanakan untuk turut dilego.
Penjualan Indosat, pemegang kontrol Satelit Palapa, paling disoroti masyarakat. Pasalnya, dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Privatisasi Indosat mengundang kritikan tajam. Salah satunya, karena divestasi 41,94 persen saham PT Indosat melalui strategic sales hanya menghasilkan dana Rp5,6 triliun. Pengamat BUMN Djokosantoso Moeljono dalam bukunya berjudul Reinvensi BUMN menyebut bahwa privatisasi ini lebih terkesan "mengejar target" sehingga dilaksanakan dengan cara relatif tergesa-gesa dan mengutamakan nilai pembayaran daripada kestrategisan.
Lebih jauh ia menjelaskan dalam buku tersebut bahwa STT yang mengambil alih Indosat adalah anak perusahaan Temasek, BUMN milik Singapura, yang juga memiliki anak perusahaan Singapore Telecom (SIngtel) yang menguasai 35% saham Telkomsel, salah satu operator selular terbesar di Indonesia. Jadi, secara strategis, Indonesia boleh dibilang "kecolongan" dalam hal ini. Pertama, Indosat mempunyai nilai strategis sebagai perusahaan terdepan dan terbesar dalam sambungan telepon internasional Indonesia.
"Pengambilalihan ini merupakan pelepasan jaringan saraf global bagi Indonesia," ungkap Djokosantoso dalam bukunya.
Kedua, ia melanjutkan, dengan pengambilalihan ini, praktis Singapura melalui BUMN-nya relatif menguasai industri dua jasa layanan telekomunikasi selular di Indonesia, yaitu Satelindo dan Telkomsel yang diperkirakan menguasai sekitar 70% pangsa pasar.
Sementara itu, ia menambahkan, pertimbangan divestasi saham Indosat dilakukan atas dasar mulai surutnya bisnis telekomunikasi internasional dengan munculnya teknologi VOIP (voice over internet protocol) yang pada masa depan akan menjadikan komunikasi antarnegara menjadi sangat murah, dan Indosat dapat menjadi sunset industry. "Namun, hal yang menarik, laba Indosat setelah privatisasi justru meningkat," papar Djokosantoso.
Meski privatisasi di beberapa sektor masih dilakukan, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia berupaya membangunkan kembali industri strategis yang sempat mandul akibat krisis. Sebagai langkah revitalisasi, pemerintah menyuntikkan modal Rp1,9 triliun ke PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, dan PT PAL Indonesia, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan, di periode kedua era SBY, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyetujui pembelian Satelit untuk kepentingan perbankan BRI.
Hingga era Presiden Joko Widodo saat ini, geliat industri strategis masih terjaga. Belakangan, PT DI mulai dibanjiri pesanan, bahkan kapal produksi PT PAL ditaksir Filipina dan berhasil terjual. PT Pindad pun mengalami hal serupa, tak hanya persenjataan berat seperti tank, persenjataan ringan buatan Pindad turut menarik perhatian dunia. Salah satu permintaan terbesar senjata yang digunakan TNI itu datang dari Timur Tengah.
Selain itu, di dunia perbankan, Bank BRI sukses membeli satelit untuk kepentingan perbankan lokal. Hal ini menjadikan BRI sebagai Bank pertama di dunia yang memiliki satelit dalam operasionalnya. Pertengahan Juni 2016 ini, satelit yang dinamakan BRIsat itu siap mengangkasa, menempati kavling satelit Palapa milik Indosat yang telah habis masa edarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Petugas memeriksa satellite receiver di Kantor PT Indosat Jl Daan Mogot KM 11, Jakarta Barat. (MI/Rommy Pujianto)
Satelit, Krisis Ekonomi, dan Privatisasi
Coki Lubis • 06 Juni 2016 20:22
LEAVE A COMMENT
LOADING