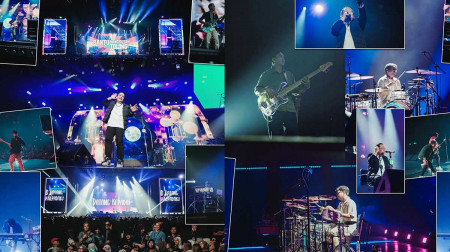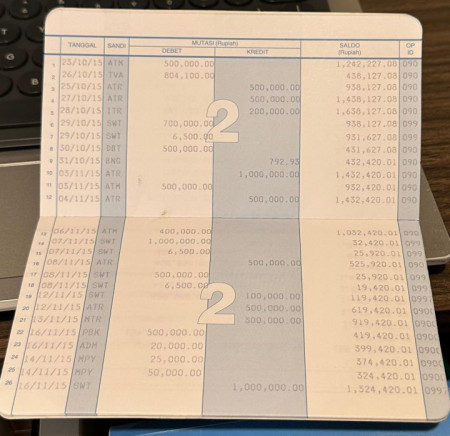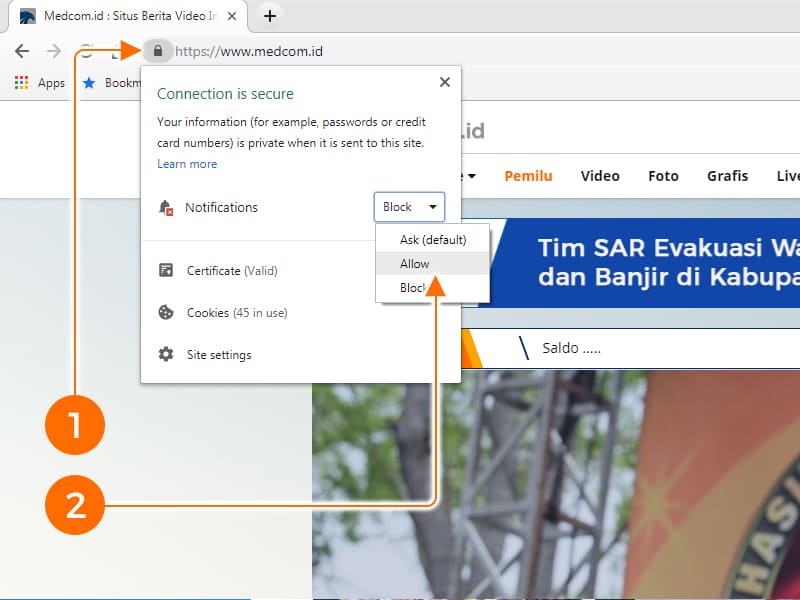Oleh Nono Sampono, anggota terpilih DPD 2014-2019 dari Provinsi Maluku
Artikel ini diambil dari Media Indonesia edisi Selasa, 30 September 2014.
INDONESIA secara geografis terdiri dari 17.508 pulau yang dipersatukan lautan yang lebih luas daripada seluruh daratannya dan itu merupakan anugerah yang nyata. Menjadi Indonesia berarti menjadi bangsa lautan: bangsa maritim.
Inilah karakter pertama dan utama bangsa Indonesia. Kenyataan belasan ribu pulau itu dihuni 1.304 suku bangsa ialah juga takdir Indonesia yang tidak bisa diingkari. Keragaman dan perbedaan suku bangsa serta agama, tetapi tetap berada dalam persatuan, menjadi khas Indonesia.
Bangsa maritim yang Pancasilais kemudian menjadi karakter Indonesia yang sesungguhnya. Karena itu, seluruh usaha memajukan bangsa demi memenuhi janji Konstitusi RI harus bertolak dari dua paduan karakter yang tidak bisa dipisahkan ini.
Karakter kepribadian Pancasila sekaligus menyadari hidup di negara maritim, sadar akan wilayah hidupnya. Namun, harus diakui, kesadaran hidup di negara maritim ini belum lagi meresap ke setiap pribadi anak bangsa. Lapisan tebal kesadaran orang Indonesia masih merasa sebagai bangsa daratan yang hidup dari bercocok tanam. Rumah Indonesia masih menghadapkan mukanya ke bukit dan gunung dengan 'pulau-pulau terluar' sebagai serambi belakang serta lautan seolah bukan bagian dari Nusantara.
Perhatikan ini, orang daratan (kontinental) menyebut pulau-pulau yang jauh dari daratan sebagai 'pulau terluar' sementara orang lautan (maritim) akan menyebutnya sebagai 'pulau-pulau terdepan'. Perbedaan pandangan dan penilaian yang sangat mendasar itu membawa konsekuensi yang krusial.
Bagi kesadaran kontinental, pulau-pulau terluar atau daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga identik dengan kemiskinan, ketertinggalan, kesulitan sarana hidup, dan kurang mendapat perhatian, untuk tidak menyebut terabaikan. Lain halnya dengan kesadaran maritim, yang akan melihat pulau-pulau terdepan dan daerah perbatasan itu (batas laut terutama) sebagai pintu-pintu harapan, gerbang kemajuan.
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 81.000 km, atau 14% dari garis pantai seluruh dunia. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2, atau mendekati 70% dari luas keseluruhan Indonesia, sementara luas daratan Indonesia hanya sekitar sepertiga luas lautnya: 1.922.570 km2. Secara geografi s RI memiliki perbatasan laut dengan 10 negara.
(1) Ujung utara Pulau Sumatra, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berbatasan dengan India, dengan pulau terdepan ialah Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, dan Pulau Rondo. (2) Sepanjang Selat Malaka, yang termasuk ke wilayah Provinsi Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan dengan Malaysia, dengan pulau-pulau terdepan ialah Pulau Berhala di Sumut, Pulau Anambas di Provinsi Riau, dan Provinsi Sebatik di Kalimantan Timur. (3) Ada Pulau Nipah, Provinsi Riau, sebagai pulau terdepan yang berbatasan dengan Singapura di sepanjang Selat Philip. (4) Di bagian utara Selat Malaka dan Laut Andaman, ada Pulau Rondo, Provinsi Aceh, sebagai pulau terdepan, berbatasan dengan Thailand.
(5) Pulau Sekatang, Kepulauan Riau, berbatasan dengan Vietnam di daerah Laut China Selatan. (6) Daerah utara Selat Makasar, dengan pulau terdepannya ialah Pulau Marore dan Pulau Miangas, Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina. (7)Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Bras, Papua, di utara Laut Halmahera, berbatasan dengan Republik Palau. (8) Di sekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa berbatasan dengan Australia. (9) Sekitar wilayah Maluku dan NTT berbatasan dengan Timor Leste dengan pulau terdepan ialah Pulau Asutubun dan Pulau Wetar, Provinsi Maluku, serta Pulau Batek, Provinsi NTT. (10) Jayapura dan Merauke, tidak memiliki batas laut dan pulau terdepan, berbatasan dengan Papua Nugini.
Setiap daerah perbatasan tentu memiliki masalahnya yang khas. Namun, jika dikelompokkan, mereka bisa dicakup ke dalam enam aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan (mencakup kelembagaan, kewenangan pengelolaan, serta hubungan antarnegara).
Keenam aspek itu sesungguhnya ialah persoalan yang bisa ditangani seandainya Indonesia memiliki kebijakan maritim (ocean policy) yang jelas dengan paradigma bangsa dan negara maritim tentu saja. Indonesia Ocean Policy sampai sejauh ini masih berupa rintisan yang belum mendapat tindak lanjut secara serius.
Secara ekonomi dan sosial budaya, akibat dari paradigma daerah perbatasan sebagai halaman belakang (kontinental), kondisi daerah perbatasan hingga saat ini masih terisolasi, tertinggal secara sosial dan ekonomi. Daerah perbatasan selalu dipahami sebagai kawasan untuk mengamankan potensi ancaman dari luar dengan kecenderungan memosisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengaman.
Akibatnya, pendekatan pengelolaan terhadap daerah perbatasan kurang memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakatnya, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam di daerah setempat misalnya. Ini terjadi di daerah perbatasan daratan. Masalah lanjutannya kemudian ialah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga yang demikian jelas.
Masyarakat daerah perbatasan di daratan Kalimantan dan Sulawesi Utara begitu mudah berkiblat ke kemajuan yang dicapai negara tetangga karena mereka melihat kehidupan sosial dan ekonomi di seberang sana yang lebih maju.
Di kawasan perbatasan laut, masalah utamanya menyangkut isu pertahanan, hubungan antarnegara, dan lingkungan. Di perbatasan Indonesia-Singapura ada masalah penambangan pasir laut di sekitar perairan Kepulauan Riau yang telah berlangsung sejak 1970. Jutaan ton pasir terus dikeruk, berakibat pada kerusakan lingkungan dan bergesernya batas pantai.
Batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Kesepakatan batas maritim antara Indonesia dan Filipina pun belum ada. Demikian juga penentuan batas baru Indonesia-Australia belum ada tindak lanjut menyangkut wilayah Celah Timor yang harus dibahas secara trilateral bersama Timor Leste.
Indonesia dengan Papua Nugini memang sudah menyepakati batas-batas wilayah darat maupun maritim. Namun, masih ada kendala kultur yang bisa menimbulkan salah pengertian. Ada kesamaan budaya dan ikatan keluarga di antara penduduk di kedua negara ini. Klaim-klaim tradisional akan memunculkan masalah yang rumit dan berkepanjangan di kemudian hari.
Masalah batas-batas maritim Vietnam di wilayah Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara kedua negara, mengingat jarak di antara kedua pulau itu tidak lebih dari 245 mil. Soal batas maritim juga masih belum diselesaikan secara tuntas dengan India, antara Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
Dengan Thailand, soal batas maritim tidak begitu kompleks karena jarak di antara pulau terdepan tiap negara berjauhan dan ada perjanjian BLK yang mengikat. Hanya, masih ada masalah penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia.
Isu perbatasan dan daerah-daerah perbatasan di Indonesia ialah pekerjaan rumah yang paling mendesak untuk segera dikerjakan demi menegaskan Indonesia sebagai bangsa dan negara maritim. Indonesia Ocean Policy ialah langkah awal yang cukup menyeluruh, yang kian nyata urgensinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Nono Sampono/MI/GINO F HADI. ()