PEMILU itu ibarat pertandingan sepak bola. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit dan ada pula partai politik yang berperan sebagai pemain. Apa jadinya jika pemain merangkap wasit?
Pemain merangkap wasit menjadi wacana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. RUU yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu masuk Program Legislasi Prioritas 2021 di DPR.
Salah satu pasal dalam revisi itu mengatur keterwakilan partai politik dalam komposisi keanggotaan KPU. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) RUU Pemilu.
Disebutkan dalam ayat itu bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan partai politik secara proporsional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
Harus tegas dikatakan bahwa pemain merangkap wasit dalam pemilu mengingkari konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Asas jujur dan adil dalam pemilu hanya bisa terwujud jika penyelenggaranya tidak diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan berbagai kepentingan. Karena itulah, Pasal 22E ayat (5) menyebutkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Mandiri maksudnya penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu justru mengkhianati hakikat pemilu yang jujur dan adil.
Elok nian bila pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, konsisten menjalankan amanat konstitusi, jangan membajaknya hanya untuk kepentingan sesaat dan sesat pula.
Pengalaman pahit Pemilu 1999 harus dijadikan pelajaran. Ketika itu anggota KPU berjumlah 53 orang terdiri dari 48 wakil partai peserta pemilu dan 5 wakil pemerintah. Kepentingan politik wakil partai di KPU menyebabkan hasil Pemilu 1999 terlambat diumumkan sehingga pengesahan Pemilu 1999 diambil alih Presiden Habibie.
Terus terang, pengalaman pahit Pemilu 1999 itulah yang menjadi dasar keinginan politik untuk menolak partai politik menjadi komisioner KPU. Kemauan politik itu dikukuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 81/PUU-IX/2011.
MK menyatakan adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan jika pemilu diselenggarakan lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta pemilu itu sendiri.
Peserta pemilu ialah partai politik, menurut MK, maka undang-undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.
Jika kini pembuat undang-undang membuka peluang partai politik menjadi komisioner KPU, sama saja melawan dengan penuh kesadaran putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Jika itu tetap dilakukan, undang-undang yang dihasilkan niscaya digugurkan MK pada saat ada pihak yang mengajukan uji materi.
Pikiran-pikiran untuk kembali menggoda netralitas KPU sebaiknya dibuang ke laut saja karena berpotensi mencederai demokrasi. Integritas KPU sebagai badan independen mestinya diperkuat dan dijaga, bukan malah dirusak. Jika pemain merangkap wasit, pertandingan menjadi kacau-balau.
(Editorial Media Indonesia Jumat, 29 Januari 2021)
Cek Berita dan Artikel yang lain di 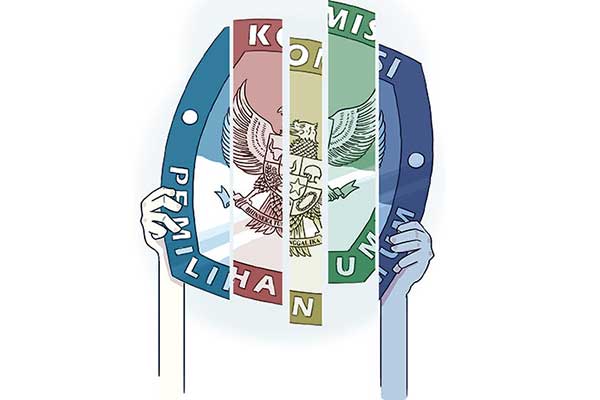
Ilustrasi. MI/Duta (Media Indonesia)
























