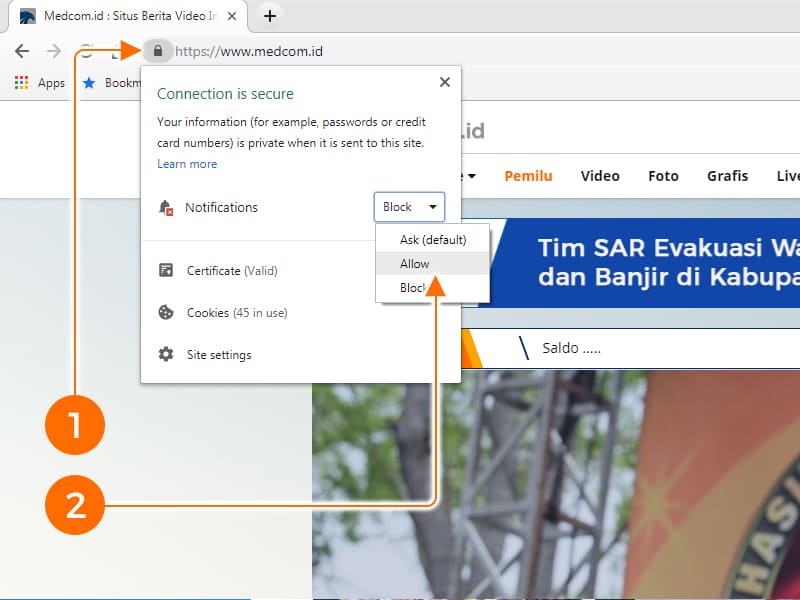Kita semua merasakan pandemi ini membawa dampak ekonomi dan sosial yang tidak baik bagi kehidupan. Salah satu kebijakan penting yang diambil pemerintah untuk menghambat penyebaran Covid-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
PSBB setidaknya diikuti penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum lainnya. Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat penyebaran Covid-29 menjadi wilayah yang pertama kali menjalankan PSBB, lalu diikuti beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Mengapa harus melakukan PSBB? Mari kita lihat dari perspektif ekonomi. Di dalam teori ekonomi ada istilah pilihan atas keputusan yang tidak mudah dilakukan atau nontrivial option-value. Jika kita dihadapkan pada situasi ekonomi dengan ketidakpastian yang tinggi (high economic uncertainty) seperti pandemi Covid-19 ini, maka semua strategi ekonomi yang dipilih bukanlah pilihan yang mudah, karena biaya dan manfaat yang tidak sebanding. Memilih membiarkan masyarakat melakukan aktivitas secara normal akan membahayakan kehidupan, namun memilih membatasi aktivitas dan mobilitas pun akan membahayakan perekonomian.
Lalu strategi apa yang sebaiknya diambil dalam situasi penuh ketidakpastian? Kembali lagi pada teori ekonomi, jika kita berada dalam situasi dengan ketidakpastian yang tinggi, namun harus membuat keputusan tanpa mengetahui hasil pasti dari keputusan itu, maka pendekatan teori utilitas yang diharapkan (theory of expected utility) dapat diadopsi.
Menurut teori ini, pada saat kita memilih suatu tindakan ekonomi, kita akan memilih tindakan yang akan menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan. Sejarah pandemi global menunjukkan, pembatasan aktivitas manusia adalah pilihan yang menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan.
Pembatasan aktivitas manusia
Jadi mari kita pahami bahwa mengacu pada teori utilitas yang diharapkan, membatasi aktivitas manusia merupakan stratregi yang dapat memberikan utilitas terbaik dalam situasi ketidakpastian. Pemerintah di berbagai negara lalu mengambil pilihan tersebut, termasuk pemerintah Indonesia.
Pembatasan aktivitas manusia ada yang radikal seperti lockdown dan shutdown secara masif pada berbagai aktivitas ekonomi. Ada pula yang moderat seperti di Indonesia, yaitu PSBB yang membatasi aktivitas manusia berskala besar, namun masih memberi izin kegiatan ekonomi yang bersifat essential.
Sekarang mari kita telaah biaya ekonomi dari PSBB. PSBB telah menciptakan guncangan (shock) terhadap perekonomian, yaitu guncangan pada produksi (supply shock) dan guncangan pada permintaan (demand shock).
Pada masa pandemi ini, kedua guncangan ini bersifat negatif (negative shock). Guncangan produksi yang bersifat negatif adalah situasi di mana kapasitas produksi dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami penurunan, menyebabkan penawaran agregat menurun. Guncangan negatif ini terjadi karena PSBB menyebabkan berbagai sektor menghentikan atau mengurangi volume produksi, pengurangan tenaga kerja.
Pengurangan tenaga kerja juga terjadi karena turunnya permintaan barang dan jasa sebagai akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Penyebab lain adalah faktor risiko kesehatan dan keselamatan karyawan menyebabkan penutupan produksi.
Guncangan produksi juga terjadi karena ada karyawan yang tidak dapat bekerja karena dalam perawatan atau karena merawat anggota keluarga yang terpapar Covid-19. Adapula karyawan yang tidak dapat bekerja karena pembatasan perjalanan dan upaya karantina.
Guncangan tenaga kerja
Guncangan dari sisi produksi ini disebut juga guncangan pada pasar tenaga kerja (labour supply shock). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 20 April 2020, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK sebanyak 2,8 juta orang, terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat.
Jumlah PHK yang dirilis Kemenaker ini sebagian besar adalah PHK di sektor formal. Jumlah PHK yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar dari jumlah ini, karena pekerja pada sektor informal lebih rentan terkena dampak pandemi Covid-19.
Guncangan kedua terjadi pada sisi permintaan atau demand shock. Guncangan permintaan yang negatif terjadi karena penurunan kemampuan atau kemauan konsumen untuk membeli barang dan jasa, menyebabkan permintaan agregat menurun. Guncangan permintaan dapat juga terjadi sebagai dorongan dari sisi produksi.
Pekerja yang terkena PHK akan kehilangan pendapatan, sehingga permintaan agregat terhadap barang dan jasa berkurang. Selain itu, pembatasan mobilitas masyarakat juga telah mengubah pola konsumsi masyarakat dan mengurangi permintaan secara drastis pada hampir semua sektor. Penyebaran Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir, juga mendorong sikap hati-hati masyarakat dalam melakukan spending dan cenderung mengurangi kemauan belanja dan menunda belanja yang tidak perlu.
Apabila guncangan pada produksi lebih besar dari guncangan pada permintaan, maka tekanan inflasi akan terjadi. Sebaliknya, apabila permintaan turun lebih besar dari penurunan produksi agregat, maka deflasi yang akan terjadi, keduanya menjadi beban perekonomian.
PDB anjlok
Pada saat guncangan produksi dan guncangan permintaan yang negatif terjadi bersamaan, maka PDB akan anjlok secara signifikan. Kondisi seperti ini yang sedang kita alami. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2020 (Januari, Februari, Maret) adalah 2,97%, terkontraksi sebesar 2,41% dari kuartal IV 2019.
Kinerja ekonomi di kuartal II 2020 (April, Mei, Juni) diperkirakan akan lebih rendah karena PSBB di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah baru dimulai awal April hingga awal Mei 2020. PSBB di wilayah ini mendorong guncangan produksi dan permintaan secara nasional karena kontribusi provinsi-provinsi ini terhadap pembentukan PDB nasional mencapai lebih dari 59%.
Selain itu, apabila konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB nasional mengalami guncangan, maka PDB akan terkontraksi secara tajam. Kontraksi PDB akan membawa masalah ekonomi dan kemanusiaan, dan menjadi opportunity cost yang mahal dari PSBB.
Sekarang kita paham bahwa PSBB diikuti opportunity cost. Kemudian dalam beberapa pekan terakhir, imbauan pemerintah untuk bersiap masuk dalam tatanan hidup "normal baru" (the new normal) semakin menguat.
Di dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada tanggal 7 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan Covid-19.
Moda transportasi komersial kembali beroperasi setelah masa PSBB. Lalu Kementrian BUMN dan Aparatur Sipil Negara dipersiapkan untuk bekerja dalam situasi normal yang baru. Di masa pandemi Covid-19 ini, hidup dalam "normal baru" dapat diartikan bahwa kita menjalani aktivitas sehari-hari meski Covid-19 belum teratasi.
Dalam kondisi normal yang baru ini, kita harus menerapkan dan mematuhi pedoman kesehatan agar terhindar dari Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah merilis Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap Covid-19 dengan judul Menuju Situasi ‘Normal Yang Baru’ tertanggal 16 Mei 2020. Meski dokumen ini ditujukan untuk kepala gugus tugas Covid-19, pada "normal baru" tersebut.
Normal baru
Pertimbangan pemerintah mengajak masyarakat hidup dalam "normal baru" dapat juga kita telusuri melalui konsep opportunity cost yang sangat populer di dalam teori ekonomi. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh David L. Green pada tahun 1894 dan dikembangkan oleh ekonom Austria Friedrich von Wieser (1911).
Dalam pandangan mereka, opportunity cost disebut juga biaya alternatif yang dihadapi individu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sementara keinginan atau kebutuhan individu tidak terbatas. Apabila sumber daya terbatas, maka untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas, individu harus menggunakan berbagai alternatif dan di sinilah individu perlu memilih.
Dalam pemikiran Green dan Wieser, opportunity cost berarti sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan manfaat terbaik dari sesuatu lainnya atau berupa nilai dari alternatif terbaik yang menjadi pilihan individu dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Ilustrasi sederhana, saat kita memutuskan menggunakan sumber daya pada aktivitas ekonomi A, maka kita tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas B ataupun aktivitas ekonomi lain pada waktu yang hampir bersamaan.
Tetapi ketika kita memutuskan alokasi sumber daya pada aktivitas ekonomi A, seharusnya pertimbangan kita sudah sangat matang, bahwa aktivitas A itu akan memberikan manfaat terbaik. Opportunity cost selalu diikuti kerelaan kita untuk kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari berbagai pilihan (what you have to give up to get something). Demikian pula bagi pemerintah, ketika memutuskan untuk mengajak masyarakat bersiap memasuki hidup dalam "normal baru", ada manfaat lain yang akan dikorbankan dari pilihan kebijakan tersebut.
Situasi yang tidak sama namun relatif mirip dengan pandemi Covid-19 adalah pandemi flu di tahun 1918 atau dikenal the Spanish Flu yang menelan korban hingga 50 juta jiwa secara global. Sejarah mencatat gelombang kedua pandemi yang terjadi lebih dari 100 tahun lalu tersebut lebih mematikan dibanding gelombang pertama.
Wabah Spanish flu
Sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Correia, Luck dan Verner (2020) di 43 kota di Amerika Serikat saat wabah Spanish Flu, menemukan bahwa kota yang melakukan pembatasan kegiatan dan interaksi fisik manusia yang lebih lama mampu melakukan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Kota-kota yang pulih lebih cepat tersebut setidaknya melakukan physical distancing sekitar 120 hari, dengan rata-rata selama 88 hari.
Sebaliknya, kota-kota yang melakukan physical distancing kurang dari 60 hari mengalami pemulihan ekonomi yang lebih lama. Studi ini juga menemukan bahwa membuka kembali aktivitas ekonomi dan melakukan pelonggaran interaksi fisik manusia lebih awal akan berdampak buruk bagi perekonomian.
Berkaca dari temuan Correia, Luck dan Verner (2020), sebenarnya kita berharap bahwa pembatasan interaksi fisik dan sosial manusia dalam bentuk PSBB dapat diperpanjang, paling tidak lebih dari 60 hari. Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak pun belum mengalami penurunan secara signifikan hingga minggu keempat Mei 2020.
Namun ketika pemerintah memutuskan untuk mengajak masyarakat bersiap memasuki pola hidup baru, seharusnya pemerintah telah memperhitungkan bahwa opportunity cost untuk melakukan pola kehidupan baru akan memberi manfaat tertinggi relatif terhadap berbagai alternatif kebijakan lain yang dapat dipilih pemerintah.
Mungkinkah hal tersebut dicapai? Dalam perspektif ekonomi, opportunity cost akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila ada kerja sama yang baik di antara pihak-pihak terkait, manfaat terbaik bersifat relying on others.
Jadi, mari kita membantu pemerintah memastikan opportunity cost yang minimal dari keputusan untuk memasuki pola hidup baru. Memulai tata kehidupan yang baru harus menjadi bentuk tindakan dan tanggung jawab bersama (collective action and responsibility).
Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua, dan keberhasilan collective action ditentukan oleh rasa saling percaya (mutual trust). Masyarakat harus memiliki trust kepada pemerintah bahwa imbauan bersiap masuk ke situasi ‘new normal’ akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menjaga trust ini dapat kita lakukan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk skenario hidup dalam ‘new normal’. Di sisi lain, pemerintah harus mampu menjaga rasa percaya dari publik (public trust) dengan menunjukkan konsistensi informasi dan kebijakan dalam mengangani Covid-19.
Jika ini dapat dilakukan bersama, bukan tidak mungkin, inilah pilihan kebijakan yang memberikan opportunity cost terbaik dalam situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, kita perlu memastikan kontribusi dan disiplin diri untuk mencapai opportunity cost yang paling minimal, jika kita harus memulai ‘new normal’ di masa pandemi Covid-19 ini.[]
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.