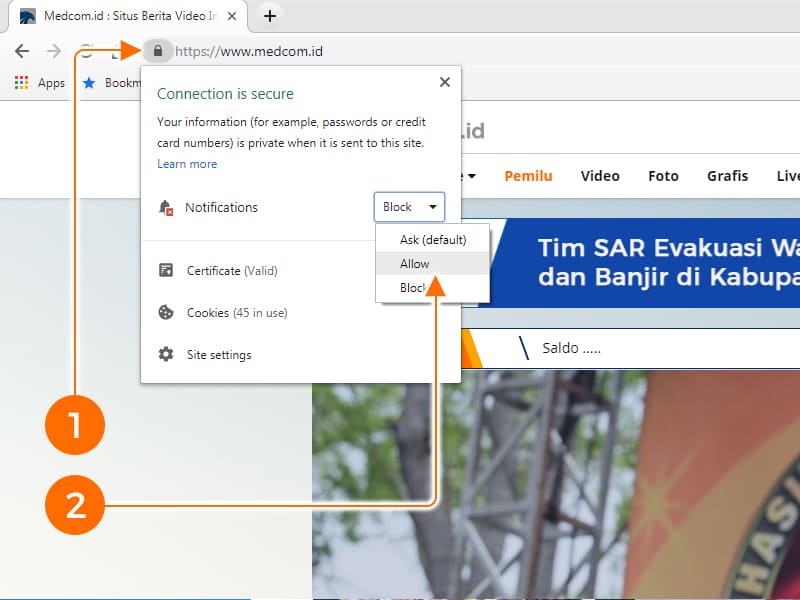A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
PRESIDEN Joko Widodo tampaknya sadar benar bahwa Indonesia harus memperkecil dengan cepat ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Pemahaman ini sudah benar.
Berkaca dari pengalaman Tiongkok, mereka boleh dibilang baru mulai membangun perekonomiannya sejak era Deng Xiao Ping, pada 1979.
Salah satu yang dikebut Tiongkok ialah membangun infrastruktur secara masif.
Mereka bahkan memiliki belanja pembangunan infrastruktur hingga 10% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Padahal, level yang sudah dianggap baik oleh konsensus para ekonom dunia 'hanya' 5% terhadap PDB.
Sejauh ini Indonesia hanya bisa membelanjakan di bawah 3% terhadap PDB.
Masih jauh di bawah ideal.
Shanghai dan Beijing juga baru bisa mulai membangun kereta bawah tanah (subway) pada 1993 atau relatif tertinggal dibandingkan kota-kota besar lain di dunia.
Bahkan Singapura sudah lebih dulu mulai memilikinya pada 1988. Namun, saat ini Shanghai dan Beijing telah memiliki jalur kereta bawah tanah lebih 500 km atau yang terpanjang di dunia.
Jakarta yang kini tengah membangunnya, baru akan memiliki mass rapid transit (MRT) sepanjang 27 km, yang terdiri dari 15 km di bawah tanah dan 12 km di atas tanah.
Banyak buruknya
Tiongkok mulai menuai dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi di atas 10% pada periode 2001-2008.
Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mereka mulai terkoreksi karena terkena krisis ekonomi global.
Pada 2015, pertumbuhan ekonomi Tiongkok 'hanya' 6,9%. Masih tinggi, tetapi termasuk rendah untuk ukuran mereka.
Mengapa infrastruktur menjadi hal terpenting untuk dikebut? Setidaknya ada tiga argumentasi kunci.
Pertama, keberadaan infrastruktur akan meningkatkan daya saing.
Kemacetan yang setiap hari terjadi di Jakarta misalnya, telah menyebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Begitu pula di jalur pantai utara Jawa.
Kedua, buruknya infrastruktur ikut menyumbang secara signifikan terhadap inflasi.
Jalanan yang rusak di sepanjang pantai utara Jawa dan lintas Sumatra misalnya, menyebabkan inflasi sulit dikendalikan pada level rendah.
Kalaupun inflasi pada 2015 yang berhasil ditekan ke 3,35%, itu lebih banyak disebabkan oleh lesunya hasrat masyarakat mengonsumsi akibat trauma pelemahan rupiah (sebaliknya apresiasi dolar AS) daripada karena lancarnya distribusi barang.
Ketiga, kendala infrastruktur menyebabkan investor terhambat untuk merealisasikan rencana investasinya.
Dalam teori pembangunan dikenal variabel ICOR (incremental capital-output ratio), yakni perbandingan antara berapa unit tambahan modal yang mesti disuntikkan untuk menambah output sebesar 1 unit.
Semakin besar ICOR, semakin kurang efisien suatu negara.
Di antara negara-negara yang selevel di regional ASEAN, ICOR Indonesia lebih tinggi daripada Thailand, Malaysia, apalagi Singapura.
Akibatnya, Indonesia kalah atraktif sebagai destinasi investasi (investment venue) dibandingkan ketiga negara itu.
Biasanya, penyebab utama besarnya ICOR sebuah negara berkembang ialah buruknya infrastruktur, lemahnya kualitas sumber daya alam, dan belitan birokrasi yang tidak efisien.
ICOR Indonesia sekitar 5, sedangkan Malaysia dan Thailand sekitar 3.
Dalam konteks inilah, masalah waktu tunggu kontainer di pelabuhan sebelum bisa masuk kapal (dwelling time) menjadi krusial.
Presiden Joko Widodo sudah benar terus menagih kepada anak buahnya (belakangan ini kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli) agar dwelling time bisa dipangkas, setidaknya mendekati level pelabuhan di Malaysia dan Thailand, kalaupun belum bisa menyamai Singapura yang hanya 1-1,5 hari.
Berbagai upaya ditempuh Presiden Joko Widodo untuk mendorong efisiensi dalam proses produksi perekonomian Indonesia, yang terkait dengan infrastruktur.
Saya juga terus tertegun melihat kemajuan pembangunan kereta bawah tanah yang membelah Jalan Thamrin dan Sudirman, Jakarta.
Rasanya tidak sabar untuk segera melihatnya beroperasi pada paling cepat Agustus 2017.
Namun, di tengah-tengah keasyikan menyaksikan berbagai proyek infrastruktur yang tengah digarap, saya justru terperangah menyaksikan ground breaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Semula saya berpikir proyek ini bakal dibatalkan, tatkala pemerintah menyatakan kedua peserta tender (Jepang dan Tiongkok) gagal, karena kedua proposal sama-sama menggunakan dana pemerintah (APBN).
Setahu saya, sebelum tender dilakukan hal ini tidak pernah disinggung.
Tapi okelah, menurut saya, pemerintah tetap boleh saja menambah klausul baru itu.
Ini mungkin ide dadakan, tapi saya masih bisa mengerti.
Tak lama kemudian, entah bagaimana prosesnya (karena tak pernah dinyatakan secara terbuka), tiba-tiba muncul berita bahwa proyek itu jadi dilaksanakan tanpa dana APBN.
Diperkirakan nilai proyeknya Rp75 triliun. Sebagai perbandingan, terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang hampir selesai, biayanya 'hanya' Rp6 triliun, sedangkan MRT Jakarta juga 'cuma' Rp30 triliun.
Sepintas, jika tidak dicermati benar, pemerintah akan bebas dari risiko bisnis yang mungkin timbul dari proyek ini, karena sepenuhnya ditangani secara business to business.
Konkretnya, proyek ini didanai oleh BUMN dan pihak Tiongkok. Pemerintah tak perlu menanggung risiko apa pun.
Benarkah?
Tunggu dulu.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, saya tetap belum bisa diyakinkan tentang kelayakan proyek tersebut.
Sebagai perbandingan, kereta cepat Shinkansen di Jepang, misalnya, terbentang melalui kota-kota industri utama di negeri itu.
Rute Tokyo-Osaka sepanjang 400 km dapat ditempuh dengan tempo 2 jam (berarti rata-rata kecepatan hanya 200 km/jam meski kereta bisa ngebut hingga lebih dari 300 km/jam).
Kota-kota yang disinggahi ialah Yokohama (kota pelabuhan terbesar Jepang), Nagoya (kota di mana Toyota berpusat), dan Kyoto (kota kebudayaan terbaik di Jepang).
Kondisi ini sangat kontras dengan rute Jakarta-Bandung yang hanya melalui kota-kota kecil seperti Karawang dan Walini.
Presiden Jokowi berharap kereta cepat akan menciptakan kota-kota satelit atau pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalur yang dilewati.
Masalahnya, apakah masih penting membuat pusat pertumbuhan baru di sekitar wilayah tersebut?
Ada keraguan
Jika kita bandingkan dengan kondisi kereta cepat di Tiongkok, hasilnya juga sama saja, alias tidak sebanding. Rutenya ialah Shanghai-Beijing yang berjarak 1.463 km (kereta api) atau 1.262 km (jalan raya).
Kedua kota ini merupakan yang terbesar di Tiongkok, penduduknya masing-masing sekitar 30 juta orang.
Dengan kata lain, kereta cepat di Tiongkok layak karena kombinasi antara potensi ekonomi kedua kota yang dihubungkan dan jaraknya yang cukup jauh sehingga kecepatan kereta bisa digeber secara ideal.
Contoh-contoh di Jepang dan Tiongkok itu menunjukkan bahwa kondisinya berbeda dengan rute Jakarta-Bandung yang jaraknya hanya 142 km.
Kereta cepat tampaknya tidak cukup tepat (inappropriate) untuk rute ini.
Di Jepang, harga tiket Shinkansen Tokyo-Osaka setara Rp1,5 juta (kelas ekonomi) dan Rp2 juta (bisnis), sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan harga tiketnya Rp200 ribu pada 2019.
Namun, ini masih berpotensi naik.
Masalah kedua yang saya ragukan ialah segala konsekuensi finansial yang timbul pada proyek ini tidak dibebankan pada APBN.
Benarkah?
Secara formal, beban diberikan kepada operator patungan bernama PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC).
Namun, jika perusahaan ini di kemudian hari ternyata tidak menguntungkan, BUMN-BUMN yang terlibat di dalamnya bisa saja mengalami kekurangan modal sehingga perlu penyertaan modal negara (PMN).
Jika ini terjadi, mau tidak mau pasti harus meminta injeksi dana APBN.
Jadi, sesungguhnya proyek kereta cepat ini tidaklah benar-benar steril dari APBN.
Dalam kondisi tertentu, secara tidak langsung APBN tetap akan berpotensi terlibat.
Ke depan, pemerintah tetap harus terus fokus membangun infrastruktur. Ini hal yang tak boleh ditawar-tawar.
Namun demikian, pemerintah harus tetap mengedepankan skala prioritas.
Pembangunan jalan di Papua ialah hal yang luar biasa karena belum pernah ada Presiden Indonesia yang berani melakukannya.
Konektivitas menjadi hal yang paling krusial dalam pembangunan ekonomi di sana. Begitu pula pembangunan waduk besar-besaran merupakan hal yang akan bermuara pada swasembada beras. Ini terobosan hebat dari Presiden Joko Widodo.
Namun, kereta cepat Jakarta-Bandung, sekalipun operatornya bukan pemerintah alias 'swasta' (tepatnya BUMN), belum tentu merupakan kebutuhan yang mendesak dengan prioritas tertinggi pada saat ini.
Pada titik inilah diperlukan kecermatan yang tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Pameran bertajuk "China High Speed Railway on Fast Track Exhibition" yang diselenggarakan di Jakarta, Agustus 2015. (foto: AFP/Bay Ismoyo) ()