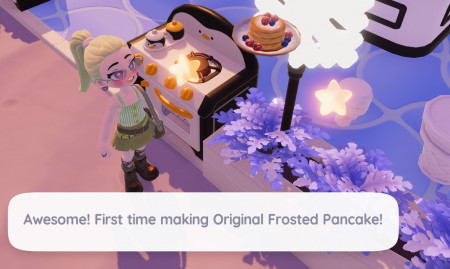Boleh dikata tak ada kampus yang tak ambil bagian dalam mengukir sejarah menumbangkan rezim Orde Baru. Tuntutannya sama, mereka mendesak Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI, hapus Dwifungsi ABRI, berantas KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).
Seiring dengan ingar bingar demonstrasi mahasiswa, kalangan jurnalis pun sibuk meliputi aksi gerakan rerformasi itu. Pewarta foto selalu terdepan mengambil momen demontrasi tersebut. Saya menjadi bagian dari jurnalis yang meliput aksi mahasiswa turun ke jalan saat itu, di antara depan Gedung MPR/DPR, jalan Thamrin dan Sudirman, tertarik mencermati seorang fotografer yang melakukan pemotretan.
Penampilannya cukup meyakinkan ala jurnalis foto. Kemeja kotak-kotak, bercelana jins, rambut gondrong, membawa rangsel dan kamera berstandar foto jurnalistik. Selain itu, yang bersangkutan juga menggunakan ID card jurnalis. Yang membedakan dia dengan jurnalis foto lainnya ialah sudut pengambilan foto (angle) dari berbagai sudut. Bahkan, sekumpulan koordinator lapangan aksi yang berada di belakang barisan demonstrasi pun difotonya. Begitu pula mahasiswa yang melempar aparat pengendalian massa Brimob dan Penanggulangan Huru-hara (PHH) TNI-AD dari bagian belakang selalu difotonya.
Sementara itu, jurnalis foto yang asli hanya mengabadikan momen-momen tertentu, seperti orasi pengunjuk rasa, aksi bersitegang atau dorong-dorongan, dan bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat.
Karena penasaran dengan fotografer yang diduga 'jadi-jadian' itu, saya penasaran mencari informasi ke aparat dan rekan-rekan fotografer. Ternyata fotografer berambut gondrong itu ialah personel dari kesatuan elite TNI-AD.
Hasilnya, seperti diduga, yang bersangkutan sedang menyamar untuk memotret kegiatan unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung hampir setiap hari ketika itu. Pada saat yang bersamaan, kesatuan intelijen TNI juga 'memelihara' sejumlah aktivis di berbagai kampus untuk mencari informasi akurat tentang gerakan mahasiswa saat itu.
Kisah aparat yang menyamar menjadi jurnalis mencuat kembali ketika Inspektur Satu (Iptu) Umbaran Wibowo masuk jajaran pejabat utama dan kapolsek yang melakukan serah terima jabatan di Polres Blora, Senin (12/12). Umbaran yang berpangkat inspektur satu dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggantikan AK Lilik Eko Sukaryono. Sebelumnya, Umbaran menjabat Wakapolsek Kradenan.
Banyak pihak yang kaget dengan pelantikan Umbaran Wibowo sebagai kapolsek. Pasalnya, selama ini Umbaran dikenal sebagai kontributor TVRI di Blora. Masa kerja Umbaran sebagai jurnalis pelat merah cukup lama, 14 tahun.
Publik merasa aneh dengan penyamaran Umbaran sebagai jurnalis.
Pasalnya, profesi jurnalis yang menjunjung tinggi independensi ternyata ditunggangi untuk aktivitas yang tak berhubungan dengan jurnalistik.
Baca juga:Respons Mabes Polri Soal Intel Menyamar Jadi Wartawan |
Karena merasa gerah, Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberhentikan Iptu Umbaran Wibowo dari status keanggotaan PWI, Kamis (15/12). Keputusan Dewan Kehormatan didasarkan pada temuan pelanggaran yang dilakukan Iptu Umbaran, yakni kode etik jurnalistik, Peraturan Dasar PWI, dan Kode Perilaku Wartawan.
Jika merujuk Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1990, Pasal 7 ayat 2 menegaskan wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers pada kode etik nomor 1 dituliskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
Dari sini jelas bahwa jurnalis atau wartawan tidak boleh kerja rangkap dengan agenda yang tak ada urusannya dengan kerja jurnalistik. Kerja intelijen ialah pengintaian, pengamatan, dan penggalian informasi untuk kepentingan di kesatuannya.
Padahal, jurnalis memiliki kewajiban melindungi narasumber sesuai dengan kode etik nomor 7 bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
Tugas segenap lembaga pers yang berbadan hukum menjaga muruah jurnalisme. Jangan mau diboncengi intelijen untuk kepentingan-kepentingan di luar jurnalistik.
Jurnalistik tidak sekadar mencari berita, tetapi menjaga dan merawat demokrasi. Makanya tak mengherankan jika pers disebut sebagai kekuatan keempat demokrasi (fourth estate). Sebutan pilar keempat demokrasi pertama kali diluncurkan Edmund Burke dari Inggris pada akhir abad ke-18.
Istilah tersebut merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki pers setara dengan ketiga pilar lainnya dalam kehidupan di Inggris: Tuhan, Gereja, dan Majelis Rendah. Dalam konteks trias politika di Indonesia, pers sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Mark Twain, hanya dua hal yang mampu menerangi dunia. Matahari di langit dan pers di bumi. Tabik!



.jpg?w=660)