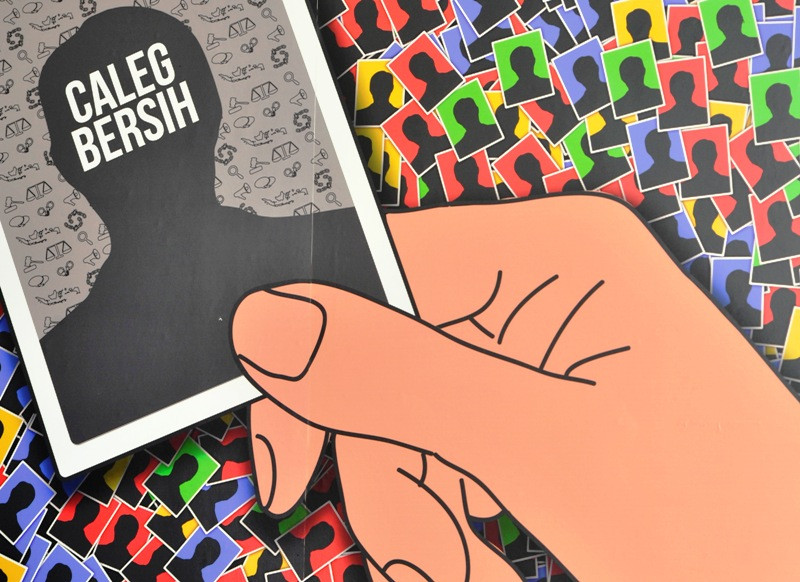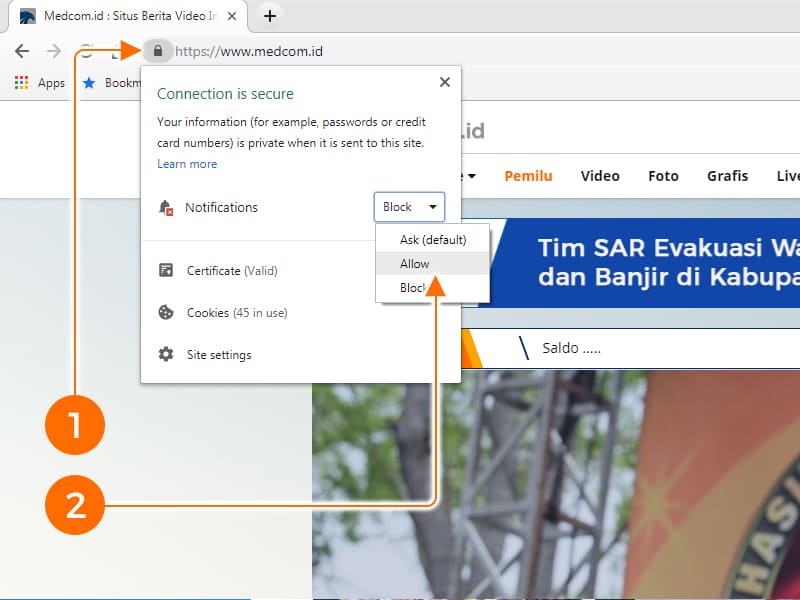Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun berbeda pandangan. Polarisasi kedua lembaga ini sebenarnya berkiblat kepada dua mazhab hukum, yakni Realisme dan Positivisme.
Dua Peraturan KPU yang melarang terpidana kasus tertentu maju sebagai calon legislatif dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah dibatalkan MA. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20/2018 melarang mantan terpidana tertentu maju sebagai wakil rakyat. Pun demikian halnya dengan pasal 60 huruf J PKPU Nomor 26/2018 yang melarang Pencalonan Anggota DPD dari bekas terpidana tiga kasus tersebut.
Dalam hal ini, KPU menganut mazhab realisme hukum atau legal realism. Mazhab ini memaknai hukum sebagai kontrol sosial. Hukum (aturan) harus didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya (real) di masyarakat.
Realisme hukum “mengurangi” makna aturan tertulis dan memposisikan hukum tidak tertulis sebagai nilai yang perlu diperjuangkan termasuk nilai keadilan. Nilai keadilan yang dibutuhkan masyarakat direspons KPU melalui PKPU 20/2018 dan PKPU 26/2018.
Dalam logika yang sangat sedehana tiga jenis kejahatan tersebut tidak dapat diterima di masyarakat. Kejahatan tersebut sangat menyakitkan meskipun pelakunya sudah dipenjara. Maka sewajarnya KPU menempatkan aturan larangan calon legislatif bagi mantan terpidana agar memenuhi rasa keadilan karena sudah menyakiti masyarakat. Artinya, KPU tidak perlu melihat apakah PKPU bertentangan dengan aturan di atasnya, yang lebih penting adalah sebuah pembaharuan aturan yang dibutuhkan masyarakat.
Negara penganut realisme hukum adalah Amerika Serikat. Dalam sistem hukum Anglo-saxon di Amerika Serikat, hakim bisa memvonis seorang penjahat hingga ratusan tahun tanpa melihat batasan normal usia manusia.
Kasus Jerry Active misalnya. Dilansir Mirror, pada 22 Agustus 2015 hakim pengadilan Alaska memvonis 359 tahun penjara kepada Jerry Active, pemuda berusia 26 tahun. Ia dianggap bersalah karena memerkosa bayi dua tahun dan membunuh kakek-neneknya. Hakim tidak peduli dengan aturan hukum tertulis yang sudah mengatur hukuman penjara maksimal. Hakim juga tidak peduli apakah putusannya berbenturan dengan aturan diatasnya.
Hakim hanya menilai kejahatan berat harus dihukum setimpal demi keadilan yang dituntut masyarakat atau keluarga korban.
Dalam konteks pemilihan umum, KPU adalah penyelenggara sekaligus hakim yang bisa meloloskan warga negara menjadi calon legislatif dan ditetapkan sebagai anggota parlemen. Maka sesungguhnya dua PKPU tersebut adalah wujud nyata kewenangan KPU membawa keadilan masyarakat dalam kontestasi politik.
KPU tidak melihat apakah pelaku sudah dihukum/rehabilitasi, mereka adalah pelaku yang sudah mengkhianati masyarakat sehingga tidak bisa diloloskan sebagai wakil masyarakat/rakyat. Tokoh realisme hukum di Indonesia Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif berpendapat “hukum untuk manusia, bukan untuk hukum itu sendiri.”
Realisme Hukum yang digunakan KPU juga menggunakan pendekatan teori kedaulatan rakyat. Adagium latin “vox populi vox dei” atau suara rakyat adalah suara Tuhan makin menguatkan KPU agar tidak main-main dengan rakyat yang kedudukannya nyaris sejajar dengan Tuhan. Sangat masuk akal jika KPU tidak meloloskan calon yang cacat, karena jika ya, KPU sama saja mencederai suara Tuhan.
Lalu, bagaimana dengan Bawaslu? Bawaslu merasa dua PKPU tersebut sudah rusak sejak lahir karena melanggar aturan yang di atasnya. Setidaknya, melanggar pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal ini membolehkan mantan terpidana maju dalam kontestasi politik setelah menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih serta mengumumkan kejahatannya kepada publik. Pijakan mazhab yang digunakan Bawaslu mengacu pada hukum positif atau legal positivism.
Aliran positivisme mewajibkan semua aturan harus tertulis dan tidak boleh kontradiksi dengan hierarki perundang-undangan di atasnya. Perbedaannya dengan mazhab realisme hukum-yang digunakan Bawaslu bukan soal keadilan, melainkan kepastian hukum.
Tanpa kepastian hukum, penyelenggaraan negara bisa kacau. Akan terjadi banyak tabrakan hukum karena masing-masing lembaga mengeluarkan peraturan dengan segala alasan pembenar.
Dalam positivisme, kepastian hukum adalah napas sebuah aturan. Mazhab ini dianut mayoritas negara Eropa kecuali Inggris, dan termasuk Indonesia. Mazhab positivisme lahir dari semangat revolusi Prancis yang melawan absolutisme penguasa karena melegalkan konvensi atau kebiasaan yang mengikat dan semena-mena. Belanda datang ke Indonesia membawa pengaruh positivisme hukum.
Bawaslu sebagai pengawas pemilu menilai KPU abai terhadap Undang-Undang di atasnya yang sudah jelas memberi hak politik kepada bekas terpidana. Dua PKPU tahun 2018 sudah kehilangan kekuatan mengikat, karenanya siapapun calon legislatif dari mantan terpidana yang mengadu ke Bawaslu akan diloloskan. Bawaslu tetap teguh menolak PKPU karena jika dibiarkan akan menjadi yurisprudensi yang melahirkan peraturan kontradiktif.
Asas kemanfaatan
Terlepas dari putusan MA, KPU maupun Bawaslu memiliki alasan pembenar. Mazhab positivisme yang dipakai Bawaslu dengan mudah mengalahkan mazhab realisme, meskipun realisme hukum seringkali dipakai Mahkamah Konstitusi melalui putusannya seperti No.102/PUU-VII/2009 yang mengizinkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) serta paspor untuk pemilih yang tak terdaftar pada Pemilu 2009.
Contoh lain putusan bermazhab positivisme hukum adalah penghapusan ribuan Peraturan Daerah yang bermasalah/bertentangan dengan hierarki di atasnya. Ada 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi dan dipublikasikan oleh situs resmi Kemendagri www.kemendagri.go.id pada 21 Juni 2016.
Dilhat dari sudut pandang mazhab hukum, sesungguhnya niat KPU dan Bawaslu sama-sama baik. Namun perlu dilihat lagi bahwa sebenarnya asas yang bisa masuk ke dalam mazhab realisme hukum dan positivisme adalah asas kemanfaatan. Asas ini merupakan pelengkap dari tiga asas hukum yakni keadilan dan kepastian hukum.
KPU mempertimbangkan asas kemanfaatan demi output anggota legislatif yang lebih baik. Bawaslu pun juga melihat asas kemanfaatan agar output pemilu sah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Namun MA memutuskan asas kemanfaatan yang lebih bermanfaat adalah mazhab positivisme. Legalitas pemilu tahun depan harus aman dari benturan hukum.
Ke depan perlu ada sebuah harmonisasi antarlembaga agar mazhab realisme dan positivisme bersatu. Penyatuan dua mazhab ini juga bisa menyatukan tiga asas hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Pekerjaan itulah yang menjadi tanggung jawab penguasa dan parlemen sebagai pembuat undang-undang. Bukan tidak mungkin jika penyatuan mazhab dan komitmen legislasi pemerintah bisa menghasilkan reformasi besar bidang perundang-undangan, termasuk juga larangan mantan terpidana menjadi wakil rakyat.[]
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id