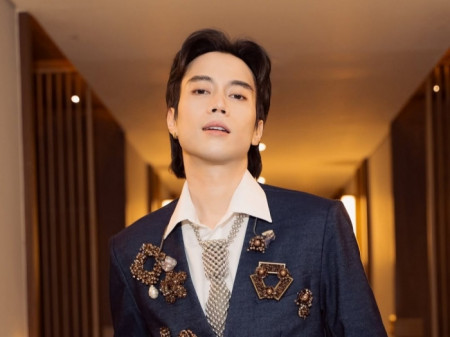Oleh: Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Anggota DPR RI
Artikel ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Kamis (2/10/2014)
RAPAT Paripurna DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat secara one man one vote hasil reformasi ke proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kisah politik konyol, tragis, dan dramatis.
Mungkin inilah politik pengkhianatan kaum demokrat di negeri ini.
Drama politik konyol dan tragis karena para anggota dewan yang terhormat terlihat sangat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan politik yang sejatinya sangatlah penting dalam proses politik dan demokrasi yang telah dengan susah payah kita perjuangkan bertahun-tahun di era reformasi ini. Lebih dari itu, mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ke proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelemahan argumentasi.
Argumentasi yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memakan biaya tinggi, menimbulkan sejumlah kekacauan sosial, hanya melahirkan pemimpin korup, dan seterusnya, tidak memiliki landasan teoretis dalam kerangka pemikiran bersifat akademis.
Kita ingat betul pertama kali pemilihan kepala daerah secara langsung digelar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan ternyata berjalan secara damai tanpa gejolak sosial yang berarti. Itu fakta sosial. Artinya, fenomena kekacauan sosial (terjadinya kerusuhan) yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai implikasi politik dari pesta demokrasi pemilihan kepala daerah layak dipertanyakan.
Tegasnya, bukan pemilihan kepala daerah secara langsung itu sebagai premis mayor yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekacauan, melainkan banyak faktor lain yang menjadi sebab terjadinya kekacauan itu. Di antaranya yang sangat fundamental ialah banyaknya elite politik yang enggan menerima kekalahan dalam proses pemilihan kepala daerah itu. Dari sinilah hasutan politik lahir. Tujuannya tidak lain agar terjadi kekacauan di masyarakat. Padahal, masyarakat Indonesia selama ini sejatinya sudah terbiasa dengan proses pemilihan pemimpin secara langsung seperti dalam pemilihan kepala desa, dan faktanya belum pernah ada kerusuhan dalam proses itu.
Secara sosiologis--antropologis, sejarah mengajarkan bahwa konflik sosial itu terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu dipicu oleh kuatnya tarikan kepentingan para elite terkait dengan keinginan kuat untuk merebut dan atau mempertahankan pengaruh dan kekuasaan.
Dalam konteks keputusan politik DPR yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ke sistem pemilihan tidak langsung (oleh DPRD), penulis melihat ini sebuah pengkhianatan kaum demokrat di pentas politik kekuasaan. Sangatlah disayangkan ini justru terjadi di tengah bangsa Indonesia sedang memperjuangkan hak-hak politik masyarakat yang selama ini tersandera oleh kepentingan pragmatis sekelompok elite di sentra kekuasaan. Padahal, dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran dalam berpolitik, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama secara politik dan berpartisipasi dalam proses politik berarti telah menggunakan hak politik untuk menentukan masa depan kehidupan mereka yang lebih baik.
Sayangnya, setelah hak-hak politik mereka itu berhasil kita perjuangkan selama era reformasi, ternyata hak-hak politik itu kini dirampas kembali oleh para elite politik yang pongah akan kekuasaan melalui Rapat Paripurna DPR di Senayan.
Pengkhianatan
Saya menyebutnya ini sebuah pengkhianatan kaum demokrat. Mengapa pengkhianatan? Kalau mau jujur, sebenarnya para elite politik, baik mereka yang ada di sentra kekuasaan ekskutif maupun mereka yang berada di legislatif (DPR), sejatinya mengetahui dan menyadari arti pentingnya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung itu bagi proses masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di negeri ini. Faktanya, proses pengambilan keputusan itu berjalan sangat dramatis.
Para tokoh dari sejumlah partai politik sebenarnya banyak yang tidak setuju manakala sistem pemilihan kepala daerah itu dikembalikan dari sistem pemilihan secara langsung ke sistem pemilihan tidak langsung. Hal itu dapat kita baca dari pernyataan mereka yang tersebar luas di berbagai media masa.
Yang paling ironis ialah sikap politik ambigu yang ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik dalam kapasitasnya sebagai presiden maupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Maka pantas kalau masyarakat luas kini marah dan kecewa terhadap Presiden SBY dan Partai Demokrat karena sikap politik Presiden SBY sangatlah tidak etis secara moral.
Bagaimana tidak, Presiden SBY kini sering mengeluh kecewa atas keputusan politik DPR yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ke sistem pemilihan tidak langsung. Akan tetapi, keluh kesah Presiden SBY ditanggapi masyarakat luas sebagai kamuflase dan pengkhianatan politik yang amat menyakitkan.
Bagaimana mungkin Presiden SBY tidak mengetahui skenario terburuk dari proses politik yang mencederai kedaulatan rakyat ini, sedangkan draf RUU yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem tidak langsung itu diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan representasi dari lembaga kepresidenan.
Parahnya lagi, Presiden SBY seolah tidak mengetahui agenda politik di balik walk out sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat saat rapat paripurna yang kemudian memuluskan kemenangan bagi koalisi Merah Putih dengan opsi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, sementara Presiden SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat.
Yang jelas, ini adalah trah politik kotor yang mencederai amanat reformasi dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika ini disebut sebagai pengkhianatan kaum demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Ferry Mursyidan Baldan. ANTARA (Ferry Mursyidan Baldan)