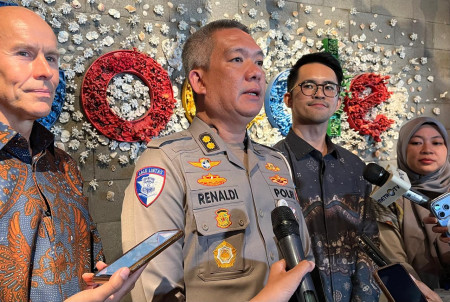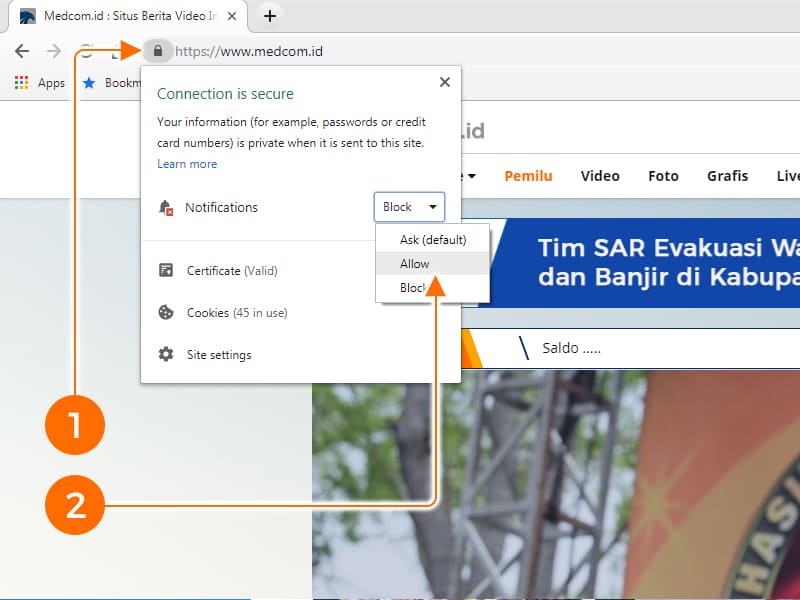Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI
PEMBAHASAN perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang lebih kuat dan efektif selalu menjadi tema hangat di tengah praktik ketatanegaraan yang sementara ini dinilai belum ideal. Salah satu fokus bahasan yang sering mengemuka ilah penataan sistem parlemen (perwakilan) yang lebih representatif bagi Indonesia. Di sinilah, antara lain kita meletakkan diskursus apakah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang perlu dipertahankan keberadaannya ataukah sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang ini yang perlu dipertanyakan efektivitasnya. Secara teoritis terdapat tiga komponen pembentukan negara yakni, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat yang berkehendak mendirikan negara pasti menempati wilayah tertentu sebagai basis pendirian negara. Contohnya, rakyat Palestina saat ini sedang memperjuangkan negara merdeka di wilayah yang saat ini mereka tempati, termasuk di sebagian wilayah yang dikuasai Israel.
Cikal bakal Indonesia merdeka juga tak lepas dari keinginan bersatu dari berbagai wilayah. Pada 1928 ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan, para pemuda mewakili identitas wilayah masing-masing; Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen, dan lain sebagainya. Ketika Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa dari berbagai wilayah bersatu tanpa mempersoalkan sedikit atau banyak jumlah penduduk di tiap-tiap wilayah. Namun, dalam perjalanan sejarah ternyata upaya mewujudkan keseimbangan dan keadilan antarwilayah itu tak berjalan sebagaimana harapan. Baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, meski terdapat representasi utusan daerah dalam MPR, tapi perannya hampir tidak ada atau terbatas karena dominasi eksekutif (Presiden). Sementara, legislatif hanya diwakili partai-partai politik atas nama rakyat yang terlalu besar. Dus, akibatnya terjadi disparitas pembangunan antardaerah yang penduduk lebih padat dengan daerah berpenduduk lebih kecil walaupun menyumbangkan wilayah yang relatif lebih luas, termasuk sumber daya alamnya.
Mengatur ulang
Dari pengalaman dua era itu, kita mendapati kenyataan bahwa praktik sistem ketatanegaraan sangat rentan diterjemahkan sebagai 'apa maunya penguasa'. Ketika memasuki era Reformasi, kita menyadari sumber masalahnya berasal dari 'struktur' dan sistem keterwakilan yang tidak mencerminkan representasi yang berimbang atas keberadaan rakyat dan wilayah. Hal itu perlu desain ulang lembaga perwakilan yang 'mewakili langsung rakyat' dan 'mewakili langsung wilayah' agar terjadi keseimbangan dan keadilan antarwilayah.
Gagasan tersebut dihasilkan oleh para pakar yang tergabung dalam Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani-yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 198/1998 untuk memberi masukan substantif kebijakan reformasi, termasuk dalam rangka amendemen UUD. Dalam rekomendasinya, antara lain tim memberikan pandangan terhadap eksistensi 'utusan golongan' dan 'utusan daerah' pada keanggotaan MPR, serta merekomendasikan 'utusan golongan' dimasukkan sebagai perwakilan partai politik untuk mengisi lembaga DPR. 'Utusan daerah' dimaknai sebagai perwakilan daerah yang menjadi cikal bakal lembaga DPD sehingga format lembaga perwakilan Indonesia menganut bikameralisme, yakni DPR merupakan wakil rakyat dan DPD merupakan wakil daerah.
Sistem bikameral ini berlaku di banyak negara baik federal maupun nonfederal. Negara-negara besar walaupun bukan negara federal memberlakukan sistem ini karena memberikan keuntungan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan antarwilayah di dalam negara. Terlebih bagi negara dengan luas wilayah yang besar dan heterogen seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, India, dan negara-negara kepulauan seperti Jepang dan Filipina, sistem bikameral terbukti merupakan konsep yang representatif untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan antarwilayah.
Sayangnya, pikiran para pakar yang jernih di atas tereduksi oleh pikiran para politikus Senayan saat penerjemahannya di dalam pasal-pasal perubahan UUD 1945. Wujud sistem bikameral Indonesia menjadi 'banci' seperti saat ini, yakni keberadaan DPD hanya struktur tapi fungsi dan kewenangannya terbatas (dibatasi). Bahkan, kedudukan DPD kembali mengalami reduksi dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)--yang mendorong DPD melakukan dua kali judicial review ke Mahkamah Konstitusi (hasilnya MK menguatkan kewenangan DPD). Padahal, DPD sebagai perwakilan wilayah seharusnya dapat memainkan peran kamar kedua parlemen yang menjamin checks and balances terhadap DPR sebagai perwakilan rakyat.
Saat ini yang terjadi adalah sistem perwakilan lebih terkonsentrasi pada daerah padat penduduk (kecuali melalui program Otsus) karena aspirasinya terwakili oleh pembuat kebijakan yang lebih banyak (baca: DPR), apalagi terdapat nomenklatur khusus semacam 'dana/program aspirasi' bagi wakil rakyat di DPR. Hal ini semakin memarginalkan daerah luas dengan jumlah rakyat sedikit seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Bengkulu, Sulawesi, dan lain-lain.
Quo vadis
Harus diakui, tidak sedikit ragu dan tanya seputar peran DPD selama ini. Dengan menyandang status sebagai lembaga perwakilan, kenyataannya masyarakat lebih mengenal DPR daripada DPD. Ingar-bingar pemberitaan media atas DPD juga tidak semasif pemberitaan atas DPR.
Di sisi lain mengatakan DPD tidak punya peran dan kontribusi sama sekali tentu salah 100%. Dari sisi legislasi, sejak 2004 sampai sekarang, DPD telah menghasilkan 543 keputusan yang terdiri dari 6 Prolegnas, 59 RUU usul inisiatif, 253 pandangan, pendapat, dan pertimbangan, 158 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU, dan 62 pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran dan 5 rekomendasi DPD.
DPD nyatanya menjadi penyeimbang kebijakan negara yang lebih berkeadilan bagi daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan Indonesia Timur yang mungkin tidak terepresentasikan oleh keterwakilan politik (DPR) yang berbasis jumlah penduduk. DPD praktis menjadi satu-satunya corong bagi daerah untuk terus mengupayakan peningkatan dana transfer ke daerah dalam APBN. Anggota DPD juga aktif menyampaikan hak bertanya kepada Presiden, antara lain terkait dengan kebijakan kereta api cepat dan program mobil LCGC. Pun, beberapa inisiatif undang-undang, seperti UU Desa, UU Pemda, UU Kelautan, RUU Kepulauan, dan RUU Wawasan Nusantara menjadi saksi bisu keberpihakan nyata DPD terhadap percepatan pembangunan daerah.
Dengan seluruh penjelasan tersebut, gagasan pembubaran DPD menjadi tidak tepat dan tidak sejalan dengan sejarah dan kondisi negara kita. Gagasan ini terkesan mengkhianati para pendiri bangsa yang berjuang untuk wilayahnya lalu bersatu dalam NKRI. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebagai berikut, yakni pertama, hadirnya lembaga perwakilan daerah penting untuk menengahi/mengimbangi kebijakan anggaran dan pembangunan yang memihak pada daerah-daerah padat penduduk karena lebih banyak diwakili anggota DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan penentu anggaran. Kedua, ukuran kinerja dan prestasi lembaga perwakilan daerah tidak bisa dilihat (hanya) dari pemberitaan media, tapi pada peran dan kiprahnya dalam menjaga keseimbangan antarwilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan.
Ketiga, penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima UUD 1945 adalah keniscayaan agar lembaga perwakilan daerah memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kuat. Terlebih lagi, terdapat Keputusan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 yang merekomendasikan, antara lain penguatan MPR termasuk DPD. Nah, sekarang akan diuji apakah partai politik yang wakil-wakilnya di MPR telah menyetujui rekomendasi itu akan mengkhianati keputusan tersebut, atau secara gentleman tetap mendukung penguatan DPD. Kita tunggu apa kata mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di ![Suasana Sidang Paripurna di DPR RI, Jakarta [ilustrasi]. Foto: MI/Mohamad Irfan.](https://cdn.medcom.id/dynamic/content/2016/03/02/492670/jAOX7gd3J2.jpg?w=1024)
Suasana Sidang Paripurna di DPR RI, Jakarta [ilustrasi]. Foto: MI/Mohamad Irfan. ()
TERKAIT