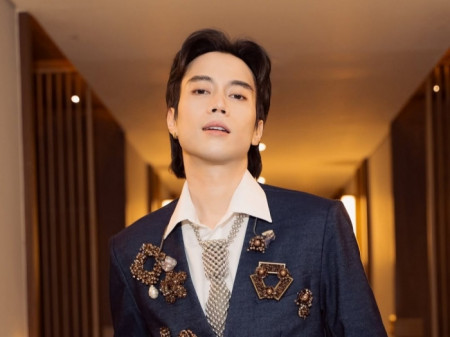Oleh Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta.
Artikel ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Senin (29/9/2014)
DINAMIKA politik di DPR telah menghantarkan demokrasi ke titik nadir! Kuasa rakyat kembali diambilalih para elite parpol dalam menentukan kepala daerah melalui DPRD. Drama Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari, menjadi elegi kekuasaan. Rakyat tunakuasa dalam menentukan para pemimpin daerah yang mereka kehendaki di kemudian hari.
Ironisnya, sidang paripurna tersebut menjadi panggung opera sabun SBY dan Demokrat dalam rangkaian cerita melodramatis yang dipertontonkan sebelum ataupun sesudah Sidang Paripurna DPR. Sangat penting menelaah potongan drama politik SBY dan Demokrat serta mengkritisi posisi mereka dalam konstelasi politik saat RUU Pilkada diputuskan.
Ada beberapa rangkaian cerita yang jika dianalisis menunjukkan plot drama SBY dan Partai Demokrat. Sepanjang Mei hingga September, Demokrat tiga kali hadir di rapat panja RUU Pilkada. Pada Mei 2014, Demokrat bersikap pemilihan gubernur secara langsung dan pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD. Pada 3-9 September Demokrat menghendaki pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota melalui DPRD. Drama simulasi realitas kian terasa saat SBY mengunggah pernyataannya melalui Youtube. Lewat pesan Youtube inilah SBY memberi harapan sekaligus menjadikan pidatonya sebagai panggung depan (front stage) pencitraan politik.
Skenario berjalan mulus dengan hadirnya peran Edhie Baskoro Yudhoyono pada 17 September yang mendukung pernyataan SBY bahwa partainya mendukung pilkada langsung.
Pernyataan mengambang dan normatif SBY serta Ibas soal dukungan Demokrat terhadap pilkada langsung dioperasionalisasikan lebih teknis oleh Syarief Hasan pada jumpa pers 18 September. Ini merupakan gimik politik Demokrat dengan mengulang janji dukungan terhadap pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan diakomodasi di RUU Pilkada. Drama pun bergulir di panggung Sidang Paripurna DPR, sikap seolah-olah mendukung pilkada langsung diperankan para `aktor pemeran pembantu' dari Fraksi Demokrat saat perdebatanperdebatan di awal sidang.
Drama berakhir antiklimaks! Demokrat meninggalkan gelanggang alias walk out dengan argumen yang terkesan dipaksakan, yakni 10 koreksi tak diakomodasi. Benarkah?
Tentu yang tahu konstelasi proses lobi di panggung belakang (back stage) saat sidang paripurna politisi, ya, mereka sendiri. Pengakuan dari beberapa elite Koalisi Indonesia Hebat yang saat pilpres mendukung Jokowi-JK ialah di injury time 10 syarat yang dikehendaki Demokrat sebenarnya disetujui PDIP, PKB, dan Hanura. Hanya, muncul syarat lanjutan, 10 koreksi Demokrat tersebut harus diakomodasi dan disepakati secara musyawarah dan mufakat, suatu hal yang teramat sulit direalisasikan saat itu.
Terlepas dari realitas di panggung belakang yang memang kerap tak terakses oleh publik, faktanya 124 anggota DPR dari Demokrat walk out meskipun masih ada 6 orang yang tetap di dalam ruang sidang. Artinya, ketidakhadiran Demokrat dengan sendirinya memuluskan Koalisi Merah Putih (KMP) memenangi pertarungan. Sudah bisa ditebak, yang setuju pilkada langsung hanya 135 orang terdiri dari PDIP (88), PKB (20), Hanura (10) dan pembelot dari Golkar (11) serta Demokrat (6).
Sementara itu, yang mendukung pilkada lewat DPRD berjumlah 226 orang terdiri dari Golkar (73), PKS (55), PAN (44), PPP (32), dan Gerindra (22). Skenario drama itu sukses memuluskan langkah mundur demokrasi Indonesia ke era Orde Baru, saat korporatisme politik elite parpol begitu dominan dalam menentukan kepala daerah. Drama pun belum usai, seolah-olah kaget dan tak tahu apa-apa SBY menyatakan kecewa dengan hasil voting RUU Pilkada. Sebuah ekspresi miskin impresi karena gelombang kecaman sudah mengalir deras tertuju pada SBY.
Rangkaian proses sikap SBY dan Demokrat tersebut mirip opera sabun. Kecenderungan drama bersambung yang mengarah kepada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam tulisannya, The Precession of Simulacra, sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya simulasi realitas itu merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi palsu atau seolah-olah mewakili kenyataan. Wajar jika politik pencitraan ala Demokrat dan SBY pun dipandang banyak kalangan sebagai wujud hiperealitas. Dalam pandangan Baudrillard, hiperealitas dimaknai sebagai simulasi suatu hal yang sesungguhnya tidak pernah nyata adanya. Sementara itu, Umberto Eco menyebutnya sebagai the authentic fake atau kepalsuan autentik.
Wajar jika reaksi publik sangat keras mengkritik SBY dan Demokrat baik melalui media mainstream maupun media sosial. Di Twitter, misalnya, hashtag #ShameOnYouSBY (malu pada diri Anda, SBY) heboh dan menjadi trending topic dunia. Di media massa baik dalam maupun luar negeri secara umum menurunkan kritik tajam atas ke putusan DPR meloloskan UU yang mengembalikan pilkada ke DPRD.
The New York Times, The Guardian, Time Magazine, The Sydney Morning Herald, dan sejumlah media asing lainnya memberi ruang pemberitaan cukup besar dan rata-rata menyebut pengesahan UU Pilkada itu sebagai kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.
Sebelum Sidang Paripurna DPR, SBY dan Demokrat menyuguhkan skenario reality by proxy. Skenario itu biasanya digunakan untuk mengaburkan antara realitas dan fantasi. Banyak mimpi indah dibangun dan membentuk kesan di masyarakat seolah-olah Demokrat propilkada langsung tapi dalam praktiknya mereka membiarkan kelompok yang pro-pilkada DPRD leluasa memenangi pertarungan.
Stok cerita Demokrat sepertinya belum usai. Kini seolah-olah antarelite Demokrat saling curiga, siapa dalang di balik skenario walk out?
Mungkinkah SBY tidak tahu apa yang hendak dilakukan para anggota DPR di sidang paripurna? Jika melihat rekam jejak Demokrat dan SBY, rasanya sulit dipercaya jika SBY tidak tahu dan tidak memberi lampu hijau untuk langkah walk out. Benar, SBY memang sedang di luar negeri. Namun, teknologi komunikasi memfasilitasi keterhubungan SBY dengan para anggota DPR dari Demokrat, terlebih ini menyangkut agenda strategis. Mayoritas anggota DPR dari Demokrat keluar ruangan dan hanya menyisakan enam orang saja di sidang paripurna. Artinya, secara mayoritas anggota DPR dari Demokrat melakukan manuver politik yang memiliki konsekuensi pada lolosnya RUU Pilkada. SBY tentu saja berkepentingan memantau dari kejauhan apa dan bagaimana proses yang berlangsung di persidangan.
Harus dicatat, Demokrat hingga saat ini masih memiliki ketergantungan pada figur SBY. Dalam tradisi partai yang menyandarkan diri pada kekuatan figur sentral, dinamika politik yang terbangun biasanya bermuara pada gejala groupthink. Dalam buku Irving Janis, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982), salah satu ciri utama gejala groupthink ialah para kader organisasi akan menghindari pemikiran dan sikap berlawanan dengan elite utamanya. Genealogi Partai Demokrat memosisikan SBY sebagai figur utama sekaligus pusat pergerakan sistem organisasi. SBY bukan semata Ketua Umum Demokrat, melainkan juga roh dan penggerak partai itu sejak awal. Mungkinkah SBY tidak merestui keputusan yang diambil para anggota DPR dari Demokrat?
Beranikah para anggota DPR dari Demokrat itu walk out tanpa izin dari SBY?
Langkah SBY dan Demokrat ini tentu saja sangat berisiko. UU Pilkada yang disahkan menjadi warisan buruk rezim SBY di penghujung kekuasaan. Sebagaimana kita rasakan, arus utama opini publik sangat resisten dengan pengembalian pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Perlawanan simbolis dan prosedural kini dilakukan masyarakat. Secara simbolis, muncul teknik name calling atau pemberian label buruk pada SBY di banyak media sosial dan beragam alat peraga di ruang publik, misalnya beredar luas pelabelan SBY sebagai `Bapak Pilkada Tak Langsung'. Tentu saja itu merupakan satire yang ditunjukkan pada SBY dan sikap Demokrat yang secara tak langsung turut memuluskan pengesahan UU Pilkada. Secara prosedural, kelompok masyara kat kritis dan publik beperhatian (attentive public) akan mengajukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara substantif, memang terdapat sejumlah kerancuan argumentasi para pengusung usulan pilkada oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap terlalu berbiaya tinggi, tak hanya biaya finansial tetapi juga biaya sosial. Atmosfer pilkada berbiaya tinggi dianggap sebagai salah satu sebab demokrasi di berbagai daerah berlangsung tak sehat. Selain itu, pilkada dituduh menjadi pangkal keruwetan masalah-masalah sosial seperti tawuran, demonstrasi, dan kekerasan.
Benarkah mengembalikan pilkada ke DPRD akan menekan biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat dan penyelenggara? Bisa jadi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD justru akan memapankan ulang tradisi upeti ke parpol atau gabungan parpol. Upeti yang menjadi akses pencalonan diri kandidat oleh partai-partai yang berkuasa di DPRD bisa jadi setara atau lebih besar daripada pengeluaran pilkada langsung seperti sekarang.
Satu hal lagi yang sangat krusial dan lebih mahal dari sekadar angka-angka ialah keleluasaan masyarakat sipil berdemokrasi. Pilkada merupakan koreksi terhadap praktik oligarki dan korporatisme politik di era Orde Baru. Salah satu buah hasil reformasi tentunya ialah kebebasan warga dalam memandatkan kekuasaan yang mereka miliki.
Pilkada oleh DPRD bisa menyuburkan kembali kartelisasi politik. Alokasi kekuasaan dilakukan segelintir elite, sehingga melahirkan monopoli untuk mengamankan agenda-agenda mereka. Menurut Dan Slater dalam tulisannya, Indonesia's Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power after Democratic Transition (2004), Indonesia kerap terjebak dalam politik kartel yang melahirkan demokrasi kolusif (collusive democracy).
Kekhawatiran juga muncul menyangkut motif pengesahan UU Pilkada tersebut. Benarkah UU tersebut disahkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, atau semata-mata manuver elite pascapilpres?
Bagi Koalisi Merah Putih, momentum ini sangat mungkin dijadikan pintu masuk menciptakan agenda bersama jangka panjang terutama prospek power sharing di daerah-daerah, sehingga diharapkan menjadi insentif bagi para mitra koalisi KMP sekaligus menjadi alat tekan untuk koalisi Jokowi-JK. Kondisi itu bisa saja melahirkan tendensi mayoritas (majoritarian tendency) tidak semata di legislatif, tetapi juga di eksekutif. Penyakit ini biasanya adalah winner takes all karena ada pemanfaatan suara dominan untuk memuluskan seluruh agenda mereka dan menutup segala akses kompetitor.
SBY tentu sangat memahami risiko-risiko lanjutan pengesahan pilkada oleh DPRD ini. Kita masih harus menunggu seperti apa sikap lanjutan SBY dan Demokrat pascapengesahan UU Pilkada. Akankah mereka tetap mengelola hiperealitas politik citra dengan memainkan opera sabun lanjutan? Inilah ujian sejarah yang harus dijawab sendiri oleh SBY di penghujung kekuasaannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Gun Gun Heryanto/ANT/Widodo S. Jusuf. ()