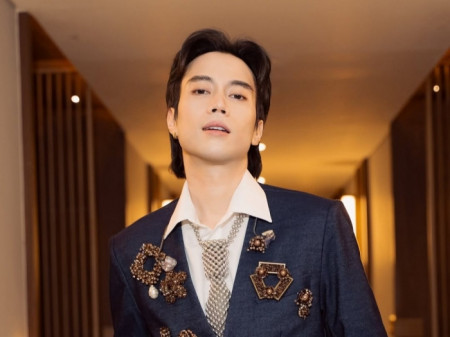Idealnya, sumber makanan yang menyediakan tiga komponen gizi utama itu didapat dari sumber beragam. Masalah datang ketika satu bahan pangan terlalu mendominasi hingga dampaknya meluas.
Persepsi bahwa nasi adalah makanan pokok, membuat Indonesia punya alasan untuk melakukan impor beras dan memperluas lahan sawah di daerah yang tidak cocok ditanami padi. Selain itu, peternakan skala luas juga memaksa lahan hutan dibuka demi memenuhi permintaan pasar—sebagaimana dilaporkan BBC dari Rondonia, hutan Amazon Brazil.
Jika sumber pangan tidak didiversifikasi dan perambahan ruang penyedia oksigen terus berlangsung, bencana lingkungan bisa terjadi lebih parah. Manusia perlu mencari sumber pangan lain. Dalam laporannya tentang antisipasi kondisi penyediaan pangan pada 2050, badan pangan dunia atau FAO merekomendasikan sejumlah kriteria. Bahan makanan kita di masa depan harus memenuhi tiga karakteristik: mengentaskan kelaparan, bergizi, dan bermanfaat secara sosial-ekonomi-lingkungan.
Sumber protein
Lantas di masa depan nanti, dari mana kita bisa penuhi kebutuhan protein? Yang jelas bukan dari peternakan. Karena gas metana yang dihasilkan dari metabolisme hewan bisa menghasilkan efek rumah kaca.Gas itu bisa membuat kita yang tinggal di planet bumi, seakan-akan berada di dalam rumah kaca. Cahaya matahari tertahan oleh kandungan gas polutan hingga berakibat pada pemanasan global.
Peternakan juga memakan lahan yang tidak sedikit. Seiring meningkatnya kebutuhan daging, meningkat pula jumlah daratan yang diperlukan buat mengandangkan sapi, ayam, atau babi.
Pengorbanan itu pun tidak sebanding dengan luaran protein yang akan dipanen. Persentase protein dalam satu ekor sapi jumlahnya 18 persen. Sementara ayam menghasilkan 12 persen. Lantas apa contoh hewan penghasil protein yang lebih sepadan dengan modal peternakannya? Ulat! Dalam satu ekor ulat tepung, persentase protein bisa mencapai 47 persen.
Ulat penghasil protein
Sebenarnya istilah yang tepat bukan ulat. Hewan yang saya maksud adalah larva Tenebrio molitor. Serupa, tapi tak sama.Ulat yang biasa kita kenal akan bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Sementara, larva yang terkenal dengan nama ulat hongkong, atau ulat tepung, atau meal worm ini, bisa tumbuh menjadi kumbang. Dan sebelum calon kumbang itu berkembang, kita bisa memanen mereka sebagai pangan sumber protein.
Dalam satu meter persegi medium biakan, ulat yang terkumpul bisa mencapai 60 kilogram. Dengan luasan yang sama, kita hanya bisa menampung sekitar empat kilogram ayam. Sapi, jelas tidak cukup terwadahi dalam satu meter persegi tadi. Maka, dalam hal efisiensi luas lahan, ulat tepung unggul. Dilihat dari sisi bisnis, peternakan ulat tepung pun cukup menjanjikan.
Demi ulat
Koes Hendra berusia 20 tahun saat merintis bisnis budidaya ulat tepung. Ia terdorong oleh semangat almarhum Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor periode 2015-2020, Mohamad Yamin. Yamin menargetkan agar 10 persen mahasiswa dari fakultasnya berwirausaha. Dan Hendra ada di dalamnya.Ketika berkuliah di jurusan Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan ini, Hendra kemudian fokus meneliti ulat tepung untuk syarat meraih gelar sarjana. Modal ilmu dari hasil riset, lalu ia jadikan bekal berbisnis.
"Kita beli waktu itu Sembilan kilogram ulat. Kita pelajari harus bagaimana dan kita tidur di kandang.Sampai sekarang ada ruangan kita itu. Jadi bener-bener ruangan kecil, kita tinggal bertiga waktu itu. Jadi, kita hidup bersama ulat, ulatnya kita taruh di kamar kita, di kampus."
Motivasi: Dendam
Jumlah permintaan (demand) ulat tepung di daerah Jabodetabek mencapai 80 ton per bulan. Selain sadar akan tingginya potensi usaha itu, ada satu hal lagi yang mendorong Hendra gigih beternak ulat: dendam!Hendra pernah dimodali orang tuanya sebesar 10 juta rupiah dari alokasi dana pendidikannya hingga level sarjana. Sayang, mitra bisnis mereka kurang kooperatif.
"Ya, keterpurukan itu memang susah karena waktu itu kita makan saja bareng-bareng, yang penting ada nasilah ya. Sisanya ya di situ kan banyak tumbuh-tumbuhan kemudian ada kolam ikan, ada banyak. Jadi, kita merawat kandang itu juga. Nanam-nanam juga sembari kita belajar ulat ini. Kurang lebih waktu yang kita butuhkan satu tahun sampai kita bisa produksi massal.”
Pangan vs pakan
Tahun 2018, Hendra dan kawan-kawan punya lima unit cabang usaha. Ulat tepung yang mereka ternakkan diolah jadi MeFu atau Mealworm Furikake. Dalam khazanah kuliner nusantara, istilah berbahasa Jepang furikake bermakna ‘abon’.Dalam peliputan bersama tim program 15 Minutes Metro TV, saya dan tim mempraktikkan proses pengolahannya. Ternyata gampang. Ulat cukup dikeringkan pakai oven, lalu dilumat, dan sisanya tinggal dicampuri beragam bumbu.
Meski abon lebih kaya sensasi rasa, bagi saya ulat tepung kering terasa lebih nikmat. Rasanya serupa kacang. Jika Anda meminum sekaleng susu dengan rasa gandum, kurang lebih cita rasa semacam itulah yang tercecap di lidah ketika mencicipi ulat tepung kering.
Ulat tepung memang sejatinya hama gandum. Mereka biasa ditemui di karung-karung gandum yang mampir di Hong Kong tempo dulu. Nama kota perdagangan itu lalu melekat setelah Tenebrio molitor sampai di Nusantara sebagai pakan.
Di banyak tempat, ulat tepung belum populer sebagai pangan. Padahal, FAO mengingatkan bahwa ada 1.900 spesies serangga yang memang bisa dimakan manusia. Hasil riset Global Market Insights menyitir bahwa serangga pangan akan bernilai ekonomi sekitar 7,4 triliun rupiah pada 2023.
Di Swiss, ulat tepung dijual dalam kemasan dan bisa diolah menjadi burger. Orang-orang Eropa memang mulai terbiasa dengan serangga sebagai pangan. Dari kebiasaan makan itu, Hendra pun hampir kebagian cuan.
Tahun 2019, ia mengaku didatangi seorang pengusaha dari Norwegia. Mereka tertarik membeli ulat hasil ternakan Hendra. Sayangnya, kapasitas produksi tidak memenuhi permintaan minimum untuk dikirim ke Eropa. Hendra pun kini fokus memenuhi pasar di dalam negeri.
Ulat tepung kering bisa ia jual hingga seharga 390 ribu rupiah per kilogram. Dengan mitra bisnis yang ada saat itu, Hendra bisa memproduksi 7 ton ulat tepung kering per bulan. Maka, pendapatan kasarnya bisa mencapai 2,7 miliar rupiah per bulan.
Meski menggiurkan, penggunaan ulat tepung yang dijual Hendra masih terbatas sebagai pakan, bukan pangan. Abon MeFu—yang diproduksi untuk menutupi wujud asli ulat tadi—baru terjual rata-rata sebanyak 200 botol 30 gram dalam satu bulan. Perjalanan usaha Hendra untuk menjadikan ulat tepung sebagai sumber protein alternatif, nampaknya masih panjang.
Dari pengembangbiakan ulat ini bisa dikatakan bahwa manusia selalu mencari inovasi untuk menemukan bahan makanan dengan kandungan nutrisi terbaik. Ketika sumber protein tertinggi ada di pangan yang lazimnya menjijikkan, siapkah Anda?[]
*Rheza Ardiansyah adalah Pemerhati Masalah Pangan dan Jurnalis Metro TV