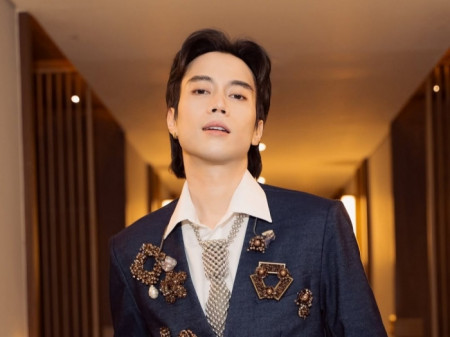SALAH satu tugas hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ialah memperkuat sistem pembentukan efek jera dengan menetapkan vonis yang membuat calon koruptor takut mencuri. Hakim di domain ini semestinya ialah mereka yang kejam terhadap koruptor, melalui penetapan vonis maksimal dari tuntutan hukuman yang diajukan jaksa.
Akan tetapi, kita kerap dihadapkan pada fakta adanya hakim yang justru gemar membebaskan terdakwa kasus korupsi, alih-alih menghukum berat. Janner Purba dan Toton, dua hakim tipikor di Pengadilan Tinggi Bengkulu, termasuk di antara hakim-hakim semacam itu.
Janner dan Toton dibekuk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap Rp650 juta, awal pekan ini. Uang itu diterima Janner dan Toton sehari sebelum keduanya memvonis dua terdakwa dalam perkara korupsi. Diduga kuat, uang suap yang diterima Janner dan Toton terkait dengan upaya para terdakwa untuk memengaruhi putusan.
Penangkapan Janner dan Toton, jika melihat rekam jejak mereka, sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Bahkan, keduanya semestinya sudah ditangkap sejak lama.
Janner dan Toton telah lama dikenal sebagai hakim yang gemar membebaskan koruptor. Hingga sebelum ditangkap, keduanya dilaporkan telah membebaskan 11 terdakwa perkara korupsi dalam berbagai persidangan.
Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, reputasi Janner itu jelas sangat mengenaskan. Janner yang semestinya membuat koruptor ketakutan, justru kerap menggembirakan para pencuri uang negara.
Kita tidak habis pikir, bagaimana mungkin Janner dan Toton dapat melakukan semua modus tercela tersebut. Yang lebih tidak bisa kita pahami ialah mengapa sistem peradilan kita melahirkan hakim-hakim pecundang seperti Janner dan Toton.
Logikanya, hakim-hakim korup dapat terlahir karena dua sebab. Pertama, karena sistem rekrutmen yang buruk. Kedua, karena sistem pembinaannya buruk.
Rekrutmen yang buruk dapat menghasilkan sumber daya hakim berkualitas rendah, baik secara intelektual, profesional, maupun moral. Pembinaan buruk dapat membuat calon hakim yang pada awalnya baik berkembang menjadi hakim yang akhirnya berkualitas rendah.
Kita khawatir banyaknya kasus hakim kita yang nakal ialah karena baik rekrutmen maupun pembinaan, keduanya sama-sama buruk. Karena sistem rekrutmen ataupun pembinaan hakim dan calon hakim berada di bawah otoritas internal Mahkamah Agung (MA), masuk akal pula bila kita menggugat tanggung jawab profesional dan moral lembaga itu dalam menjalankan kedua fungsi tersebut.
Benar, secara eksternal, ada Komisi Yudisial (KY) yang berhak memberikan rekomendasi hukuman terhadap hakim nakal. Akan tetapi, implementasi atas rekomendasi KY tidak selamanya dijalankan MA.
Perang melawan korupsi membutuhkan hakim yang mampu membuat koruptor dan calon koruptor ketakutan. Kita mau sistem rekrutmen dan pembinaan di MA melahirkan hakim-hakim tipikor semacam itu. Bukan hakim-hakim yang bekerja dengan sistem argo untuk mengamankan, menyamankan, dan membahagiakan koruptor.
Karena itu, harus ada perbaikan sistemis dan masif dari hulu di MA. Tanpa itu, yang ada hanya perbaikan tambal sulam, atau malah kamuflase.
Cek Berita dan Artikel yang lain di 
Editorial Media Indonesia ()
TERKAIT