medcom.id, Jakarta: Tanpa perlu menunggu pernyataan resmi dari pihak berwenang, sejumlah orang sudah mencuit di Twitter dengan nada mengaitkan, antara ledakan di Kampung Melayu, Jakarta dengan Manchester, Inggris, kemudian baku tembak di Marawi, Filipina. Ini serangan global!
Hal semacam ini tentu tidak terjadi pada peristiwa bom di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta 17 tahun silam, tepatnya pada 1 Agustus 2000. Alasannya sederhana; masyarakat awam belum mengenal apa itu Al Qaeda, terlebih ISIS.
Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2010. Foto: MI
Ya. Nama Al Qaeda baru diperkenalkan pasca serangan 11 September 2001 yang menyasar gedung WTC di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya, barulah kita mengenal istilah serangan teroris global itu dari Presiden AS George Walker Bush.
Sejak itu, setiap kejadian teror di dunia mesti dicap ulah jaringan yang berpusat di Afghanistan itu. Termasuk rangkaian teror yang ada di tanah air, mulai dari Bom Bali 1, yang terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan dan 1 hari setelah WTC (2002), kemudian Bom Kedubes Asutralia di kawasan Kuningan, Jakarta (2004), Bom Bali 2 (2005), dan seterusnya.
Jaringan garis keras ini baru agak berubah setelah heboh Arab Spring alias kebangkitan dunia Arab, yang tercetus pada 2010. Gelombang revolusi yang berujung pada penumbangan rezim berkuasa di negaranya masing-masing itu menjalar, dari Tunisia, Mesir, hingga Libya.
Hanya saja, gerakan yang mashur dengan slogan Ash-sha`b yurid isqat an-nizam (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini) itu tersandung di Suriah, negeri yang memiliki letak geografis paling menguntungkan, baik dari sisi politik maupun ekonomi, khususnya jalur minyak di Timur Tengah.
Di tengah panasnya konflik di Suriah, munculah sebuah kelompok anti-rezim yang baru pada 2014, yang mengenalkan diri dengan nama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).
ISIS semakin populer tatkala kabar kekejamannya menyeruak. Belum lagi klaim pertanggungjawabannya atas sejumlah aksi teror yang muncul di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Transnasional, begitulah rupa ISIS dan konsep kekhilafahan yang mereka usung.
Sebagai catatan, sejumlah penelitian dan analisa internasional mengungkap, ISIS pun bagian dari faksi-faksi dalam dinamika Al Qaeda. Kalau kata orang, ISIS adalah salah satu cucu Al Qaeda.
Dari Al Qaeda, kini ISIS, begitulah pengamatan awam soal jaringan garis keras yang kerap melancarkan aksi-aksi teror. Bila Al Qaeda yang kita kenal cenderung menganggap "Barat" adalah lawan, maka ISIS lebih spesifik. Negara-negara yang dianggap menghambat cita-cita khilafah, adalah musuh.
Bila sebelumnya kita menganggap target-target teror adalah sesuatu yang bersinggungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kini, teror lebih mengarah kepada perangkat-perangkat negara. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, aparat keamanan kerap menjadi target, dianggap sebagai lembaga paling agresif meredam gerakan mereka.
Jadi, mahfumlah ketika ada serangan-serangan teror, hampir semua orang mengalamatkan tuduhannya ke ISIS. Artinya, bila pelaku bom di Manchester tempo hari diumumkan terkait ISIS, lantas baku tembak di Marawi disebut-sebut jaringan yang berafiliasi dengan ISIS, maka di Kampung Melayu, Jakarta pun orang memandangnya sama, jaringan, faksi-faksi atau minimal simpatisan ISIS.
Analisa sederhana dari masyarakat ini pun dibenarkan oleh Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pelaku diduga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.
Ya. Analisa masyarakat semakin tajam ihwal aksi-aksi teror. Atau, boleh jadi ini soal Deja Vu (berulang kembali), karena setiap rentetan teror kerap dilakukan oleh jaringan garis keras yang itu-itu lagi.
Sadar bahwa jaringan teror merupakan ‘serangan global’, dua tahun terakhir, masyarakat dunia tampak kompak mengutuknya, di manapun teror itu terjadi. Media sosial menjadi senjata. Pikirannya nyaris sama semua, ada di sisi para korban.
Dimulai dari "Serangan Paris" pada November 2015. Tanda pagar (tagar) beraroma solidaritas, #PrayForParis, berhari-hari menjadi topik populer di media sosial. Doa dan ungkapan belasungkawa seolah menjadi perlawanan warganet terhadap aksi teror di ibukota Prancis itu.
Hingga kini, solidaritas global itu selalu muncul membuntuti aksi-aksi teror di manapun. Polanya selalu sama, seperti sudah menjadi konsensus bersama di kalangan warganet sedunia. #PrayForParis, #PrayForBrussels, #PrayForManchester, #PrayForMarawi, hingga terakhir dan untuk yang kedua kalinya, #PrayForJakarta.
Tempat kejadian ledakan bom di sekitar lokasi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5/2016). Foto: MI
Islam radikal
Di tengah riuh fenomena global soal teror dan solidaritas bagi korbannya, istilah Islam radikal pun kian santer di ruang percakapan. Tidak mengherankan, karena jaringan garis keras yang menjadi pelaku teror itu membawa embel-embel agama, dalam hal ini Islam.
Sejak Serangan 11 September di New York, Islam radikal bak sebutan formal bagi jaringan-jaringan garis keras penebar teror. Sebut saja Al Qaeda dan turunan-turunannya, termasuk ISIS, faksi-faksinya serta para simpatisannya. Bahkan, cap Islam radikal juga ditujukan kepada jaringan lain yang berpikiran sama dengan ISIS, yang bercita-cita menegakkan kekhalifahan tanpa sekat negara bangsa.
Nahasnya, tanpa disadari, cap itu seakan mencitrakan dikotomi, ada dua jenis Islam dalam konteks keagamaan. Yang satu Islam radikal, dan sudah pasti yang lainnya adalah Islam moderat.
Padahal, bagi sejumlah peneliti dan pengamat, sejatinya, radikalisme yang muncul tidak ada kaitannya dengan Islam sebagai agama. Salah satunya, peneliti yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali, mengatakan, "radikalisme bukan karena agama. Radikalisme karena politik."
Artinya, bila publik maupun negara membahasakan kelompok garis keras itu dengan sebutan Islam radikal, rasanya seperti memberi ruang kepada mereka untuk menggunakan legitimasi agama. Sementara, gerakannya cenderung bertolak belakang dengan kedamaian yang diajarkan agama.
Terlebih, bila cap Islam radikal itu tetap digunakan, maka, menjadi sebuah kesalahanlah solidaritas yang terbangun, alias blunder. Pasalnya, cap itu seakan membenarkan adanya dikotomi tadi, yang boleh jadi berujung konflik antar pemeluk agama Islam.
Baca juga: Kala Dunia Kesengsem Islam Indonesia
Tak heran bila disela-sela solidaritas global di media sosial, acap kali terselip kalimat, Islam bukan teroris, atau sebaliknya, teroris bukan Islam, serta beragam kicauan lain yang senada. Semua mempertegas untuk tidak mengaitkan tindakan yang tidak manusiawi itu dengan Islam.
Apalagi, Islam sebagai agama, tentu bersifat universal. Sudah pasti pula universalitas itu bukan untuk merajut jaringan teror. Dan inilah yang menjadi alasan untuk tidak memberikan ruang 'Islam' kepada kelompok radikal.
Dengan begitu, betul lah apa yang dilakoni Presiden Sukarno kala menghadapi ancaman perpecahan yang melibatkan kelompok Islam pada 1950-an.
Mulai dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), hingga peristiwa PRRI/Permesta yang melibatkan orang-orang dari partai Islam Masyumi, Bung Karno enggan membawa embel-embel Islam dalam penumpasannya. Pula tidak ada cap Islam radikal di sana. Semua cukup disebut "pemberontak".
Baca juga: Tidak Menjadi Nasionalis Kolot
Ya. Tampaknya, sudah tiba saatnya gerakan solidaritas global bergerak lebih agresif. Tidak lagi sekadar membuntuti peristiwa teror. Namun, menyerang dengan gegap, mendahului serangan terorisme global, dan kompak memisahkan aksi antikemanusiaan itu dengan Islam. Karena jelas, radikalisme bukan karena agama, tapi karena politik!
medcom.id, Jakarta: Tanpa perlu menunggu pernyataan resmi dari pihak berwenang, sejumlah orang sudah mencuit di Twitter dengan nada mengaitkan, antara ledakan di Kampung Melayu, Jakarta dengan Manchester, Inggris, kemudian baku tembak di Marawi, Filipina. Ini serangan global!
Hal semacam ini tentu tidak terjadi pada peristiwa bom di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta 17 tahun silam, tepatnya pada 1 Agustus 2000. Alasannya sederhana; masyarakat awam belum mengenal apa itu Al Qaeda, terlebih ISIS.
 Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2010. Foto: MI
Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2010. Foto: MI
Ya. Nama Al Qaeda baru diperkenalkan pasca serangan 11 September 2001 yang menyasar gedung WTC di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya, barulah kita mengenal istilah serangan teroris global itu dari Presiden AS George Walker Bush.
Sejak itu, setiap kejadian teror di dunia mesti dicap ulah jaringan yang berpusat di Afghanistan itu. Termasuk rangkaian teror yang ada di tanah air, mulai dari Bom Bali 1, yang terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan dan 1 hari setelah WTC (2002), kemudian Bom Kedubes Asutralia di kawasan Kuningan, Jakarta (2004), Bom Bali 2 (2005), dan seterusnya.
Jaringan garis keras ini baru agak berubah setelah heboh Arab Spring alias kebangkitan dunia Arab, yang tercetus pada 2010. Gelombang revolusi yang berujung pada penumbangan rezim berkuasa di negaranya masing-masing itu menjalar, dari Tunisia, Mesir, hingga Libya.
Hanya saja, gerakan yang mashur dengan slogan
Ash-sha`b yurid isqat an-nizam (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini) itu tersandung di Suriah, negeri yang memiliki letak geografis paling menguntungkan, baik dari sisi politik maupun ekonomi, khususnya jalur minyak di Timur Tengah.
Di tengah panasnya konflik di Suriah, munculah sebuah kelompok anti-rezim yang baru pada 2014, yang mengenalkan diri dengan nama ISIS (
Islamic State of Iraq and Syria).
ISIS semakin populer tatkala kabar kekejamannya menyeruak. Belum lagi klaim pertanggungjawabannya atas sejumlah aksi teror yang muncul di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Transnasional, begitulah rupa ISIS dan konsep kekhilafahan yang mereka usung.
Sebagai catatan, sejumlah penelitian dan analisa internasional mengungkap, ISIS pun bagian dari faksi-faksi dalam dinamika Al Qaeda. Kalau kata orang, ISIS adalah salah satu cucu Al Qaeda.
Dari Al Qaeda, kini ISIS, begitulah pengamatan awam soal jaringan garis keras yang kerap melancarkan aksi-aksi teror. Bila Al Qaeda yang kita kenal cenderung menganggap "Barat" adalah lawan, maka ISIS lebih spesifik. Negara-negara yang dianggap menghambat cita-cita khilafah, adalah musuh.
Bila sebelumnya kita menganggap target-target teror adalah sesuatu yang bersinggungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kini, teror lebih mengarah kepada perangkat-perangkat negara. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, aparat keamanan kerap menjadi target, dianggap sebagai lembaga paling agresif meredam gerakan mereka.
Jadi, mahfumlah ketika ada serangan-serangan teror, hampir semua orang mengalamatkan tuduhannya ke ISIS. Artinya, bila pelaku bom di Manchester tempo hari diumumkan terkait ISIS, lantas baku tembak di Marawi disebut-sebut jaringan yang berafiliasi dengan ISIS, maka di Kampung Melayu, Jakarta pun orang memandangnya sama, jaringan, faksi-faksi atau minimal simpatisan ISIS.
Analisa sederhana dari masyarakat ini pun dibenarkan oleh Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pelaku
diduga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.
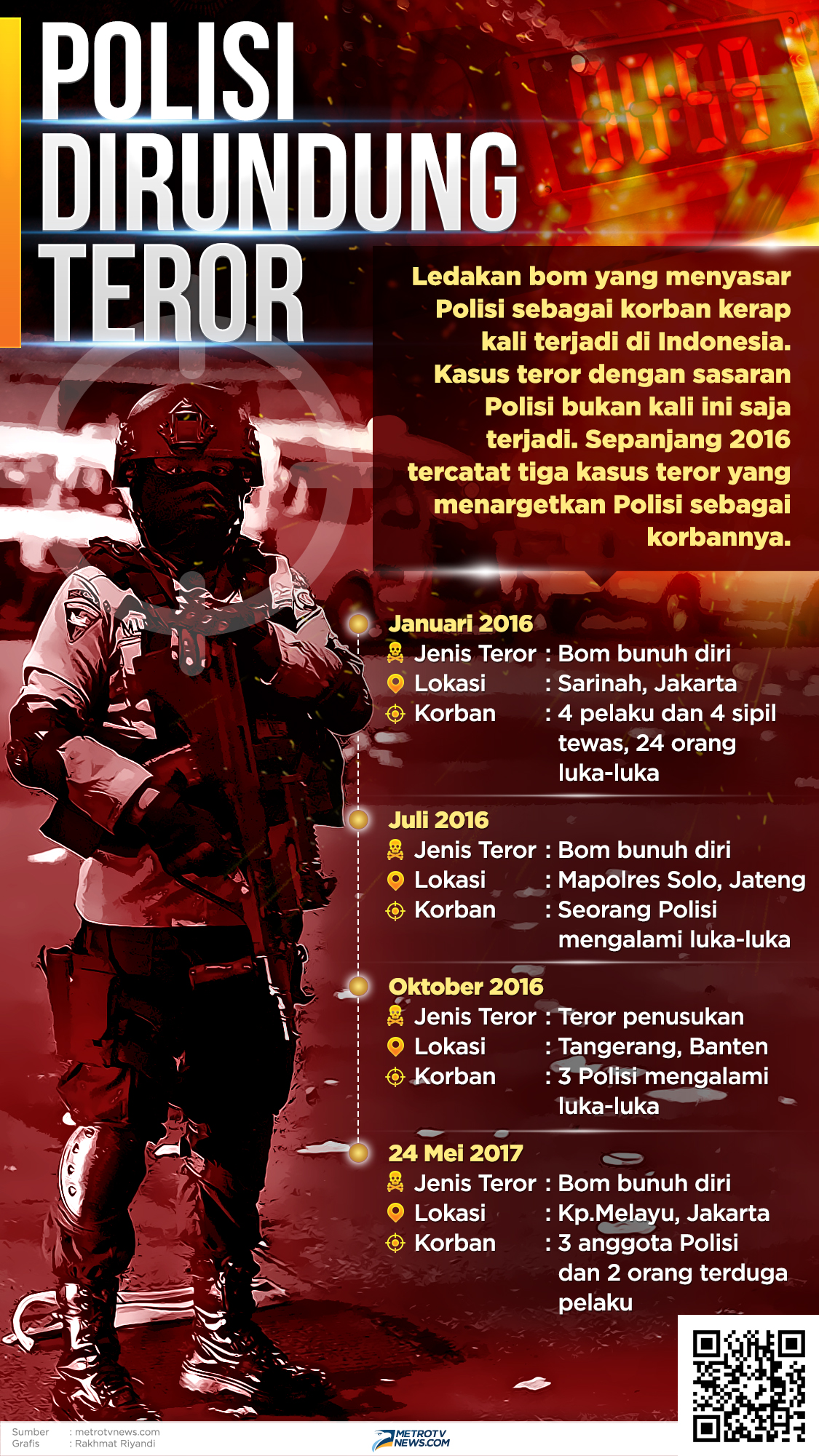
Ya. Analisa masyarakat semakin tajam ihwal aksi-aksi teror. Atau, boleh jadi ini soal
Deja Vu (berulang kembali), karena setiap rentetan teror kerap dilakukan oleh jaringan garis keras yang itu-itu lagi.
Sadar bahwa jaringan teror merupakan ‘serangan global’, dua tahun terakhir, masyarakat dunia tampak kompak mengutuknya, di manapun teror itu terjadi. Media sosial menjadi senjata. Pikirannya nyaris sama semua, ada di sisi para korban.
Dimulai dari "Serangan Paris" pada November 2015. Tanda pagar (tagar) beraroma solidaritas, #PrayForParis, berhari-hari menjadi topik populer di media sosial. Doa dan ungkapan belasungkawa seolah menjadi perlawanan warganet terhadap aksi teror di ibukota Prancis itu.
Hingga kini, solidaritas global itu selalu muncul membuntuti aksi-aksi teror di manapun. Polanya selalu sama, seperti sudah menjadi konsensus bersama di kalangan warganet sedunia. #PrayForParis, #PrayForBrussels, #PrayForManchester, #PrayForMarawi, hingga terakhir dan untuk yang kedua kalinya, #PrayForJakarta.
 Tempat kejadian ledakan bom di sekitar lokasi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5/2016). Foto: MI
Islam radikal
Tempat kejadian ledakan bom di sekitar lokasi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5/2016). Foto: MI
Islam radikal
Di tengah riuh fenomena global soal teror dan solidaritas bagi korbannya, istilah Islam radikal pun kian santer di ruang percakapan. Tidak mengherankan, karena jaringan garis keras yang menjadi pelaku teror itu membawa embel-embel agama, dalam hal ini Islam.
Sejak Serangan 11 September di New York, Islam radikal bak sebutan formal bagi jaringan-jaringan garis keras penebar teror. Sebut saja Al Qaeda dan turunan-turunannya, termasuk ISIS, faksi-faksinya serta para simpatisannya. Bahkan, cap Islam radikal juga ditujukan kepada jaringan lain yang berpikiran sama dengan ISIS, yang bercita-cita menegakkan kekhalifahan tanpa sekat negara bangsa.
Nahasnya, tanpa disadari, cap itu seakan mencitrakan dikotomi, ada dua jenis Islam dalam konteks keagamaan. Yang satu Islam radikal, dan sudah pasti yang lainnya adalah Islam moderat.
Padahal, bagi sejumlah peneliti dan pengamat, sejatinya, radikalisme yang muncul tidak ada kaitannya dengan Islam sebagai agama. Salah satunya, peneliti yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali, mengatakan, "radikalisme bukan karena agama. Radikalisme karena politik."
Artinya, bila publik maupun negara membahasakan kelompok garis keras itu dengan sebutan Islam radikal, rasanya seperti memberi ruang kepada mereka untuk menggunakan legitimasi agama. Sementara, gerakannya cenderung bertolak belakang dengan kedamaian yang diajarkan agama.
Terlebih, bila cap Islam radikal itu tetap digunakan, maka, menjadi sebuah kesalahanlah solidaritas yang terbangun, alias
blunder. Pasalnya, cap itu seakan membenarkan adanya dikotomi tadi, yang boleh jadi berujung konflik antar pemeluk agama Islam.
Baca juga: Kala Dunia Kesengsem Islam Indonesia
Tak heran bila disela-sela solidaritas global di media sosial, acap kali terselip kalimat, Islam bukan teroris, atau sebaliknya, teroris bukan Islam, serta beragam kicauan lain yang senada. Semua mempertegas untuk tidak mengaitkan tindakan yang tidak manusiawi itu dengan Islam.
Apalagi, Islam sebagai agama, tentu bersifat universal. Sudah pasti pula universalitas itu bukan untuk merajut jaringan teror. Dan inilah yang menjadi alasan untuk tidak memberikan ruang 'Islam' kepada kelompok radikal.
Dengan begitu, betul lah apa yang dilakoni Presiden Sukarno kala menghadapi ancaman perpecahan yang melibatkan kelompok Islam pada 1950-an.
Mulai dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), hingga peristiwa PRRI/Permesta yang melibatkan orang-orang dari partai Islam Masyumi, Bung Karno enggan membawa embel-embel Islam dalam penumpasannya. Pula tidak ada cap Islam radikal di sana. Semua cukup disebut "pemberontak".
Baca juga: Tidak Menjadi Nasionalis Kolot
Ya. Tampaknya, sudah tiba saatnya gerakan solidaritas global bergerak lebih agresif. Tidak lagi sekadar membuntuti peristiwa teror. Namun, menyerang dengan gegap, mendahului serangan terorisme global, dan kompak memisahkan aksi antikemanusiaan itu dengan Islam. Karena jelas, radikalisme bukan karena agama, tapi karena politik!
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(COK)
 Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2010. Foto: MI
Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2010. Foto: MI
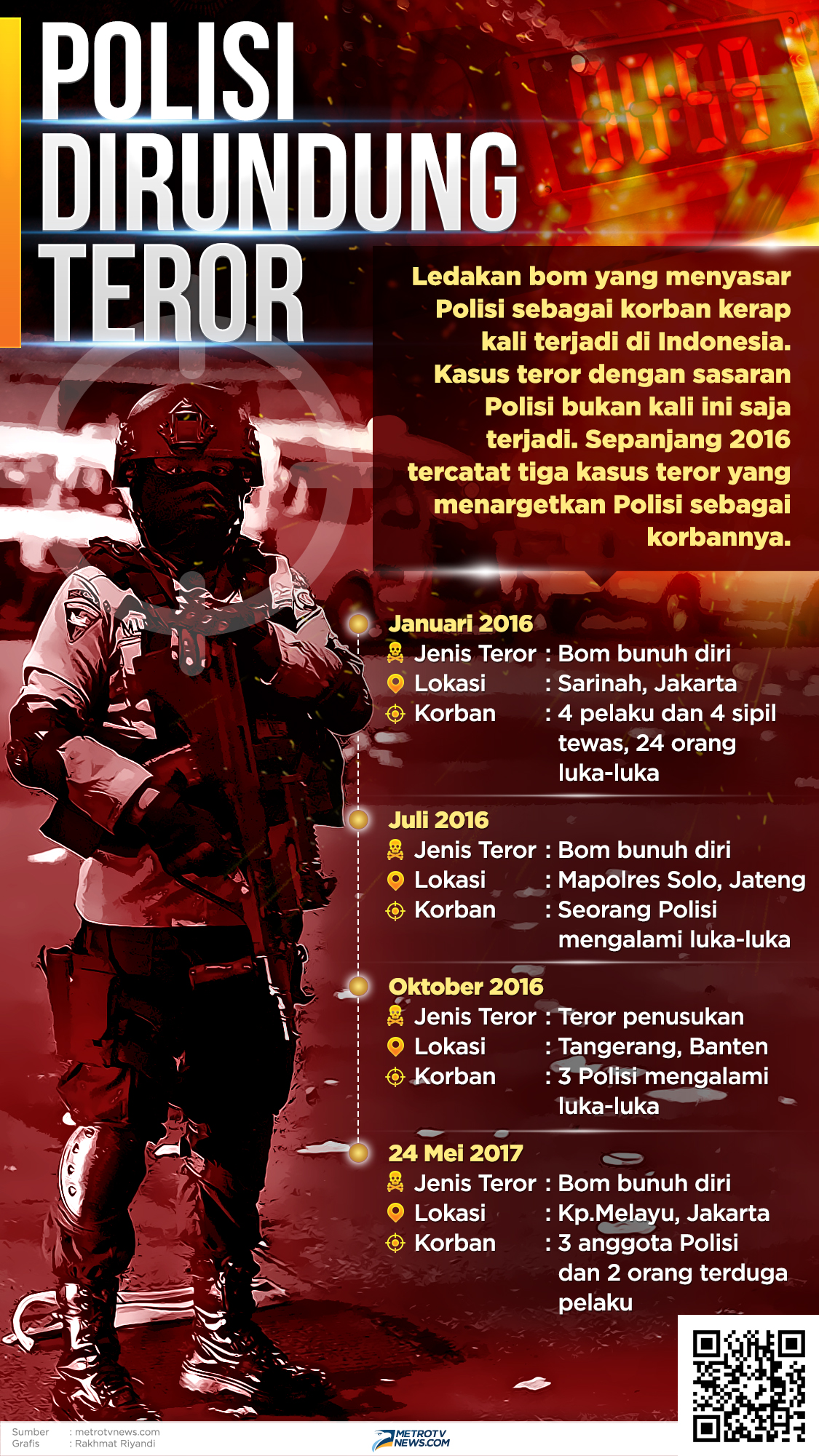
 Tempat kejadian ledakan bom di sekitar lokasi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5/2016). Foto: MI
Tempat kejadian ledakan bom di sekitar lokasi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5/2016). Foto: MI




















