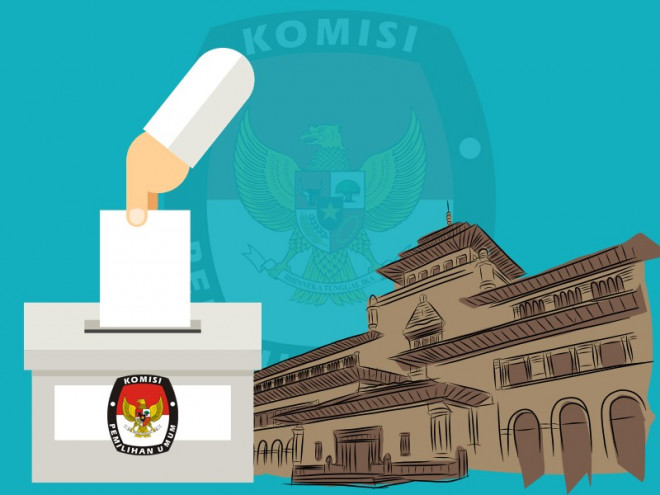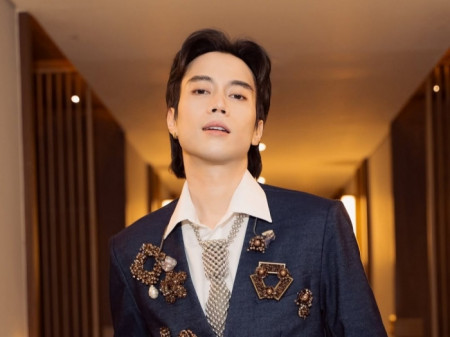Kedai itu berkonsep pusat jajan dengan gaya outdoor. Lokasinya di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat - persis di seberang kampus IAIN Syekh Nurjati.
Malam itu, Sabtu, 18 November 2017, obrolan yang mencuat tentang eksistensi wilayah Pantura (pantai utara), terkait pergulatan politik di Jawa Barat. Maklum, setahun lagi pemilihan gubernur akan dihelat.
Wilayah Pantura Jawa Barat, yang mencakup Kota/Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Subang, merupakan satu dari tiga subkultur yang membuat Jawa Barat unik, juga rumit. Secara tradisional, wilayah-wilayah tersebut merupakan eks-Karesidenan Cirebon. Banyak kalangan menyebutnya dengan 'cirebonan'.
Termasuk soal bahasa lokal, bahasa ibu orang Pantura didominasi Bahasa Cirebon, bukan Bahasa Sunda. Sementara dari sisi budaya, cirebonan lebih terpengaruh kepada "Tanah Jawa", yakni, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Subkultur lain adalah Jabar Priangan, mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan sebagian Karawang.
Bicara Sunda, maka Priangan inilah yang dimaksud. Terbesar secara wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh.
Terakhir, subkultur Jabar Jabodetabek. Sudah jelas, wilayahnya adalah kota atau kabupaten yang mendapatkan pengaruh metropolitan secara langsung. Yakni, wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta; Bekasi, Depok dan sebagian kecil Bogor.
Jadi, bila ada persinggungan identitas dalam kontestasi politik di Jawa Barat, biasanya bukan berlatarbelakang kepartaian atau ideologi, tapi subkultur. Itu pun halus dan tidak terlalu mencolok.
Tagih janji
Semakin malam perbincangan kian serius, tapi tetap santai. Sesekali terdengar kelakar yang memancing tawa.
Meski menyoal politik identitas, perbincangan tidak menjurus kepada pembelahan politik nasionalis atau relijius. Tak disinggung pula soal Islam fundamental, Islam tradisional, dan nonmuslim, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak - merujuk "efek" Pilkada DKI Jakarta.
Agung Firmansyah, salah satu warga Cirebon yang kami temui di Saung Perjuangan, mengakui, politik identitas berbasis subkultur kerap hadir dalam kontestasi politik di Jawa Barat.
Kemunculan politik identitas subkultur ini bukan tanpa alasan. Pantura, di mata Agung dan kawan-kawan, bak wilayah yang 'dianaktirikan'. Dilirik saat Pilkada, dicampakkan seusai pesta.
Mahfum, wilayah Pantura tidak memiliki potensi suara besar. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dari gabungan wilayah itu hanya 3,5 juta jiwa. Nyaris sebanding dengan satu Kabupten Bogor, yakni 3,3 juta jiwa, juga Kabupaten Bandung yang berpenduduk 2,4 juta jiwa.
Pantura kerap tak kebagian rembesan kebijakan para calon yang menjadi juara. "Dari sederet janji kampanye Pilkada, yang sudah-sudah, kesejahteraan daerah Pantura, ya segitu-gitu saja," ujarnya.
Di Pantura, angka kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan ekonomi pun tak terlalu mumpuni.
Bagi Agung, sudah semestinya Pantura menentukan sikap. Tak peduli siapa dan dari mana pemenang Pilkada, Pantura harus memadukan tekad untuk menagih janji-janji kampanye si pemenang.

Suasana diskusi di Saung Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 18 November 2017. MTVN/Coki
Masih di area Saung Perjuangan, kami pun bertemu Budayawan yang juga Filolog Cirebon Raffan S. Hasyim. Pria yang karib disapa Mama Opan itu tampak menguatkan tekad para remaja yang terlibat dalam diskusi, tentu melalui sudut pandang sejarah dan budaya.
Menurut Opan, meski jumlah penduduk Pantura sedikit dan tidak memiliki pengaruh sekuat priangan, orang Pantura tidak perlu minder.
Secara historis, kata Opan, sunda priangan dan cirebonan sama tua. "Jadi, perjuangkan hak-hak melalui momen Pilkada itu adalah baik."
Pada akhirnya, boleh dikata, dalam obrolan serius nan santai itu, tidak lagi bicara dukungan bagi calon dari partai A atau partai B, ideologi politik A maupun ideologi politik B. Hal-hal semacam itu mulai buyar.
Kalau bisa, siapapun pasangan calon yang bertarung, ada orang Panturanya. Kalau tidak ada, mau tak mau harus bawel menagih janji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News