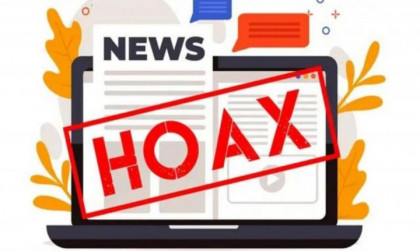medcom.id, Jakarta: Setiap priayi boleh datang atas nama kekuasaan, tak peduli mereka adalah hansip, mantri pasar, opas kecamatan, atau seorang pejabat dinas perkebunan negara seperti Marsusi. Dan ketika kekuasaan, menjadi aspek yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat, orang Dukuh Paruk seperti Srintil tidak mungkin mengerti perbedaan antara polisi, tentara, dan pejabat perkebunan. Semuanya adalah tangan kekuasaan dan Srintil tidak mungkin bersikap lain kecuali tunduk dan pasrah.
Kurang lebih seperti inilah wajah birokrat di masa lampau saat ditilik dari aneka ragam latar novel-novel terbitan lawas. Ronggeng Dukuh Paruk (1982) karya Ahmad Tohari termasuk salah satu novel yang begitu gamblang memaparkan kondisi sekaligus kesan para birokrat dalam satu-dua adegan. Sebelum Tohari, banyak lagi, yang lebih fenomenal adalah novel berjudul Ziarah (1969) yang ditulis oleh sastrawan Iwan Simatupang, di dalamnya bahkan dilengkapi seabrek rutinitas yang tampak membosankan; masuk kantor, membaca surat-surat, mengangkat telepon berdering, dan melongok arloji dengan putaran waktu yang terasa amat panjang.
Para birokrat memiliki dua wajah kontras yang berbarengan dalam pandangan masyarakat Indonesia. Satu sisi, mereka kerap diposisikan sebagai sebuah profesi ideal yang ditopang segala bentuk kesejahteraan. Di tahun 1990-an, posisi birokrat yang kerap diwakili oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menduduki posisi teratas dalam stratifikasi sosial di tengah masyarakat. Keidealan profesi sebagai birokrat, PNS, atau kepanjangan tangan negara tentu bukan sembarang anggapan. Mereka dikenal sebagai satu-satunya profesi paling menjamin masa depan lantaran bergaji, penuh tunjangan, terdapat istilah “pensiunan” yang sampai kapanpun akan tercukupi dalam segi rezeki. Di masyarakat lampau bahkan beredar sebuah pameo “Belajarlah yang rajin, biar bisa jadi PNS,”.
Sisi berikutnya justru berbanding terbalik. Para birokrat –terutama di tingkat bawah-kerap pula direpresentasikan sebagai simbol masyarakat serba pas-pasan. Mereka bergaji tergantung pada nasib inflasi, bayaran di bawah standar, menyelami profesi serupa kacung, atau keterikatan yang teramat kuat dengan segenap peraturan. Kadang-kadang, birokrat kelas rendah sering diposisikan sebagai simbol perlawanan dari panjangnya tali rantai sistem yang mereka ikuti.
Kehadiran wajah birokrat di Indonesia dengan dua kesan yang saling bertolak belakang ini bukan sesuatu yang baru. Birokrat merupakan profesi dengan perjalanan sejarah cukup panjang. Ia hadir di setiap era, jika mengukur pada ruang-ruang besar garis waktu, setidaknya ia bisa ditilik dari tiga zaman, sebelum dan sesudah masa kolonial, awal kemerdekaan hingga orde baru, serta masa paling terkini, masa-masa penuh jargon “reformasi birokrasi”.
Kaum Perlente di Zaman Kolonial
Jauh sebelum para penjajah datang, istilah birokrat sudah hadir dalam penyebutan struktur dan sistem kekuasaan kerajaan. Di banyak kerajaan Jawa, para pelaksana titah sang raja menduduki posisi bergengsi di tengah masyarakat. Di dalam lingkungan kerajaan setidaknya ditunjuk empat orang pejabat sekelas menteri yang kerap disebut Wedana Lebet. Guna memperlancar kerja Wedana Lebet, ditetapkan pula seorang pemangku yang bertugas mengkoordinir arahan raja, posisi penting ini di dalam kerajaan besar, termasuk Singosari dan Majapahit dinamakan Patih alias Pepatih Lebet.
Di bawah Patih, berjajar banyak orang-orang yang saat di luar lingkungan kerajaan akan mendapatkan peran dan posisi terhormat. Mereka dianggap sebagai orang-orang terpercaya dari lingkungan kerajaan atau keraton. Untuk porsi pekerjaan dan tugas, para pejabat yang masih berkutat di dalam lingkungan kerajaan ini disebut Abdi Dalem.
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia III (Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia) menjelaskan bahwa pola birokrasi yang diadopsi kerajaan-kerajaan pendahulu Hindu-Budha terus berlangsung hingga era kejayaannya tergantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Di tengah masyarakat, orang-orang birokrat kerajaan dianggap golongan elite lantaran pekerjaan dan tugas yang mereka geluti. Dalam perkembangannya, golongan elite masyarakat ini meluas tidak hanya untuk sekitar kerajaan atau keraton, melainkan kepada setiap lini yang bersinggungan dengan mereka, seperti golongan aristokrasi, tentara, keagamaan, pedagang, dan plutokrasi.
Tidak hanya berlaku tinggi di tengah masyarakat. Secara spesifik Marwati juga mengutarakan di dalam golongan birokrat juga berlaku tingkatan dan kelas berbeda. Mereka dibedakan dalam kelas yang relatif dan disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan di kerajaan.
“Kaum aristokrat dan kaum bangsawan ada yang menempati suatu jabatan pada pemerintahan sebagai golongan elite birokrat. Kecuali di Mataram Islam ada demarkasi antara elite birokrat (priayi) dengan kaum bangsawan (bendara). Di Mataram, golongan elite birokrat itu disebut priayi yang terbagi atas priayi gede dan priayi cilik,” tulis Marwati.
Di luar lingkup kerajaan, jaringan birokrat dan para priayi ini diwakili oleh para bupati hasil tunjuk langsung sang raja. Mereka yang kemudian diamanati sebagai penguasa daerah yang mewakili kerajaan pusat biasanya berasal dari pejabat bupati lama yang telah ditaklukkan, pemuka masyarakat, atau saudara dan kolega raja sendiri.
Di periode berikutnya, keberlangsungan sistem birokrasi kerajaan tradisional dilestarikan secara turun temurun. Mereka tak lagi memakai sistem tunjuk dari kerajaan. Untuk jabatan bupati, misalnya, ia bisa secara langsung mendapuk putra mahkota sebagai pelanjut wewenang. Dalam posisi ini pada akhirya sistem birokrasi dibentuk berdasarkan jalur keturunan yang disebut dengan istilah darah biru.
Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, sejarawan M.C Ricklefs membatasi kekuatan birokrasi melalui jalur keturunan ini pada tahun 1900. Menurut dia pada periode tersebut prestise, kekuasaan, dan kepercayaan diri kaum elite bangsawan Jawa mencapai titik rendah. Hal ini disumbang atas pengaruh kolonial penjajah Barat yang semakin kuat merecoki bahkan mengambil alih kebijakan kerajaan yang pada masanya mendirikan bentuk pemerintahan tersendiri.
“Elite bangsawan yang lebih tinggi merasakan adanya tantangan dari kelompok pejabat baru yang jumlahnya semakin besar. Kalangan atas dalam pemerintahan Jawa secara kolektif disebut 'priayi', dan kelompok pejabat baru tadi dapat disebut priayi 'baru' atau 'yang lebih rendah'.Munculnya kelompok ini mencerminkan adanya ambivalensi dalam kebijakan kolonial pada akhir abad XIX mengenai perlunya bentuk kekuasaan yang 'tradisional'. Tugas-tugas mereka adalah baru seluruhnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh dinas-dinas pemerintahan yang baru,” tulis Ricklefs.
Para priayi baru pada masa ini juga turut diberi gelar dan kemegahan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan status dan menambah kekuatan dan pengaruh di tengah masyarakat pribumi.
“Pada tahun 1861, misalnya, guru-guru sekolah pemerintah diberi pangkat mantri guru dan hak untuk tampil di depan umum dengan sebuah payung, sebuah tombak, sebuah tikar, sebuah perangkat buah pinang, dan empat orang pengiring,” tulis Ricklefs.
Para priayi baru dalam perkembangan selanjutnya menempati aneka profesi mulai dari juru tulis di kantor-kantor, mantri, guru, ambtenaar (pangreh praja), para pakar hukum yang bergelar sarjana hukum (meester in de rechten), sarjana teknik (ingenieur), atau dokter Jawa (Javansche Artsen).
Peran dalam pekerjaan administrasi dan keahlian profesional kalangan priayi memperkuat potensi ekonomi mereka sebagai kelompok konsumen kelas menengah. Pendapatan priayi yang berposisi sebagai elite mencapai jumlah 7,25 persen dari seluruh jumlah pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang mayoritas kulit putih. Pendapat terendah kaum priayi kecil ditempati mereka yang berposisi sebagai staf administrasi (semacam juru tulis kelas satu atau kelas dua) yaitu kurang dari 50 gulden per bulan, dan jumlah mereka sebagai mayoritas yaitu 92,61 persen dari keseluruhan pegawai gubernemen.
“Dalam tingkatan yang berlapis sesuai dengan pendapatannya, mereka membentuk gaya hidup dan pola konsumsi yang mengacu kepada kiblat gaya hidup kaum kulit putih Barata para tuan kolonialnya,” tulis Budi Susanto dalam Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia.
Di era kolonial, para birokrat alias priayi baru ini tampil berbeda untuk menunjukkan eksistensinya di tengah golongan pribumi. Mereka tampil sebagai sosok ideal yang modern, cerdas, rapi, berpendidikan, dan tentu; perlente.
Birokrat dan Sumbangsih Pendidikan Barat
Kolonial Belanda mendobrak tradisi lokal mengenai pola kebangsawanan yang telah ratusan tahun diadopsi masyarakat Nusantara. Kini, jalur kebangsawanan bisa ditempuh melalui peran serta di jalur-jalur birokrasi Hindia Belanda, jalannya disediakan melalui sekolah-sekolah kepegawaian ala kaum terpelajar Barat.
“Dengan pendidikan modern terjadi proses mobilitas sosial vertikal yang memungkinkan kaum wong cilik menaiki tangga status sosial sebagai golongan priayi baru yang disebut sebagai priayi gobernemen atau priayi profesional,” tulis Budi Susanto dalam buku yang sama.
Dalam serinya yang lain, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto memaparkan jasa pertama dari pengajaran sistem Barat ialah memperkuat dasar legitimasi atau kesahan bagi penguasa pribumi. Para calon birokrat pemerintahan kolonial dari kalangan pribumi lebih percaya diri karena merasa telah terkumpul dalam dua sumber kesahan, yaitu keturunan yang mempunyai tarikan tradisional dan penguasa asing.
“Oleh karena itu, tuntutan bagi pengajaran Barat sangat keras bergema di kalangan mereka. Tuntutan ini menjadi lebih keras karena dimulainya pelebaran kelas pegawai oleh pemerintah kolonial. Keluhan-keluhan tentang pelebaran kelas pegawai atau priyayi adalah gejala yang agak umum juga pada awal abad ke-20,” tulis Marwati dalam Sejarah Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda).
Marwati menjelaskan, para pegawai lama yang sebelumnya mendapatkan status sebagai goloongan elite hanya bertopang pada kebanggaan keturunan maka mau tidak mau harus melebur dalam pola baru demi mempertahankan harkat kepegawaian yang sebelumnya diraih berkat hubungan khusus dengan raja.
“Begitu umpamanya, pada tahun 1905 bupati dari Tuban mengeluh bahwa dari 260 orang priyayi yang baru diangkat di keresidenan Rembang hanyalah sepuluh orang yang mendapat didikan OSVIA,” tulis Marwati.
OSVIA merupakan kepanjangan dari Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren aliaas sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai pribumi yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900. Lulusan OSVIA berhak dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Pada mulanya, OSVIA menerbitkan sistem belajar selama lima tahun, namun pada 1908 masa belajar ditambah menjadi tujuh tahun.
Pada 1927, OSVIA mengubah nama menjadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren). Dalam lembaga pendidikan baru ini, pemerintah Hindia Belanda hanya menerima peserta didik yang merupakan lulusan dari sekolah lanjutan khusus Bumiputera, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) –setingkat sekolah menengah pertama–untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat.
“Pengajaran diberikan di sekolah kelas I kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta, di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi pada umumnya. Sekolah jenis pertama didirikan menurut Stb. 1893 no. 128, di ibu kota keresidenan, afdeling, dan onderafdeling atau kota pusat perdagangan dan kerajinan. Pada tahun 1903 terdapat 14 sekolah kelas I di ibu kota keresidenan dan 29 di ibu kota afdeling,” tulis Marwati.
Kelak, sekolah kepegawaian yang meluluskan para calon birokrat ini terus berubah nama dan beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial-politik yang berlaku. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendirikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) pada 1948. Selanjutnya didirikan pula Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada t17 Maret 1956, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada 1967, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada 18 Agustus 1992. Lembaga-lembaga pendidikan calon birokrat ini tersebar di Malang, Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.
Perubahan terakhir muncul pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dan IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyusul terungkapnya kasus kekerasan di salah satu sekolah tinggi tersebut.
Para birokrat masa republik awal
Tidak banyak data yang menyinggung mengenai wajah para birokrat pada masa penjajahan Jepang. Namun sedikit gambaran tertera dalam buku Konflik di Balik Proklamasi yang ditulis oleh St. Sularto dan D. Rini Yunarti, di dalamnya dijelaskan dampak kehadiran dan kekejaman pemerintahan militer Jepang yang berlangsung tak lebih dari empat tahun memang meninggalkan kebencian karena kekejaman dan kerakusannya, namun di sisi lain, ada nilai “positif” yang tersembunyi dalam hal pola kebirokrasian yang dianut.
“Struktur birokrasi pemerintah tidak didominasi penjajah seperti halnya di zaman Belanda, melainkan untuk posisi-posisi menengah ke bawah diserahkan kepada rakat pribumi,” tulis Sularto.
Dualisme jalur birokrasi mengawali persoalan ruang kerja para birokrat di awal kemerdekaan. Pada 1948, pemerintah Indonesia mengadopsi dua kantor kepegawaian yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya dalam porsi yang sama. Kedua kantor brokrasi ini adalah Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang didirikan pemerintah Indonesia saat berkedudukan di Yogyakarta melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1948 pada 30 Mei 1948, dan Kantor Urusan Umum Pegawai (KUUP) yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) saat berkedudukan di Jakarta.
KUUP dibentuk melalui Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 10 pada 20 Februari 1946. Kantor ini sebelumnya berada di bawah Departemen Urusan Sosial, namun dengan Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948, kantor tersebut diganti dengan mnama Djawatan Urusan Umum Pegawai (DUUP).
Tak lama, setelah Indonesia telah benar-benar meraih kedaulatannya, KUP dan DUUP dilebur menjadi satu melalui PP Nomor 32 Tahun 1950 dengan nama Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang berada di bawah dan bertanggugjawab kepada perdana menteri. Sayangnya, akibat ketidakstabilan suasana politik saat itu, KUP yang bertanggungjawab penuh dalam usaha penataan birokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya lantaran pada 17 Agustus 1950 terjadi pergantian konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 yang berimbas pada perubahan bentuk birokrasi yang dikembalikan ke dalam pola negara kesatuan.
Akibat belum adanya pola yang pasti dalam format birokrasi yang dipakai, pada 1953 T.R Smith membantu pemerintah Indonesia dengan merekomendasikan laporan untuk Biro Perancang Negara dengan judul Public Administration Training.
"Setahun kemudian, dua orang profesor dari Cornell University, School of Business and Public Administration Amerika yang diundang ke Indonesia yaitu Edward H. Lichtfeld dan Alan C. Rankin yang berhasil menyusun laporan rekomendasi yang berjudul Training for Administration in Indonesia. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 9 April 1957) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 dibentuk Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian atau Panitia Organisasi Kementerian (PANOK) sebagai pengganti Kantor Urusan Pegawai (KUP) serta ikut dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertugas menyempurnakan administratur negara atau birokrasi keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri," tulis Samodra Wibawa dalam Negara-Negara di Nusantara.
Pada 5 Juli 1959, dikeluarkan dekrit presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang melarang PNS golongan F menjadi anggota partai politik. Dua tahun kemudian, yakni 1961 dikeluarkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan dibentuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) diikuti dengan lembaga baru bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang pokok-pokok organisasi aparatur pemerintah negara tingkat tertinggi.
"Pada 1963, dikeluarkan Keppres Nomor 98 Tahun 1964 dibentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR) merupakan kelanjutan dari Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir ini lebih bernuansa politis dengan penyingkiran birokrat yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party) atau yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan republik," tulis Samodra.
PNS dan teduhnya pohon beringin
Pola pengorganisasian birokrasi yang penuh ketidakpastian terus berlanjut hingga pengujung Orde Lama. Hal itu diperparah oleh peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai-partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan, program rekrutmen birokrasi ikut mengalami spoil system yang merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya di luar tugas birokrasi.
Pada 1966, Presiden Suharto kembali membentuk panitia pengorganisasian birokrasi sebagai pembantu presidium yang kemudian dikenal dengan nama Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah atau disingkat menjadi Tim PAAP. Tim ini beranggotakan sebelas orang dengan Menteri Tenaga Kerja selaku ketua didampingi oleh Direktur LAN sebagai sebagai sekretaris serta dibantu oleh lima orang penasehat ahli yang mengusulkan unit kerja baru bernama Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat tercermin dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.
Pada 1968 kembali dibentuk Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah yang disebut pula sebagai Proyek 13 disusul dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1968 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968. Proyek 13 ini kemudian berganti nama menjadi Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara yang lebih dikenal dengan nama Sektor P dengan anggota terdiri dari LAN, BAKN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Transmigrasi dan Koperasi. yang diketuai oleh Awaloeddin Djamin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dengan tugas agar dapat menyempurnakan administrasi pemerintahan.
Saat Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara bertugas melanjutkan pembersihan birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan berpolitik kepartaian. Lantas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan pula Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia. Tim PAAP dan Proyek 13 pun akhirnya dilebur ke dalam Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, sementara Sektor P tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara yang dipimpin oleh seorang menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban). Pada tahun berikutnya, Keppres Nomor 45/M Tahun 1983 Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara diubah kembali menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang secara langsung menteri yang menjabat akan merangkap sebagai wakil Ketua Bappenas.
Alih-alih membersihkan para birokrat dari aktivitas kepartaian, melalui Golongan Karya (Golkar) pemerintah Orde Baru justru mendapatkan dukungan kuat dari para pegawai negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa ini, PNS dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan PNS dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Meski secara formal pegawai negeri tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.
“Dampak negatif dari monoloyalitas PNS dalam politik ini sangat dirasakan, di mana birokrasi kemudian lebih menampilkan eran dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan kekuasaan,” aku Akbar Tandjung dalam The Golkar Way.
Keterikatan kuat antara para birokrat dan Golkar dalam berpuluh tahun memberikan relasi yang saling menguntungkan dan berketergantungan. Bahkan dalam era reformasi, perlu banyak waktu untuk memisahkan dua hal ini. Termasuk, gagasan reformasi birokrasi yang terus didengungkan untuk membuang kekhawatiran terjerembabnya para birokrat pada lubang yang sama di setiap masa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sejumlah PNS Biro Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta. (foto: Antara/Widodo S Jusuf)
Wajah Para Birokrat di Tiga Zaman
Sobih AW Adnan • 14 Maret 2016 21:23
LEAVE A COMMENT
LOADING