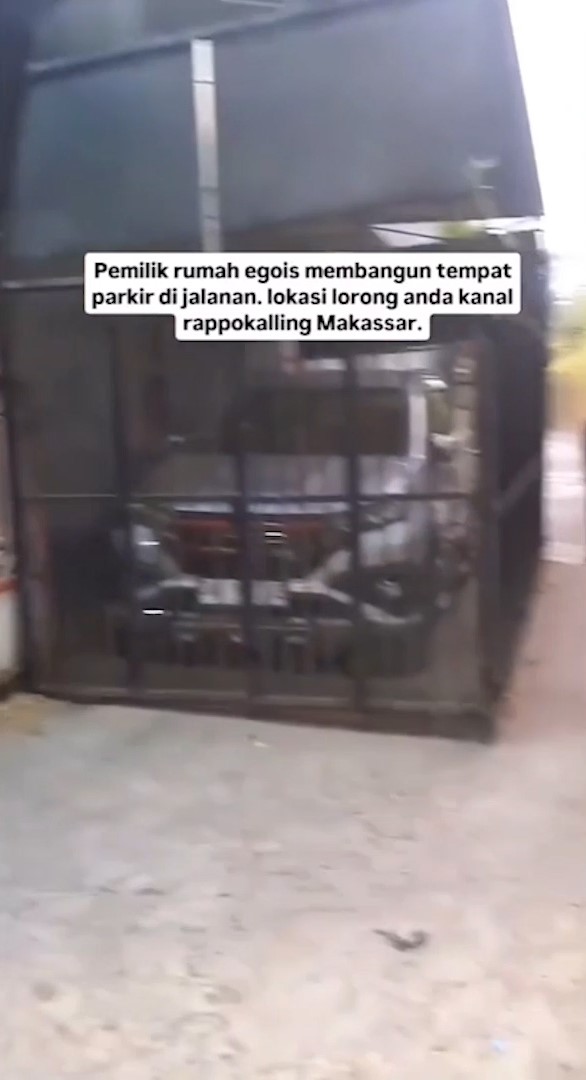Ditengarai situasi kemacetan DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar atas penilaian buruk ini. Apalagi Badan Pusat Statistik juga mencatat pada tahun 2016 perbandingan jumlah kendaraan di Jakarta terhadap panjang jalannya adalah 2.077 unit kendaraan per satu kilometer. Artinya, tingkat kepadatan kendaraan di jalanan Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi yang lainnya.
Kondisi ini diperparah dengan tidak efisiennya sistem lalu lintas di Jakarta. Per Januari 2017, menurut survei Numbeo, indeks inefesiensinya sebesar 301,09. Salah satu faktornya adalah jumlah penduduk dan tingginya mobilitas.
Angka tersebut menempatkan Jakarta di urutan kesebelas dunia atau kelima di Asia terkait sistem lalu lintas yang tidak efisien. Sementara bila dinilai berdasarkan indeks lalu lintas secara keseluruhan, Jakarta berada di posisi ketujuh terburuk di dunia. Indikatornya rata-rata durasi waktu perjalanan, estimasi waktu, ditambah inefisiensi sistem lalu lintas tadi.
Dengan demikian, Jakarta hanya lebih baik dari enam kota lain di dunia. Yakni Koltaka, Dhaka, Mumbai, Sharjah, Nairobi, dan Manila.
Meminjam istilah yang digunakan oleh Indonesia Traffic Watch (ITW), boleh dibilang Jakarta sudah di titik “gawat darurat”.
Tidak lepas tangan
"Lalu lintas di Jakarta brengsek. Sayalah yang paling tidak puas terhadap keadaan itu." Inilah celoteh Ali Sadikin, dua hari setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1966.
Keluhan gubernur Jakarta nan legendaris yang akrab disapa Bang Ali itu tertuang dalam memoar Ali Sadikin karangan Ramadhan KH. Jelas, kemacetan memang problem klasik ibu kota sejak dulu.
Pada masa menjabat kepala pemerintahan DKI Jakarta, Bang Ali mengambil langkah pembangunan transportasi massal sebagai solusi untuk mengurai kemacetan. Sejumlah terminal bus didirikan.
Bahkan, rencana induk tata ruang Jakarta juga disiapkan –dahulu dikenal dengan sebutan Masterplan 1965-1985. Berbasis pada dokumen tersebut, Jakarta mulai berbenah.
Dalam perancangannya, sangat tampak bahwa mobilitas Jakarta berorientasi kepada transportasi massal. Bahkan, kala itu pembangunan monorail dan subway sudah disebut-sebut.

FOTO: Kemacetan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kala pemberlakuan sistem pelat ganjil-genap. (ANTARA)
Buram
Perubahan paradigma terjadi di masa Gubernur Soeprapto. Minimnya infrastruktur jalan dianggap satu-satunya faktor penyebab kemacetan.
Asumsi rasio jalan terhadap kendaraan menjadi patokan. Hasilnya, panjang jalan selalu kurang. Ini pula yang menjadi alasan pemerintah di masa Orde Baru memacu pembangunan jalan layang dan jalan tol.
Pada sisi lain, investasi besar otomotif sedang dibuka lebar, khususnya dari Jepang. Industri otomotif bergeliat masif, menangguk keuntungan dari situasi yang ada. Sementara, konsep transportasi massal boleh dikata semakin 'buram'.
Alhasil, kemacetan bak warisan. Dari periode ke periode, gubernur silih berganti, problem ini terus menghantui Jakarta.
Persoalannya pun nyaris sama: infrastruktur jalan minim, bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, ketiadaan tempat parkir khusus, termasuk ketidaktertiban pengguna jalan.
Coba-coba
Solusi terus dicari agar kemacetan bisa terurai. Hasilnya, bak 'bongkar pasang' kebijakan. Tak berhasil di kebijakan yang satu, akan diganti dengan yang baru. Terus menerus begitu.
Ambil contoh kebijakan three in one (3 in 1) di sejumlah ruas jalan protokol pada masa Gubernur Sutiyoso (2003). Yaitu kebijakan mengendalikan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Gatot Subroto dengan mewajibkan kendaraan pribadi jenis roda empat berpenumpang paling sedikit tiga orang pada jam-jam tertentu.
Setelah berjalan cukup lama, kebijakan 3 in 1 akhirnya dicabut pada masa Gubernur Basuki Tjahja Purnama (2016), karena dianggap tidak efektif. Ahok –sapaan Basuki, menggantinya dengan pembatasan roda empat berdasarkan plat nomor kendaraan.
Saat tanggal ganjil, yang boleh melintas hanya mobil dengan angka terakhir ganjil di plat nomornya. Begitupula saat tanggal genap, hanya yang berangka genap yang bisa melintas.
Sempat pula mencuat rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar. Awalnya akan diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman dengan diuji coba pada Juli 2014. Namun, hingga kini ERP tidak terdengar lagi kabarnya.
Sepeda motor pun tak lolos dari kebijakan antikemacetan. Di beberapa jalan utama, pada 2015, kendaraan roda dua dikanalisasi dalam satu lajur. Namun, usai uji coba, program ini tidak dilanjutkan. Beberapa kalangan menganggap kanalisasi itu justru mempersempit lebar jalan.
Selang setahun, diluncurkanlah kebijakan yang lain untuk sepeda motor. Kali ini roda dua dilarang melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Program tersebut hingga kini masih diberlakukan.
Belakangan, di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat, muncul wacana perluasan kawasan pelat kendaraan ganjil-genap, termasuk perluasan larangan sepeda motor. Sayangnya rencana tersebut mendapatkan respons negatif dari para pengguna jalan. Bahkan, sempat pula muncul ancaman demonstrasi bila perluasan larangan motor diberlakukan.
Teranyar, penegakkan aturan larangan parkir di bahu jalan, hingga ke kawasan hunian. Bahkan, rencananya, regulasi itu diperkuat dengan kebijakan wajib memiliki garasi –bagi pemilik kendaraan roda empat.
Pakar tata kota Nirwono Joga mengaku tidak masalah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, yang dia sayangkan, langkah-langkah yang diambil sering kali tidak menyentuh akar persoalan.
"Hanya untuk menyelesaikan masalah di hilir. Tapi tidak di hulu, sebagai persoalan mendasar," tutur Joga saat berbincang dengan medcom.id, Senin, 18 September 2017.
Yang diharapkan Joga, Jakarta seharusnya berani mengambil kebijakan yang sangat strategis dan makro, yakni, menata ulang kotanya. “Inilah persoalan intinya.”

FOTO: Suasana kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (ANTARA)
Inkonsistensi
Meski infrastruktur untuk transportasi massal gencar dibangun, tapi, bagi Joga, bila kotanya tidak ditata ulang, permasalahan yang sama akan terus muncul.
"Caranya, Gubernur cukup membaca sedikit tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) DKI 2030, termasuk rencana kecil tata ruangnya. Dengan begitu pemerintah tahu, sampai 13 tahun ke depan kota ini mau diapakan," ucap Joga.
Bila sudah mengetahui arah pembangunannya, program-program yang mendukung perlu dibuat dan dimulai segera. Dan yang terpenting, sambungnya, kebijakan yang dilakukan tidak sektoral. Diperlukan sinergi antar dinas dan instansi lainnya.
Bila dilihat dari RTRW DKI Jakarta, masyarakat seharusnya didekatkan ke pusat kota –bukan justru terlempar ke pinggir jauh Jakarta. Tujuannya, masyarakat dekat dengan lokasi aktifitas sehari-hari tanpa perlu berkendara.
"Buat apa motor atau mobil, kalau sehari-hari, untuk antar sekolah, belanja, kantor, semua cukup jalan kaki atau sepeda. Titik-titik itu yang seharusnya dikembangkan di Jakarta," ucap Joga.
Tapi kenyataannya, tengah kota sudah dikuasai apartemen kelas atas yang harganya tak tersentuh kelas menengah ke bawah. Padahal, kelompok masyarakat inilah yang mobilitasnya tinggi.
Sementara itu, apartemen murah, rumah susun, atau kampung susun, justru terpinggirkan. "Sekarang wajar bila pekerja di Jakarta datang dari pinggir jauh, kemacetan terjadi," ujarnya.
Dari sisi transportasi yang dikembangkan, seperti MRT, LRT, Busway, KRL, bila mengacu pada RTRW, seharusnya lebih difungsikan sebagai penghantar ke wilayah pinggir Jakarta. Bukan sebaliknya, sebagai penghantar masyarakat dari pinggir ke pusat-pusat kota.
Kini, seandainya Pemprov mau konsisten dengan RTRW-nya sendiri, dan dikerjakan dengan koordinasi yang baik antar sektor, tahun 2030 masalah kemacetan bisa terkurangi.
Masalahnya, dari dahulu, gubernur yang menjabat jarang sekali ada yang berdiri tegas di atas RTRW Jakarta.
"Sebagai contoh, LRT yang kini sedang dibangun, di kuningan itu, sebenarnya tidak ada di dalam RTRW kita. Itu (pembangunan LRT) melanggar tata ruang. Tapi, menurut mereka tidak masalah, karena dianggap proyek nasional." ucap Joga.
Selama 40 tahun terakhir, pembangunan Jakarta kerap menegasikan RTRW yang ditetapkan. Sebaliknya, setelah pembangunannya selesai, barulah RTRW itu direvisi, atau bahkan “diputihkan” dengan penerbitan RTRW periode berikutnya.
"Kebijakannya fokus di hilir. Jadi tidak aneh kalau (kebijakannya) seperti gali lubang tutup lubang. Bongkar-pasang," tandas Joga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News