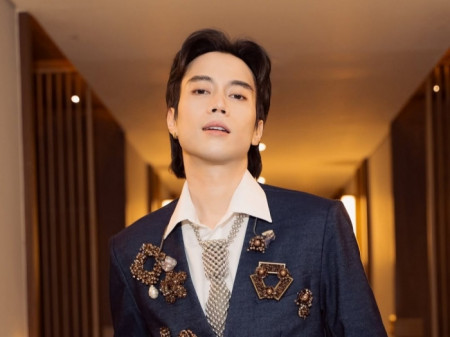PEKAN lalu, di forum ini saya menulis bahwa tidak ada yang diuntungkan perang, bahkan negara yang sedang berperang itu sendiri. Hari-hari ini, saya makin yakin bahwa hanya kerugian demi kerugianlah yang dituai dari perang.
Serangan Rusia ke Ukraina, yang terus-menerus terjadi, dengan cepat menggoreskan luka global yang dalam. Warga dunia, termasuk Indonesia, mulai merasakan dampak superperih akibat perang Rusia-Ukraina tersebut. Harga minyak mentah dunia jenis brent untuk pengiriman Mei, misalnya, sudah menembus lebih dari US$129 per barel. Itu harga tertinggi dalam kurun satu setengah dekade terakhir.
Bahkan, sejumlah analis memperkirakan harga minyak bisa melambung melampaui US$150 per barel jika perang Rusia-Ukraina tidak kunjung dihentikan. Sejak ketegangan di negara bekas Uni Soviet itu terjadi, harga minyak sudah naik 60%. Kondisi itu tak lepas dari rencana Amerika dan sekutu mereka melarang impor minyak dari Rusia.
Padahal, Rusia ialah negara dengan produksi minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Data British Petroleum Statistical Review of World Energy 2021 menunjukkan Rusia memproduksi 524,4 juta ton minyak atau 12,6% dari total produksi minyak global 2020. Produksi itu setara dengan lebih dari 10,5 juta barel minyak mentah per hari.
Bagi Indonesia, naiknya harga minyak dunia lebih menjadi musibah ketimbang berkah. Dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi minyak nasional hampir dua kali lipat produksi. Konsumsi minyak kita sekitar 1,45 juta barel per hari. Di sisi lain, produksi minyak nasional hanya 800 ribu barel per hari.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia pasti keteteran menghadapi situasi melambungnya harga 'emas hitam' dunia itu. Cadangan devisa kita juga pasti tergerus. Fiskal kita juga terganggu karena defisit APBN bakal membengkak. Pasti ada biaya puluhan triliun rupiah untuk menambah biaya subsidi minyak. Apalagi, dalam APBN, patokan harga minyak dunia disahkan pada angka US$63 per barel.
Di lapangan, naiknya harga minyak mentah langsung berimbas pada naiknya harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi di SPBU sudah naik lebih dari 15% dalam sepekan terakhir. Bisa diprediksi, harga BBM masih akan melambung pada April hingga Mei mendatang. Naiknya harga BBM pasti berefek domino pada naiknya harga-harga kebutuhan lainnya, yang dalam sebulan terakhir memang sudah naik.
Sebagian masyarakat yang sudah kencang ikat pinggangnya sudah sulit lagi untuk dianjurkan mengencangkan ikat pinggang. Mereka malah merindukan pelonggaran ikat pinggang karena virus korona makin terkendali. Namun, yang muncul justru meranggasnya daya beli karena 'disiram' melonjaknya harga minyak dunia.
Serangan Rusia ke Ukraina juga membuat harga gandum dan beras dunia mulai terkerek. Harga gandum dunia sudah mencapai US$11 per bushel, level harga tertinggi sejak 2008. Rusia sebagai pemasok gandum terbesar dunia mulai menahan pasokan mereka.
Dengan pasokan gandum yang mengetat seperti itu, dunia mulai berpaling ke beras. Alhasil, harga beras dunia mulai naik 4,2% menjadi US$16,89 per 100 pounds. Harga beras juga melaju naik 11% dalam dua pekan terakhir. Padahal, beras merupakan komoditas 'panas', khususnya bagi Indonesia. Naiknya harga beras yang tidak terkendali memicu ketidakstabilan politik.
Naiknya harga beras juga berpotensi diikuti kenaikan harga-harga komoditas pertanian lainnya. Itu terjadi lantaran harga pupuk dunia juga kian mendaki. Lagi-lagi, itu juga buah dari perang Rusia-Ukraina. Sejak 2 Februari hingga 1 April, Rusia melarang ekspor amonium nitrat, bahan utama pupuk nitrogen, demi memproteksi petani dalam negeri mereka.
Tahun lalu, Tiongkok juga menyetop pasokan fosfat ke pasar global, juga dengan alasan memproteksi petani mereka. Dampaknya, harga pupuk urea dan NPK yang bersumber dari fosfat meroket hingga 100%. Ujung-ujungnya, harga kebutuhan pangan berbasis pertanian akan susah turun.
Kiranya, ancaman kepedihan akibat pemuasan nafsu serakah yang tidak kunjung padam ini belum akan berakhir dalam waktu singkat. Meja-meja perundingan masih kosong-melompong. Belum tebersit niat bermufakat mengakhiri perang.
Yang riuh justru teriakan 'kemenangan' bersabung dengan jeritan kesengsaraan. Bara masih panas menyala. Yang ada masih tekad bulat untuk melumat. Apakah 'kiamat' memang sudah dekat?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Abdul Kohar
Dewan Redaksi Media Group