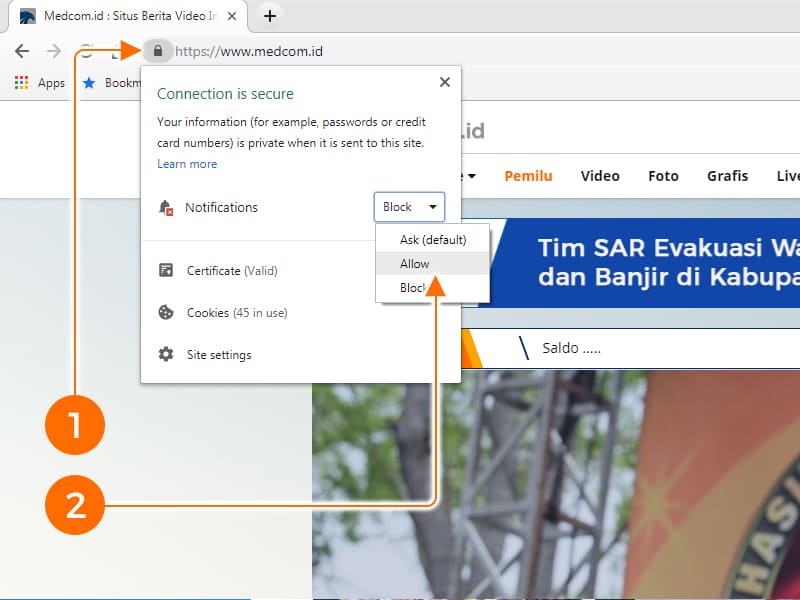TIADA lelah berbenah, pemerintah terus 'menyempurnakan' sejumlah aturan dan kebijakan untuk memastikan swasembada daging sapi bisa diraih pada 2017.
Selain membenahi kelemahan penetapan kuota impor sapi bakalan dan daging, kapal khusus ternak telah diluncurkan.
Untuk memastikan pasokan daging sapi di pasar mencukupi, lewat paket kebijakan ekonomi I dan IX, sumber pemasukan diperlonggar, yakni dari country base menjadi zone base.
Ada juga kebijakan Permentan 58/2015 yang membebaskan impor daging variety meat, dan Permenkeu 267/2016 tentang Pemberlakuan PPN yang hanya berumur 15 hari dan dicabut kembali.
Ini semua untuk memastikan pasokan cukup.
Dari semua kebijakan itu, salah satu yang menarik (dan kontroversial) adalah relaksasi sumber pasokan daging, yakni dari semula berbasis negara jadi zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).
Beleid ini memungkinkan impor dari zona bebas PMK meski negara itu belum bebas PMK.
Kebijakan itu didasari alasan jika ketersediaan daging terjamin dan harganya terjangkau tidak akan menciptakan instabilitas di pasar.
Harga daging yang stabil akan membantu pemerintah mengendalikan inflasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu penyumbang utama inflasi ialah pangan, salah satunya daging.
Agar prinsip kehati-hatian tetap terjaga, pemerintah menetapkan Pulau Naduk, Bangka Belitung, yang berstatus hutan produksi sebagai pulau karantina.
Pulau ini akan menampung sapi-sapi indukan impor dari negara yang belum bebas PMK.
Sapi indukan ini untuk menambah kekurangan yang ada agar bisa menjadi basis produksi yang sustain.
Perangkat amdal dan detail desain tuntas tahun ini.
Bangunan fisik dimulai pada 2017.
Pembangunan fisik meliputi kandang, armada kapal/pelabuhan, serta akses jalan khusus.
Kebijakan ini beralas pada UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hasil revisi UU No 18/2009.
Sebagai wujud relaksasi sumber pasokan daging, Kementerian Pertanian mengubah Permentan No 139/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/Olahannya ke dalam Wilayah RI jadi Permentan 58/2015.
Masalahnya, UU 41/2014 dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Yang diuji Pasal 36C, yakni Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah NKRI dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
Pasal ini jelas-jelas tak memperhatikan keputusan judicial review MK atas UU 18/2009.
Semula, Pasal 59 Ayat 2 UU 18/2009 membolehkan pemasukan produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.
Lewat uji materi, para pihak yang terkait dengan peternakan, pasal ini diubah MK menjadi "berasal dari suatu negara" bukan berasal dari zona dalam suatu negara.
Salah satu pertimbangannya ialah kaidah 'maksimum sekuriti'.
Memang antara Pasal 36C dan Pasal 59 ayat 2 ada perbedaan frasa ternak ruminansia indukan dan produk hewan.
Namun, perbedaan komoditas pada UU 18/2009 dengan UU 41/2014 tidak serta-merta menyebabkan rendahnya risiko berjangkitnya penyakit hewan menular.
Sebenarnya upaya pemerintah merevisi UU 18/2009 sudah muncul tidak lama setelah ada putusan MK pada 27 Agustus 2010.
Alasannya, pendekatan country base membuat Indonesia tidak leluasa mengimpor daging (dan sapi) dari berbagai negara.
Karena tidak banyak negara bebas PMK, Indonesia amat tergantung pasokan daging (dan sapi) dari Australia (dan Selandia Baru).
Sebenarnya, di luar Australia dan Selandia Baru, Indonesia bisa mengimpor daging dan sapi dari AS, Kanada, dan Jepang yang bebas PMK.
Indonesia lebih banyak mengimpor daging dan sapi dari Australia lantaran pertimbangan kedekatan geografis sehingga harga daging dan sapi lebih murah.
Memang benar harga daging dan sapi impor dari negara yang bebas PMK lebih mahal dari negara yang masih endemik PMK.
AS misalnya, mengimpor daging sapi dari Australia dengan harga premium 30% lebih tinggi daripada daging sapi asal negara tertular.
Namun, ini tidak bisa menjadi justifikasi untuk melonggarkan aturan impor ternak, terutama sapi.
Jika PMK kembali berjangkit, kerugian ekonomi yang ditimbulkan tak ternilai besarnya.
Kerugian ekonomi Indonesia menangani PMK selama 100 tahun (1887-1986), menurut Ditjen Peternakan (2002), mencapai US$ 1,66 miliar (Rp19,92 triliun).
Bagi negara-negara bebas PMK, termasuk Indonesia, sangat penting memastikan impor ternak dan produknya bersumber dari negara dengan status sama.
Perdagangan ternak hidup tidak dianjurkan antara negara bebas dan negara endemik PMK.
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mengatur standar dan persyaratan kesehatan hewan impor ternak dan produknya untuk mengawal perdagangan yang aman di seluruh dunia.
Menurut OIE, impor ternak sapi bisa saja dilakukan dari negara yang memiliki zona bebas PMK, tapi perlu persyaratan tambahan yang ketat, baik di negara eksportir maupun negara importir (Naipospos, 2015).
Syarat itu pula yang direkomendasikan Tim Analisis Risiko Independen (TARI) yang dibentuk Kementerian Pertanian (Kementan, 2008).
Tindakan sanitasi di negara pengekspor, yakni impor dibatasi hanya pada daging beku tanpa tulang yang telah dilakukan pemisahan kelenjar limfa, impor tidak termasuk jeroan dan daging variasi, dan impor dari zona bebas PMK tanpa vaksinasi harus diprioritaskan.
Selain itu, impor dari zona bebas PMK dengan vaksinasi bisa dilakukan dengan syarat 3 tahun terakhir tak terjadi wabah PMK, pengangkutan ternak dari peternakan tidak boleh singgah, dan rumah potong hewan (RPH) yang digunakan harus disetujui pengimpor.
Sanitasi di negara pengimpor meliputi peningkatan kemampuan teknis dan fasilitas diagnostik karantina; penguatan sistem kesehatan hewan; peningkatan kemampuan teknis dan fasilitas laboratorium untuk pengujian PMK; surveillance dan monitoring di wilayah distribusi daging impor, termasuk, sosialisasi dan simulasi kesiap-siagaan darurat veteriner dari bahaya PMK; penyediaan dana tanggap darurat PMK siap pakai; pembatasan jumlah impor daging beku tanpa tulang; sertifikasi, audit dan pengawasan fasilitas usaha (cold storage, dan lain-lain); peningkatan sistem pengawasan peredaran daging; serta peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat atas penanganan limbah daging.
Ini menunjukkan impor daging sapi dari negara belum bebas PMK dimungkinkan dengan syarat: sistem pengamanan (UU Veteriner), infrastruktur (otoritas veteriner dan SDM), dan pelayanan veteriner di Indonesia dibenahi terlebih dahulu.
Tanpa itu, dengan sendirinya impor tidak bisa dilakukan karena ini sama saja dengan mengancam target swasembada daging pada 2017.
Impor daging dari zona belum bebas PMK amat berisiko karena sistem dan infrastruktur di Indonesia masih banyak loophole.
Pertama, sistem kesehatan hewan lemah, terutama tak adanya garis komando langsung dari pusat ke daerah dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit.
Kedua, dana tanggap darurat tak tersedia tiap saat.
Ketiga, kemampuan teknis dan fasilitas diagnostik untuk mendeteksi virus PMK pada hewan dan produk hewan di karantina di pelabuhan pemasukan belum ada.
Keempat, laboratorium diagnostik untuk mendeteksi virus PMK dengan kemampuan teknis dan fasilitas yang memadai belum tersedia (TARI, 2008).